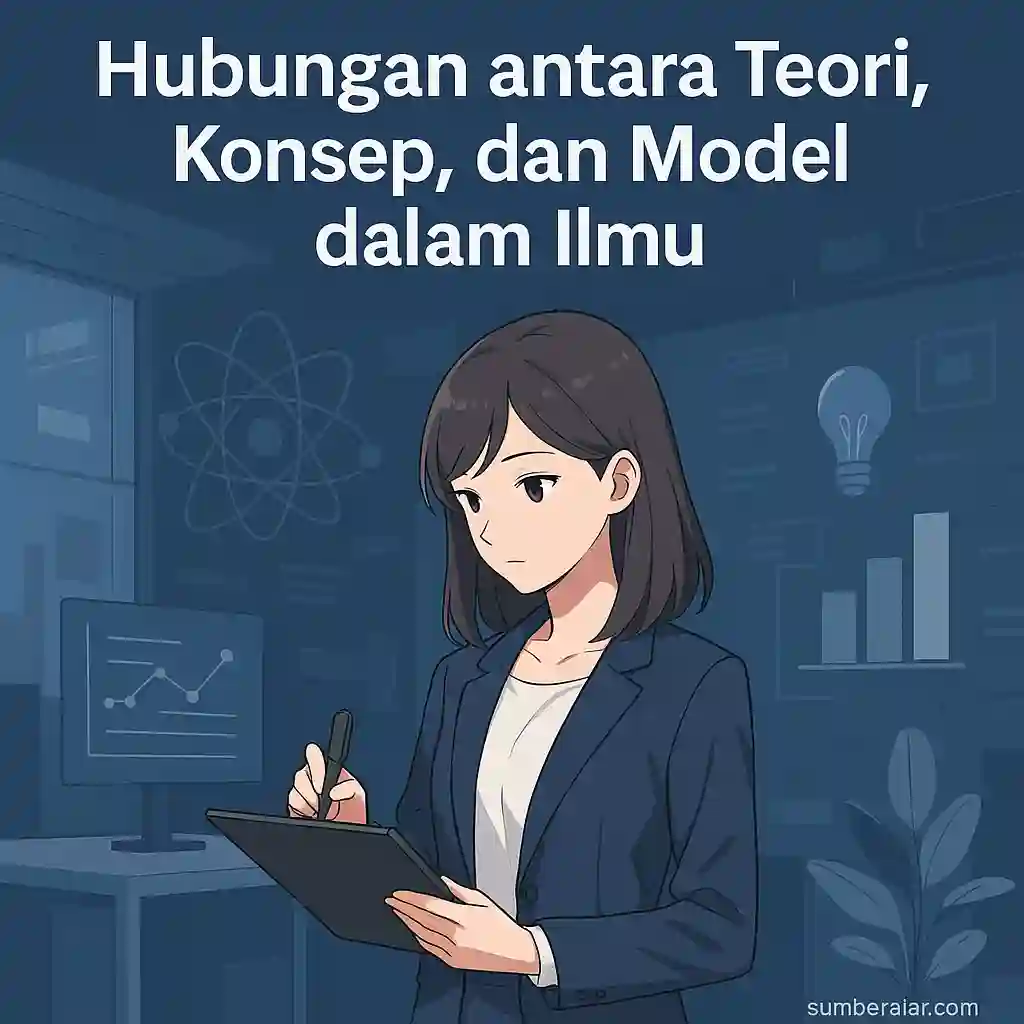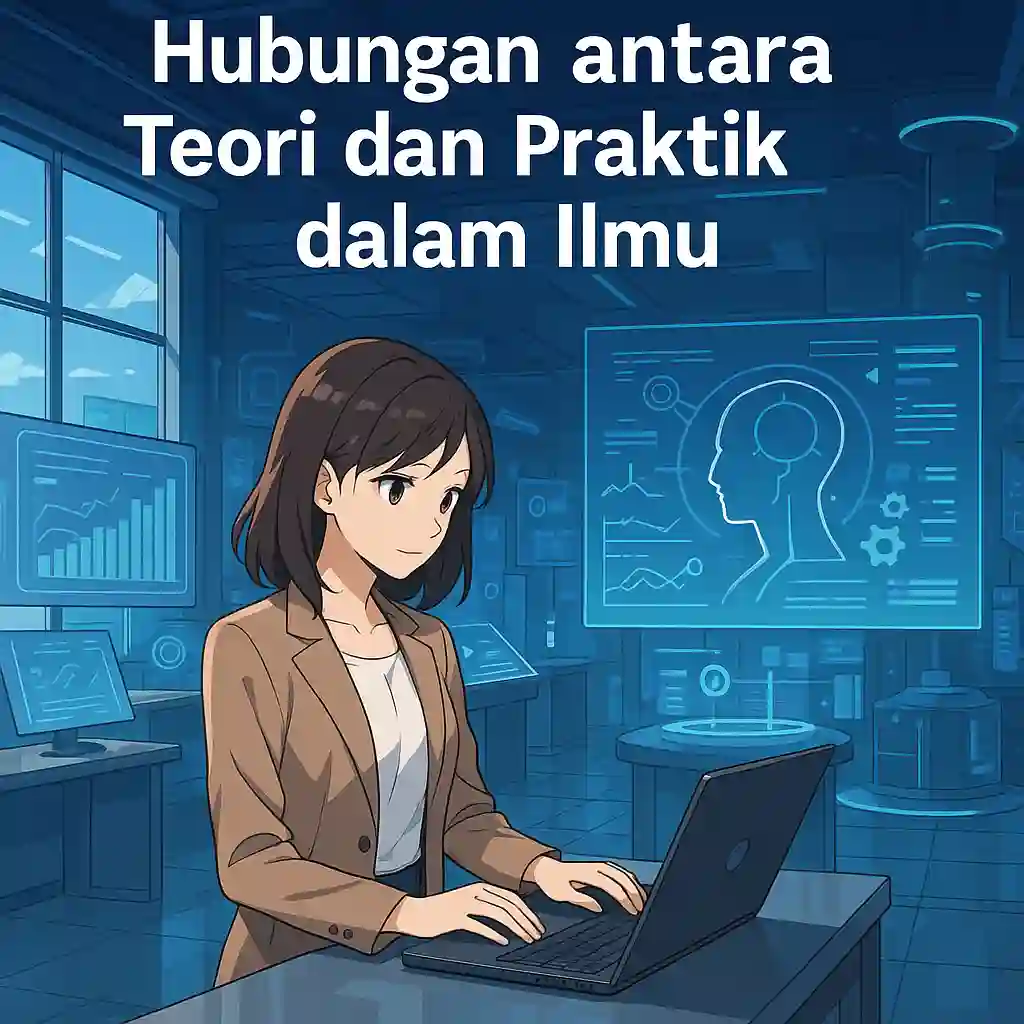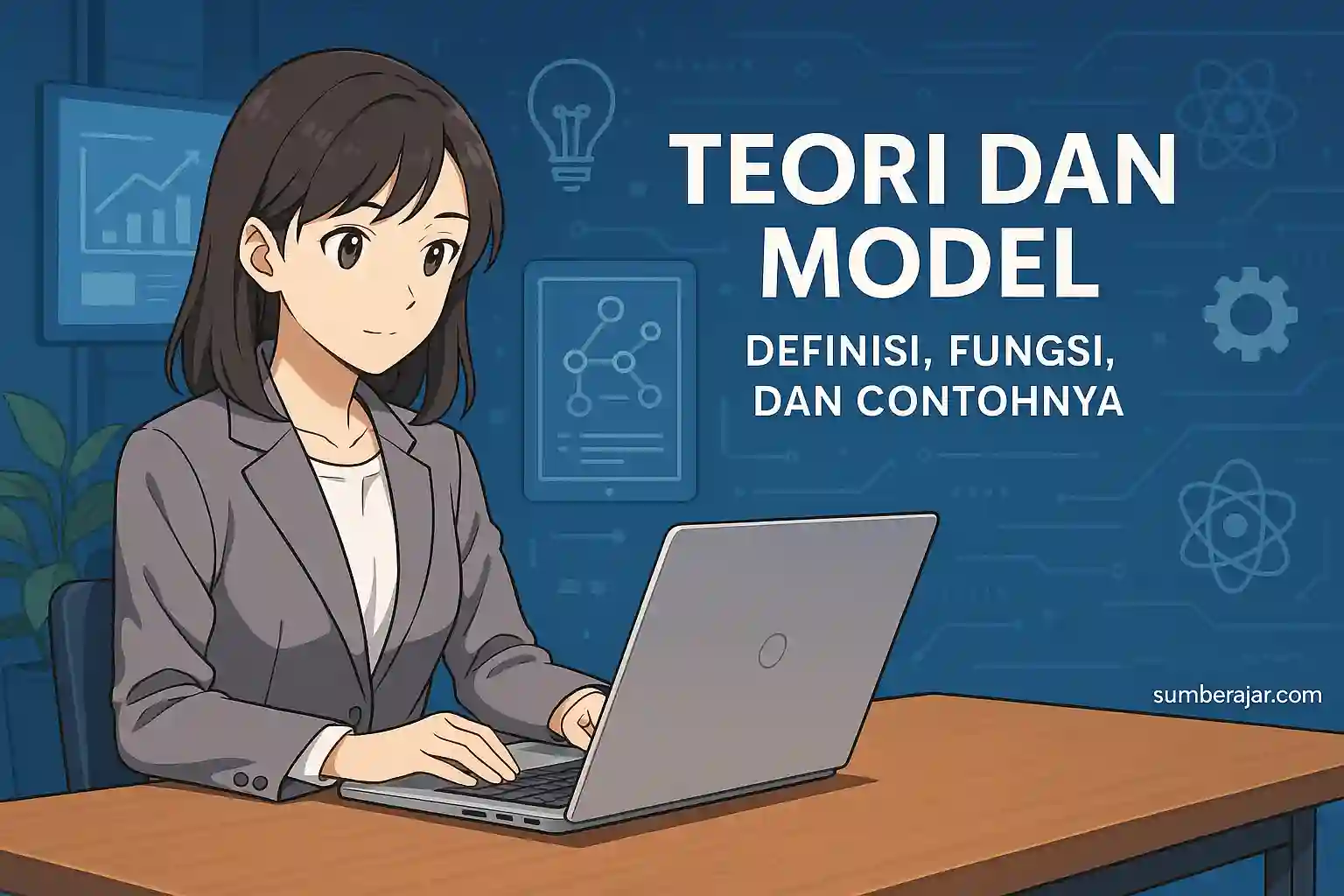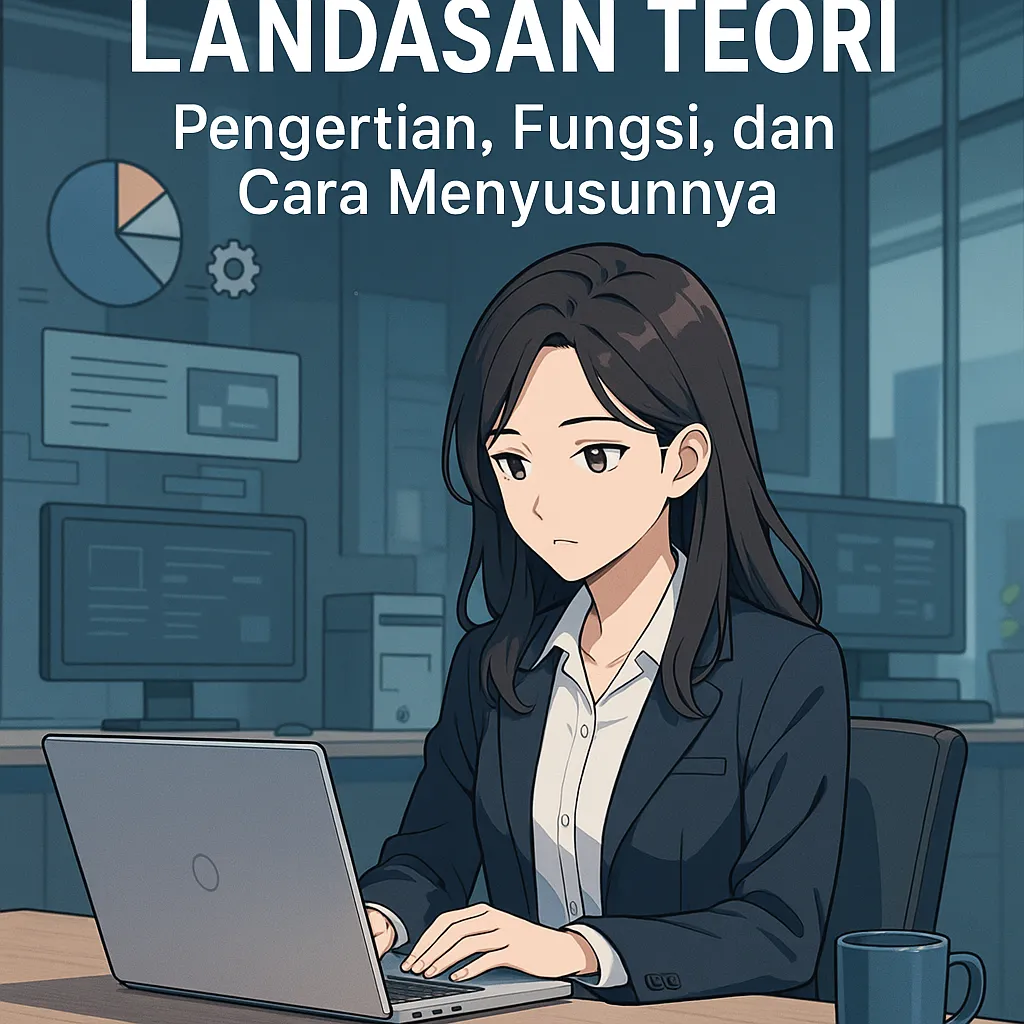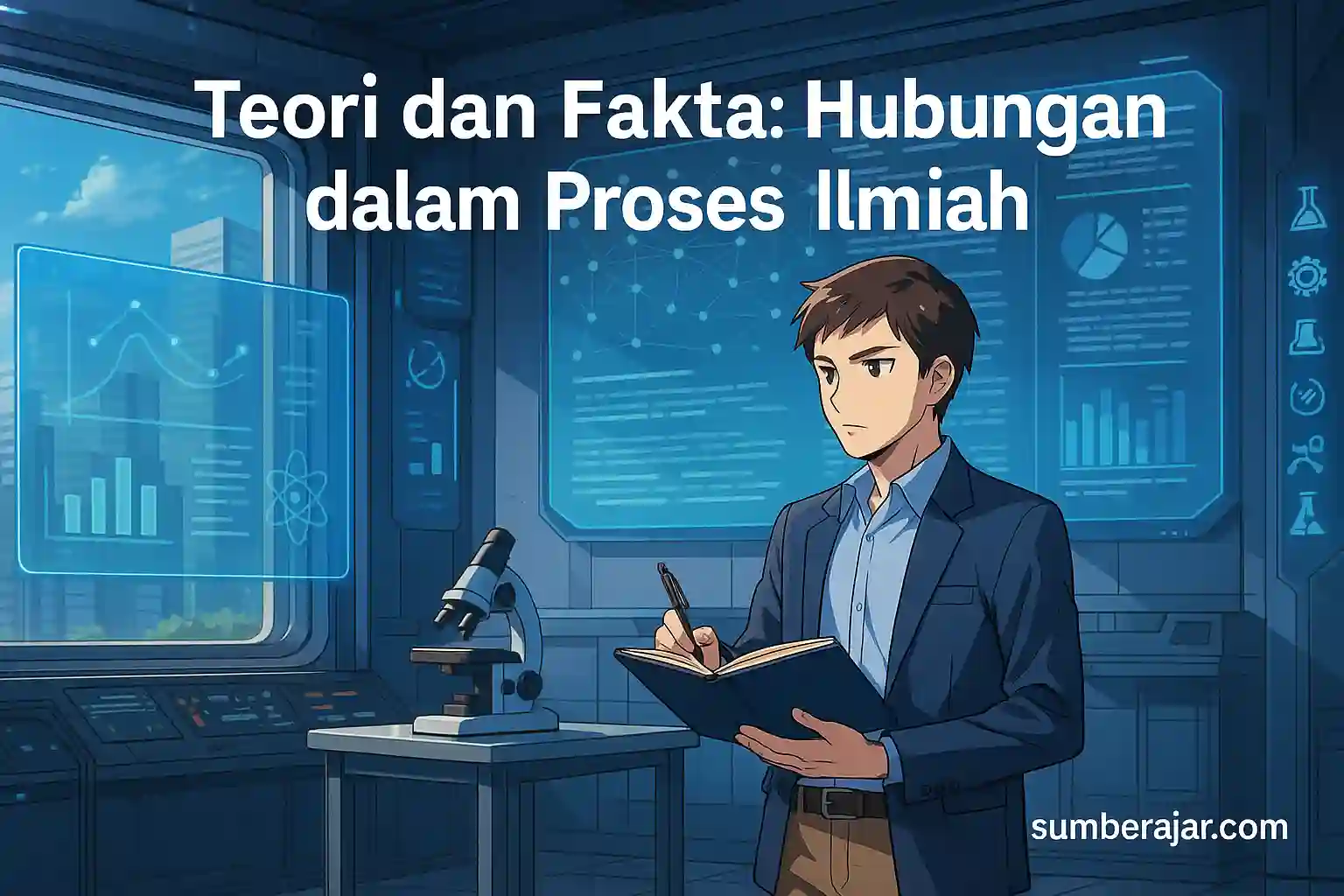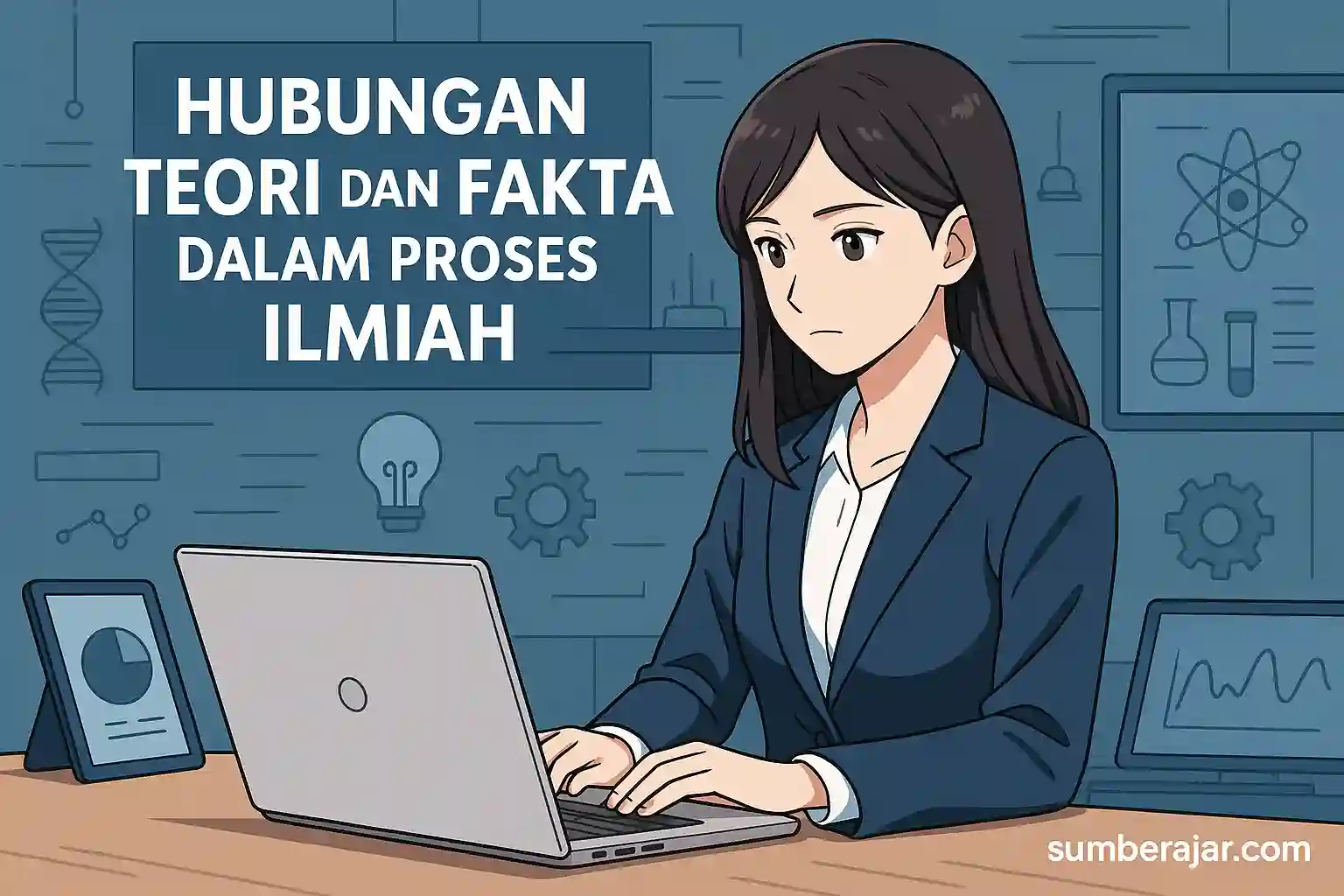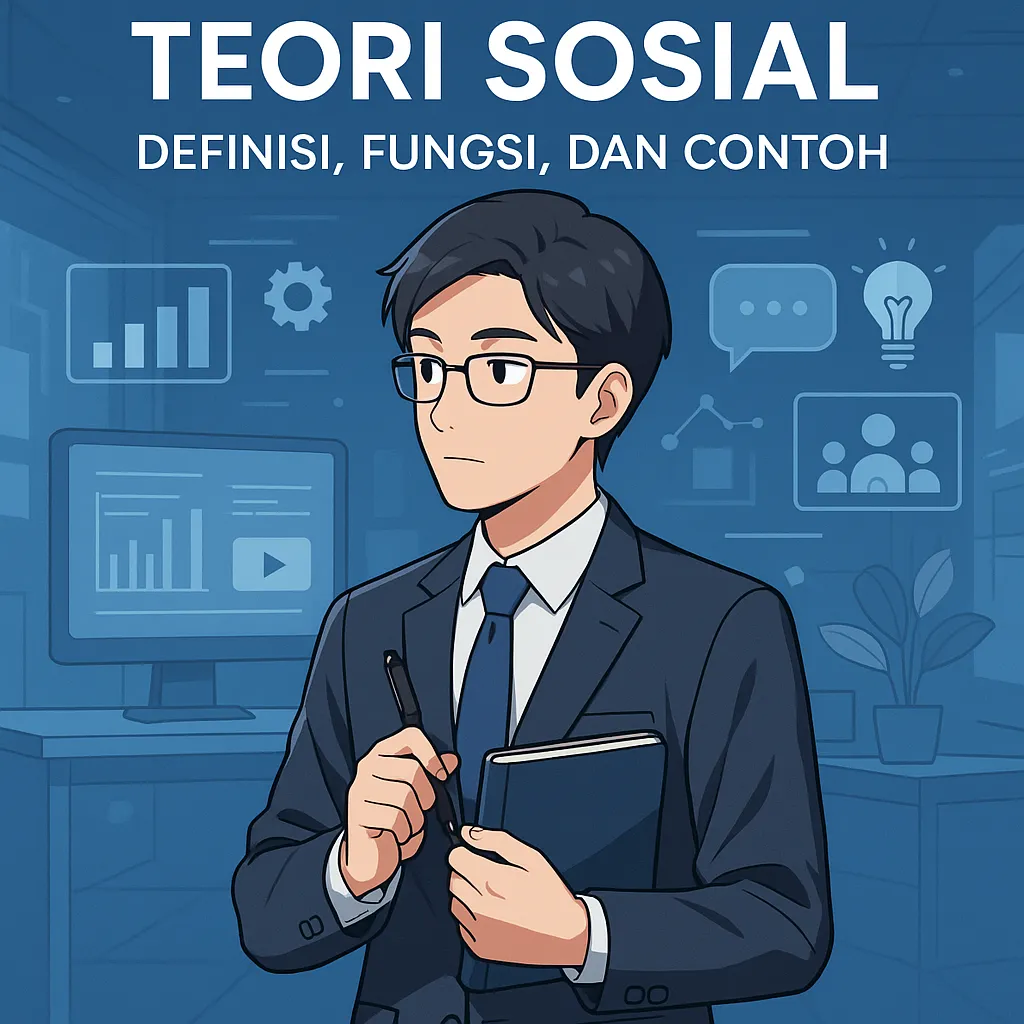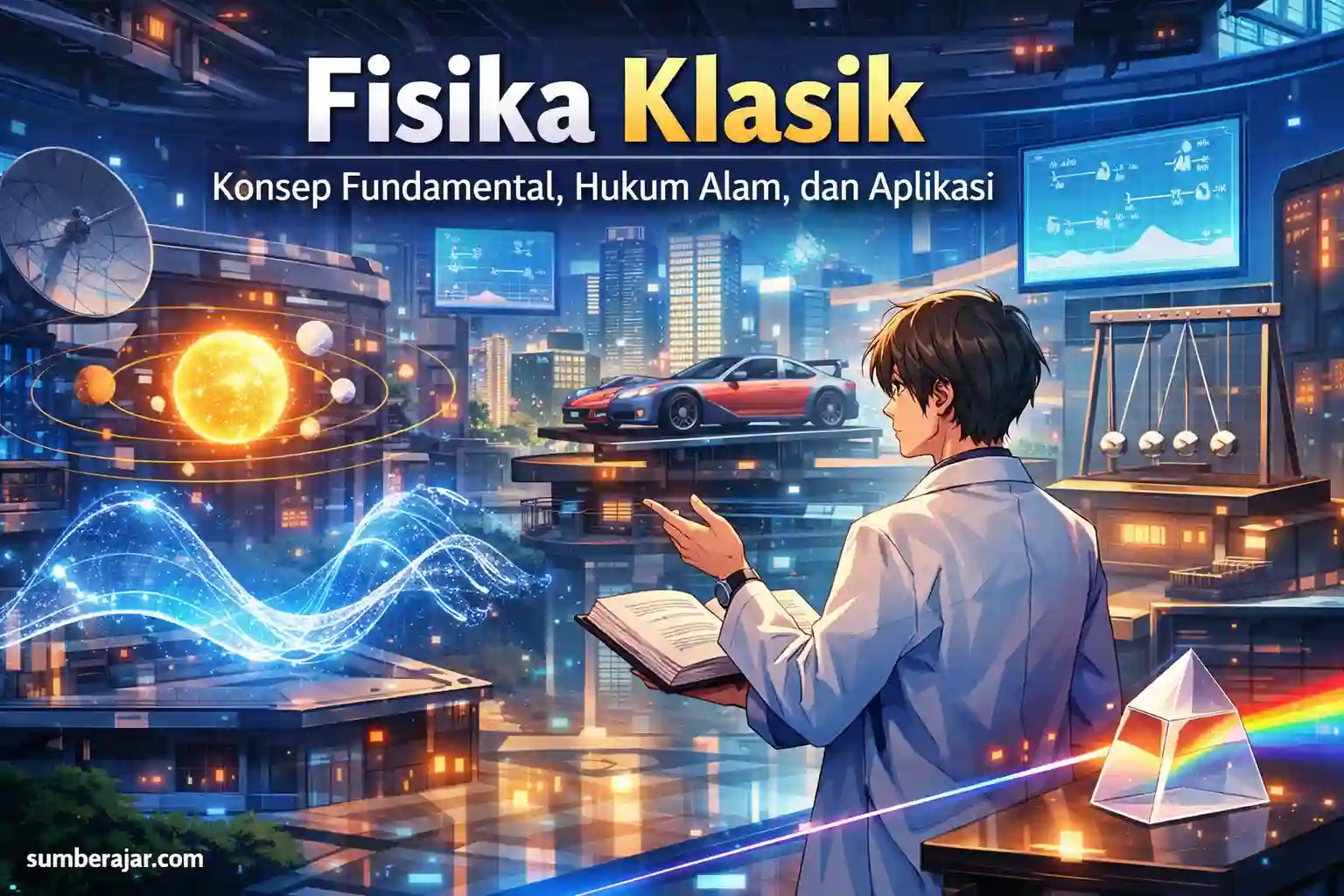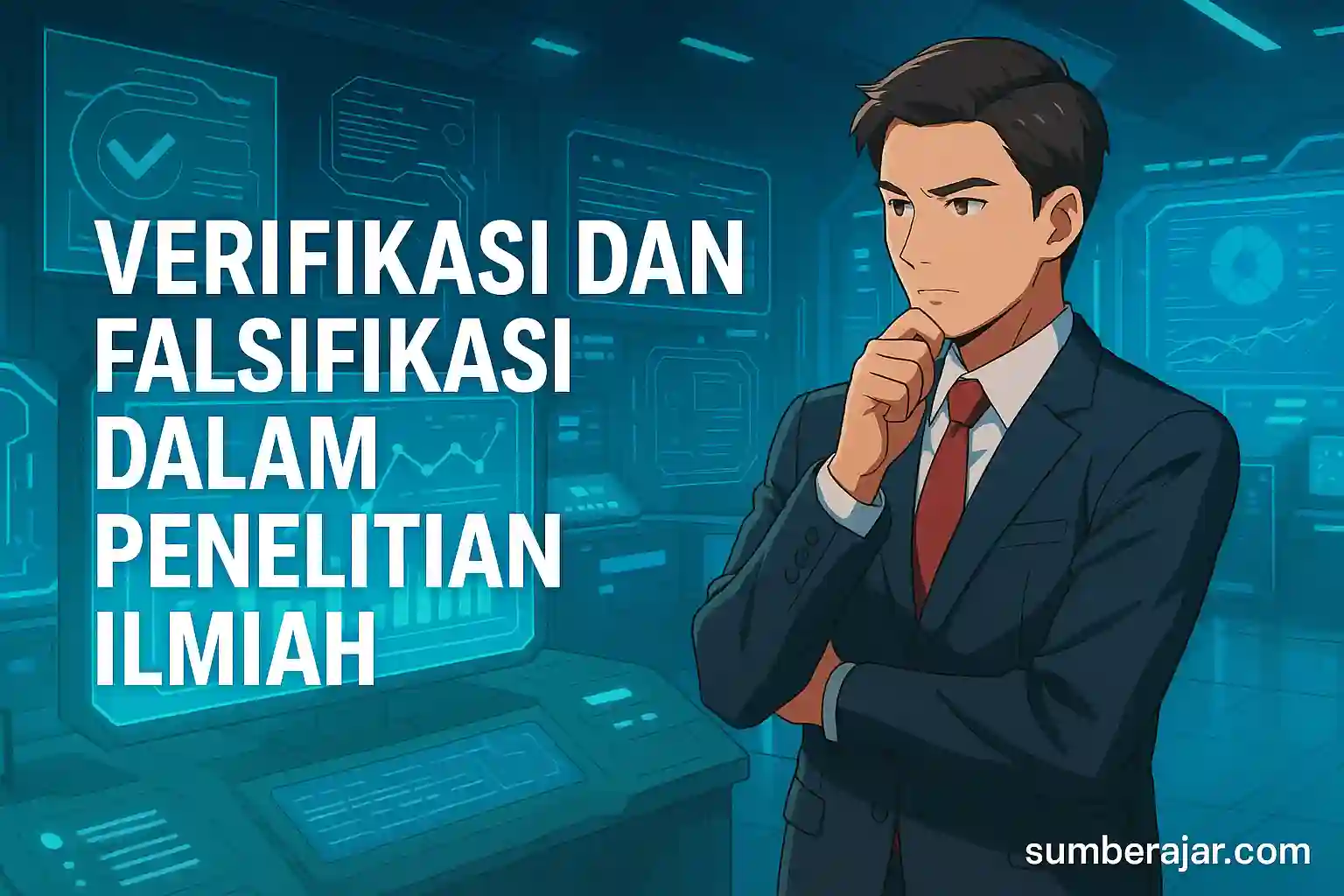Teori Relativitas Sosial dalam Kajian Ilmiah
Pendahuluan
Dalam kajian ilmu sosial, fenomena “relativitas” telah menjadi salah satu konsep penting untuk memahami bagaimana realitas sosial dibentuk, diinterpretasi, dan berubah oleh subjek sosial dalam konteks budaya, ekonomi, dan politik. Istilah “relativitas sosial” dalam artikel ini dipahami sebagai gagasan bahwa nilai-nilai, norma, makna sosial, dan realitas bersama tidak bersifat mutlak atau tunggal, melainkan tergantung pada konteks sosial, sejarah, budaya, dan struktur sosial di mana individu atau kelompok berada. Kajian ilmiah terhadap relativitas sosial bukan hanya memfokuskan pada aspek budaya (relativisme budaya) tetapi juga bagaimana konstruksi realitas sosial, persepsi, dan interpretasi sosial mempengaruhi pembentukan struktur dan dinamika sosial. Dengan demikian, memahami teori relativitas sosial akan membantu peneliti maupun praktisi sosial untuk melihat fenomena sosial dengan lebih kritis dan kontekstual, serta menghindari penjelasan yang terlalu universal atau deterministik. Artikel ini kemudian akan membahas definisi teori relativitas sosial secara umum, dalam KBBI, dan menurut para ahli; diikuti dengan pembahasan sub-judul utama seperti kerangka teoritis relativitas sosial, aplikasi dalam penelitian ilmiah, dinamika relasi sosial dan kekuasaan, serta tantangan metodologis. Akhirnya akan ditarik kesimpulan yang mengikat.
Definisi Teori Relativitas Sosial
Definisi Teori Relativitas Sosial Secara Umum
Secara umum, teori relativitas sosial dapat dianggap sebagai suatu kerangka pemikiran dalam sosiologi dan ilmu sosial yang menegaskan bahwa perubahan sosial, nilai-norma, realitas sosial, dan pengetahuan sosial bersifat relatif terhadap kondisi sosial, budaya, dan historis. Artinya, apa yang dianggap “normal”, “benar”, atau “valid” dalam satu kelompok atau konteks sosial belum tentu demikian dalam kelompok lain atau dalam konteks historis yang berbeda. Pendekatan ini memfokuskan pada perspektif bahwa realitas sosial dibentuk oleh interaksi sosial, konstruksi simbolik, dan faktor konteks,sehingga tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang tunggal. Misalnya, dalam penelitian sosial sering muncul bahwa interpretasi suatu fenomena seperti kemiskinan, stigma sosial, atau mobilitas sosial akan berbeda ketika dilihat dari subjek yang berbeda latar belakangnya. Hal demikian sejalan dengan gagasan bahwa “kenyataan” bukanlah sesuatu yang bebas nilai atau bebas konteks, melainkan dibentuk oleh pengetahuan, interaksi sosial, dan struktur sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh penulis bahwa “kenyataan … bersifat plural, karena adanya relativitas sosial dari apa yang disebut pengetahuan dan kenyataan.” [Lihat sumber Disini - researchgate.net]
Definisi Teori Relativitas Sosial dalam KBBI
Untuk definisi dalam KBBI (KBBI – Kamus Besar Bahasa Indonesia) secara spesifik mungkin tidak terdapat entri “teori relativitas sosial” sebagai istilah yang baku dalam sosiologi; namun kita dapat menarik definisi komponen-komponennya. Misalnya, “relatif” dalam KBBI diartikan sebagai “tergantung kepada sesuatu yang lain; tidak mutlak; bersifat perbandingan” (KBBI daring). Dengan demikian, “relativitas sosial” dalam makna umum dapat diartikan sebagai “keadaan atau sifat sosial yang bergantung atau berbeda menurut konteks, tidak bersifat mutlak”. Sehingga secara terjemahan bebas, teori relativitas sosial adalah “teori yang menyatakan bahwa kondisi, nilai, norma atau makna sosial seseorang atau kelompok bergantung pada konteks sosial tertentu dan tidak dapat diberlakukan secara universal”. Untuk keperluan artikel ini, definisi ini dijadikan dasar agar pembaca memahami bahwa aspek sosial tidak selalu identik antar konteks.
Definisi Teori Relativitas Sosial Menurut Para Ahli
Berikut beberapa pendapat ahli terkait gagasan yang dapat dikaitkan dengan teori relativitas sosial:
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa realitas sosial adalah konstruksi bersama yang dihasilkan dari proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi dalam interaksi sosial. Mereka menyatakan bahwa apa yang dianggap “realitas” oleh individu adalah hasil konstruksi sosial yang terus-menerus dijalin melalui interaksi dan dipengaruhi oleh habitus atau pengetahuan kolektif. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
- Dalam kajian paradigma penelitian sosiologi, Abdul Malik (2021) menyatakan bahwa paradigma konstruktivisme atau interpretivisme secara ontologis bersifat relativistis, yang berarti realitas sosial dihasilkan melalui konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial yang bersifat lokal dan spesifik sehingga tidak bisa digeneralisir begitu saja. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
- Dalam kajian “relativitas budaya” karya A. Aziz (2022) dijelaskan bahwa teori relativitas budaya memandang bahwa setiap individu atau kelompok berbudaya memiliki standar nilai sendiri sesuai konteks latar belakang budaya masing-masing, sehingga tindakan atau tradisi suatu budaya dipandang berasal dari kerangka nilai lokal dan bukan dari kerangka universal. [Lihat sumber Disini - e-journal.iainptk.ac.id]
- Dalam tulisan yang membahas konstruksi realitas sosial di Indonesia, Y.C. Pamungkas (2024) menyatakan bahwa media massa dan media sosial di Indonesia memainkan peran dalam membingkai realitas sosial yang kemudian diterima publik, dan bahwa makna sosial sering bersifat relatif tergantung pada konstruksi media. [Lihat sumber Disini - jayapanguspress.penerbit.org]
Dengan demikian, kombinasi pemikiran para ahli ini memperkuat gagasan bahwa teori relativitas sosial mengandung unsur: konstruksi realitas sosial, relativitas nilai/norma dalam konteks sosial dan budaya, serta peran aktor sosial (individu/kelompok/media) dalam memproduksi makna sosial.
Kerangka Teoritis Relativitas Sosial
- Konstruksi Realitas Sosial
Kerangka ini menekankan bahwa realitas sosial bukan hanya “apa adanya”, melainkan dibentuk oleh proses interaksi sosial, internalisasi norma, eksternalisasi makna, dan objektivasi pengalaman individu menjadi kenyataan bersama. Menurut Berger & Luckmann, proses tersebut terdiri dari tahap eksternalisasi (individu mengungkapkan makna dalam interaksi sosial), lalu objektivasi (makna menjadi objek sosial yang dianggap “real”) dan kemudian internalisasi (individu menerima kembali makna sosial yang telah dibentuk). [Lihat sumber Disini - media.neliti.com] Dalam kerangka ini, relativitas sosial muncul karena tiap individu atau kelompok memiliki titik awal pengalaman, struktur sosial, pengetahuan, dan budaya yang berbeda,sehingga konstruksi realitas sosial mereka pun berbeda. - Relativitas Nilai, Norma, dan Makna Sosial
Bagian ini menunjukkan bahwa nilai dan norma sosial tidak universal melainkan bersifat kontekstual. Misalnya dalam kajian relativitas budaya disebutkan bahwa standar benar-salah, adat istiadat, moral maupun tindakan tertentu dapat berbeda dan bergantung pada latar belakang budaya masing-masing. [Lihat sumber Disini - e-journal.iainptk.ac.id] Dalam level makna sosial yang lebih luas, relativitas sosial menunjukkan bahwa interpretasi fenomena sosial seperti kemiskinan, kelas sosial, stigma, mobilitas atau bahasa akan berbeda antar kelompok dan antar kultur,yang selanjutnya berdampak pada struktur kekuasaan dan hubungan sosial. Contoh di Indonesia: penelitian mengenai variasi bahasa dan stratifikasi sosial menunjukkan bahwa penguasaan bahasa Inggris atau bahasa daerah memengaruhi persepsi status sosial dan akses ekonomi, yang merupakan salah satu manifestasi relativitas sosial dalam mobilitas sosial. [Lihat sumber Disini - journal.intelekmadani.org] - Relasi Sosial, Kekuasaan, dan Struktur
Relativitas sosial juga terkait erat dengan bagaimana struktur kekuasaan dan relasi sosial mempengaruhi makna dan realitas sosial. Struktur dominasi, hegemoni budaya, akses terhadap sumber daya, dan kontrol wacana sosial adalah bagian dari dinamika di mana relativitas muncul: kelompok yang memiliki kekuasaan dapat membentuk definisi “normal” atau “benar”, sementara kelompok subordinat mungkin memiliki konstruk realitas alternatif. Artikel-kajian paradigma sosiologi menyebutkan bahwa realitas yang dihasilkan melalui konstruksi sosial bersifat historis, lokal, dan spesifik serta tidak dapat digeneralisir. [Lihat sumber Disini - ejournal.uin-suka.ac.id] - Implikasi Metodologis dalam Kajian Ilmiah
Dalam penelitian sosial, memahami relativitas sosial mengharuskan peneliti menyadari bahwa kategori, konstruk, instrumen, dan interpretasi data tidak bersifat netral atau universal. Para peneliti harus mempertimbangkan konteks lokal, posisi subjek, nilai budaya, bahasa, dan relasi kekuasaan dalam desain penelitian, pengumpulan dan analisis data. Misalnya paradigma konstruktivisme menolak klaim universalitas pengetahuan dan menekankan bahwa realitas sosial bersifat sementara dan terlokalisasi. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
Aplikasi Teori Relativitas Sosial dalam Penelitian Ilmiah
Dalam praktik penelitian ilmiah sosial, teori relativitas sosial dapat diterapkan dalam beberapa aspek:
- Analisis nilai dan norma lokal: Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana norma sosial dipahami dan diterapkan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Sebagai contoh, penelitian mengenai relativitas budaya dalam konseling lintas budaya menunjukkan bahwa nilai etika dan tradisi berbeda antar budaya, sehingga intervensi konseling harus mempertimbangkan konteks budaya klien. [Lihat sumber Disini - e-journal.iainptk.ac.id]
- Penggunaan instrumen penelitian yang sensitif terhadap konteks: Karena realitas sosial bersifat relatif, penggunaan kuesioner, skala, atau variabel yang dikembangkan dalam satu budaya belum tentu valid di budaya lain tanpa adaptasi konteks. Peneliti harus melakukan adaptasi silang budaya, validasi lokal, dan menggunakan pendekatan kualitatif bila diperlukan.
- Interpretasi hasil penelitian dengan memperhatikan posisi sosial subjek: Sebagai contoh, penelitian terkait bahasa dan mobilitas sosial di Indonesia menyebut bahwa subjek dengan penguasaan bahasa berbeda mengalami persepsi status sosial yang berbeda,menunjukkan bahwa interpretasi data tanpa memperhatikan faktor konteks akan mengabaikan relativitas sosial. [Lihat sumber Disini - journal.intelekmadani.org]
- Refleksi terhadap hegemonia dan konstruk dominan: Penelitian yang menggunakan teori relativitas sosial akan mengkaji bagaimana konstruk dominan dalam masyarakat,misalnya definisi “sukses”, “beradab”, “modern”,diproduk oleh kelompok dominan dan bagaimana kelompok subordinat mungkin memiliki konstruk alternatif. Dengan demikian, penelitian menjadi lebih kritis terhadap status quo dan memungkinkan dekonstruksi makna sosial.
- Desain penelitian komparatif dan lintas budaya: Karena realitas sosial bersifat relatif, penelitian lintas budaya atau komparatif dapat mengeksplorasi perbedaan konstruk nilai dan norma sosial antar kelompok, wilayah, atau budaya. Hasilnya dapat memperkaya pemahaman tentang keragaman sosial serta dinamika perubahan sosial.
Dinamika Relasi Sosial dan Kekuasaan dalam Perspektif Relativitas Sosial
Teori relativitas sosial membantu memunculkan beberapa dinamika penting dalam relasi sosial dan kekuasaan:
- Penetapan “normalitas” oleh kelompok dominan: Dalam banyak masyarakat, kelompok yang memiliki posisi sosial, ekonomi atau politik yang lebih tinggi sering menetapkan norma, nilai dan definisi sosial tentang apa yang dianggap “normal”, “benar” atau “legitim”. Kelompok subordinat kemudian mungkin mengalami tekanan, marginalisasi atau stigma ketika realitas sosial mereka berbeda. Kerangka relativitas sosial membuka ruang untuk melihat bahwa definisi “normal” bukanlah universal.
- Mobilitas sosial dan konstruksi status: Karena nilai dan norma bersifat relatif, jenis-mobilitas sosial yang dianggap “naik” dalam satu konteks mungkin berbeda dalam konteks lain. Misalnya, penguasaan bahasa asing dianggap sebagai simbol status tinggi di urban Indonesia, sementara kelompok tradisional mungkin menilai aspek komunitas lokal atau budaya tradisional sebagai simbol status. Penelitian tentang stratifikasi bahasa menunjukkan bahwa variasi bahasa berhubungan dengan mobilitas sosial dan posisi/status,ini bagian dari relativitas sosial. [Lihat sumber Disini - journal.intelekmadani.org]
- Resistensi dan perubahan sosial: Kelompok yang mengalami tekanan atau marginalisasi dapat mengembangkan narasi alternatif atau realitas sosial sendiri sebagai bentuk resistensi terhadap konstruksi dominan. Dengan demikian, relativitas sosial menjadi alat analisis untuk perubahan sosial.
- Kompleksitas multi-dimensi relasi sosial: Realitas sosial tidak hanya dipengaruhi oleh satu dimensi seperti ekonomi, tetapi juga oleh budaya, gender, bahasa, teknologi, media, dan globalisasi. Teori relativitas sosial menjelaskan bahwa setiap dimensi ini membawa konteks latar belakang yang berbeda sehingga relasi sosial menjadi kompleks dan penuh variasi.
- Kekuasaan wacana dan media: Artikel terkait konstruksi realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa media massa dan media sosial berperan aktif dalam membingkai realitas sosial,yang berarti bahwa proses relativitas sosial terjadi melalui kontrol wacana, interpretasi, seleksi informasi, dan produksi simbol sosial. [Lihat sumber Disini - jayapanguspress.penerbit.org]
Tantangan Metodologis dalam Kajian Relativitas Sosial
Meskipun teori relativitas sosial menawarkan kerangka yang kaya untuk menganalisis fenomena sosial, terdapat beberapa tantangan metodologis yang harus diperhatikan oleh peneliti:
- Generalizabilitas vs kontekstualitas: Karena realitas sosial dianggap relatif, menarik generalisasi dari satu kasus ke kasus lain menjadi problematik. Peneliti perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan yang berlaku secara luas tanpa memperhatikan konteks spesifik. Artikel paradigma konstruktivisme menyebut bahwa realitas sosial bersifat lokal dan spesifik, tidak bisa digeneralisir secara lepas. [Lihat sumber Disini - ejournal.uin-suka.ac.id]
- Validitas instrumen lintas budaya: Instrumen penelitian (kuesioner, skala, indeks) yang dikembangkan di satu konteks budaya bisa saja kehilangan validitas bila diterapkan di konteks lain yang berbeda secara sosial, budaya, bahasa atau ekonomi. Adaptasi dan pre-testing menjadi penting.
- Refleksivitas peneliti: Peneliti sendiri sebagai subjek sosial memiliki posisi dan latar belakang yang bisa mempengaruhi interpretasi data. Teori relativitas sosial menuntut peneliti untuk reflektif terhadap bias sosial, budaya dan struktural yang dibawa dalam penelitian.
- Kompleksitas interaksi sosial: Karena banyak faktor yang mempengaruhi konstruk realitas sosial (budaya, sejarah, struktur ekonomi, teknologi, media), analisis menjadi kompleks dan memerlukan pendekatan multidisipliner atau gabungan metode kuantitatif dan kualitatif.
- Etika penelitian dalam konteks pluralitas: Memahami dan menghormati perspektif nilai yang berbeda dalam masyarakat menjadi esensial. Peneliti harus memastikan bahwa interpretasi tidak menyamaratakan atau mendiskreditkan kelompok budaya tertentu.
- Dinamika temporal dan perubahan sosial: Realitas sosial dan nilai sosial tidak statis,mereka berubah seiring waktu. Penelitian harus mempertimbangkan aspek historis dan perubahan sosial agar tidak terjebak dalam pemahaman yang usang atau tidak relevan.
Kesimpulan
Teori relativitas sosial menawarkan kerangka pikir yang penting dalam kajian ilmiah sosial karena menegaskan bahwa realitas sosial,termasuk nilai, norma, makna, struktur dan relasi sosial,tidak bersifat mutlak melainkan bergantung pada konteks sosial, budaya, sejarah, dan struktur kekuasaan. Melalui tiga aspek definisi (umum, KBBI, dan menurut para ahli) kita telah memahami bahwa gagasan ini menekankan konstruksi sosial, relativitas makna sosial dan pentingnya konteks. Kerangka teoritis menunjukkan bagaimana realitas sosial dikonstruksi melalui proses interaksi sosial, konstruksi makna, relasi kekuasaan dan metodologi penelitian. Aplikasi teori ini dalam penelitian ilmiah menuntut sensitivitas terhadap konteks, posisi subjek, adaptasi instrumen, serta refleksivitas peneliti. Di sisi lain, tantangan metodologis seperti keterbatasan generalisasi, adaptasi instrumen lintas budaya, kompleksitas interaksi sosial dan dinamika perubahan menjadi catatan penting agar penelitian tetap sahih dan kontekstual. Dengan demikian, bagi peneliti, praktisi sosial atau pengambil kebijakan, memahami relativitas sosial berarti membuka ruang analisis yang lebih kritis terhadap konstruk “normalitas” dan “realitas” dan memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap keragaman sosial masyarakat.