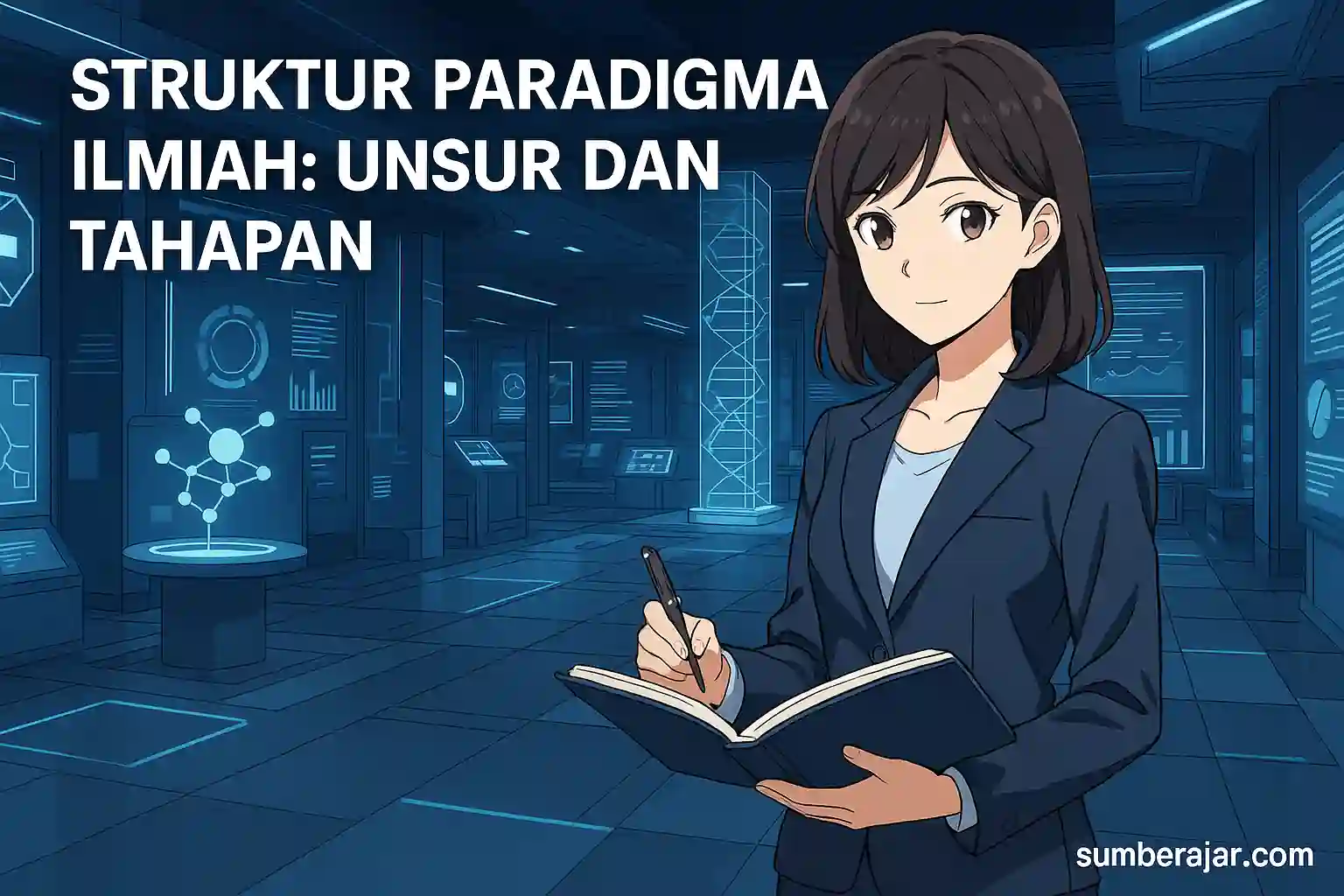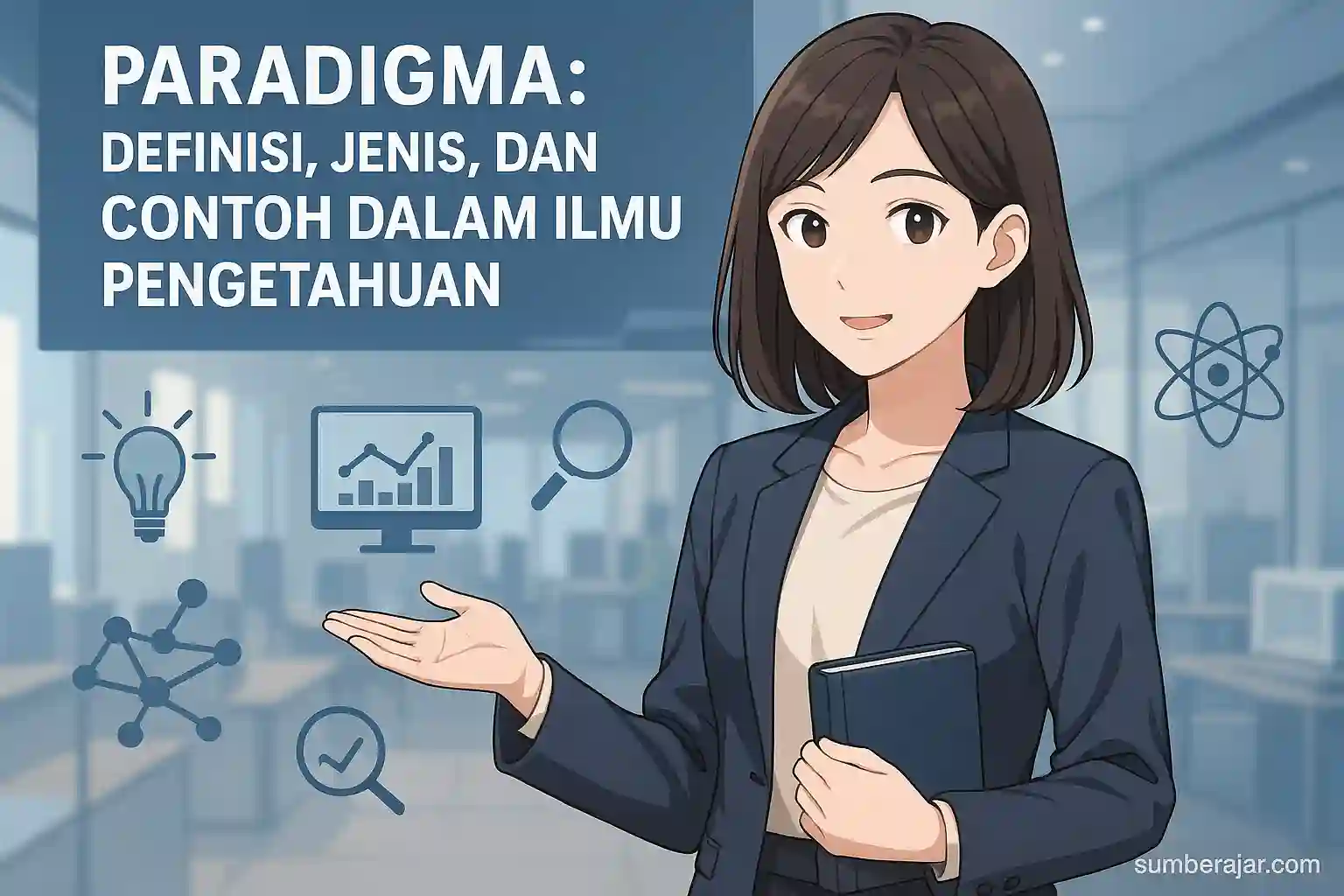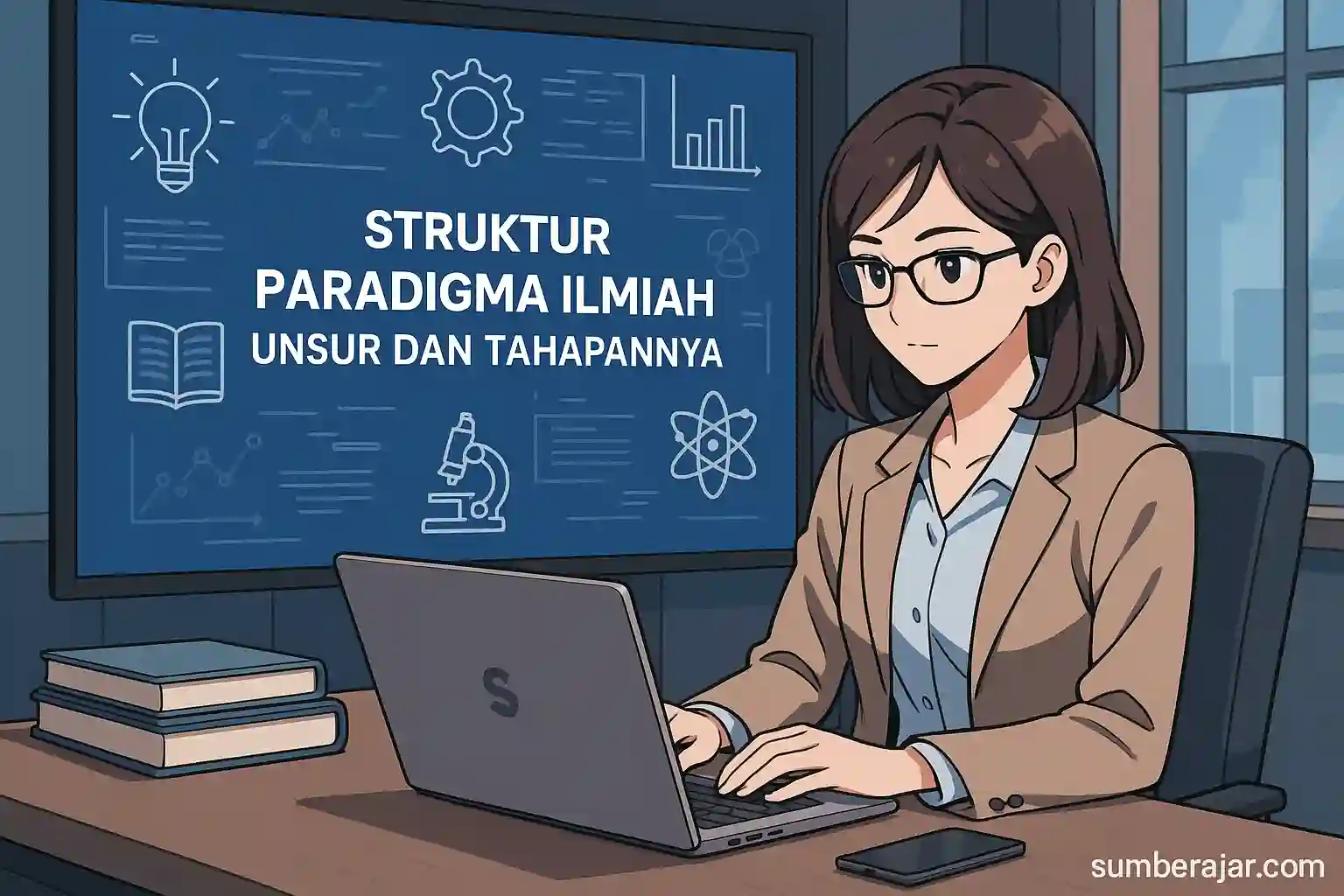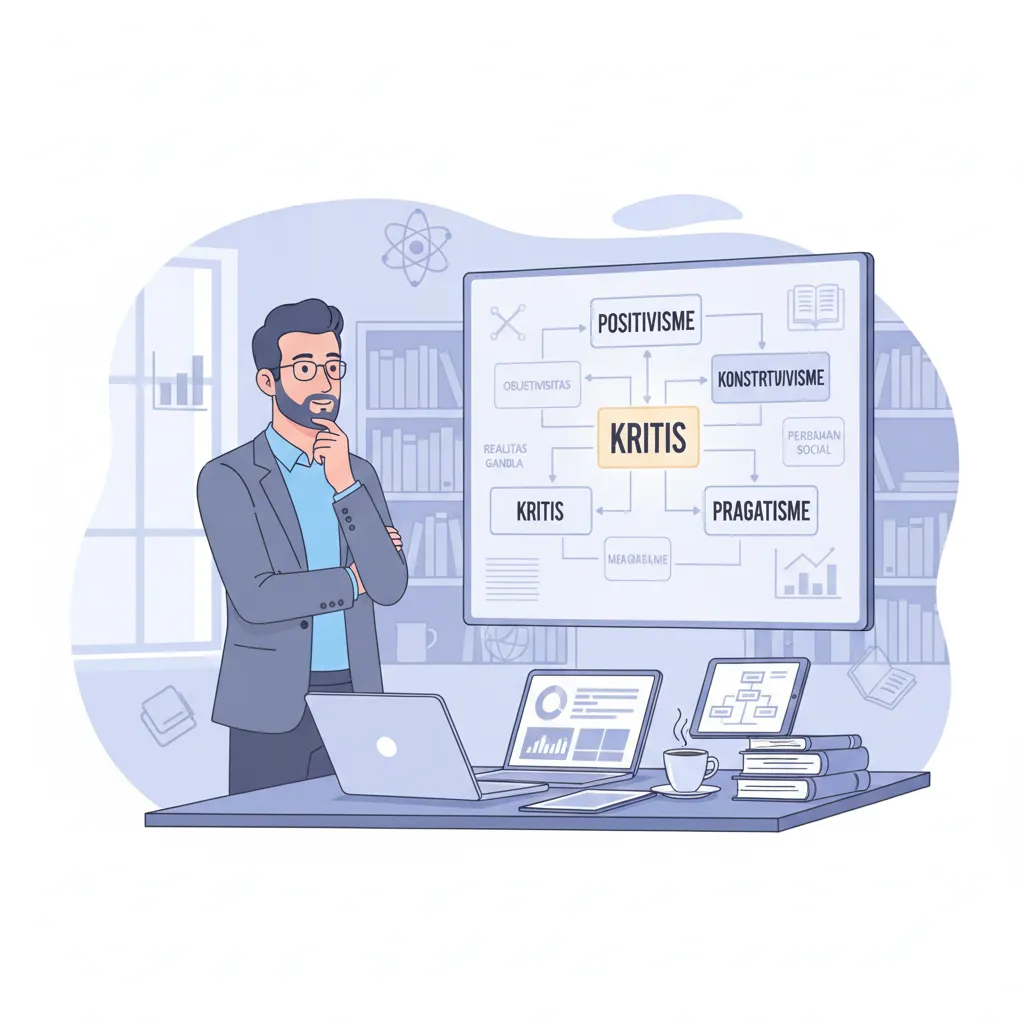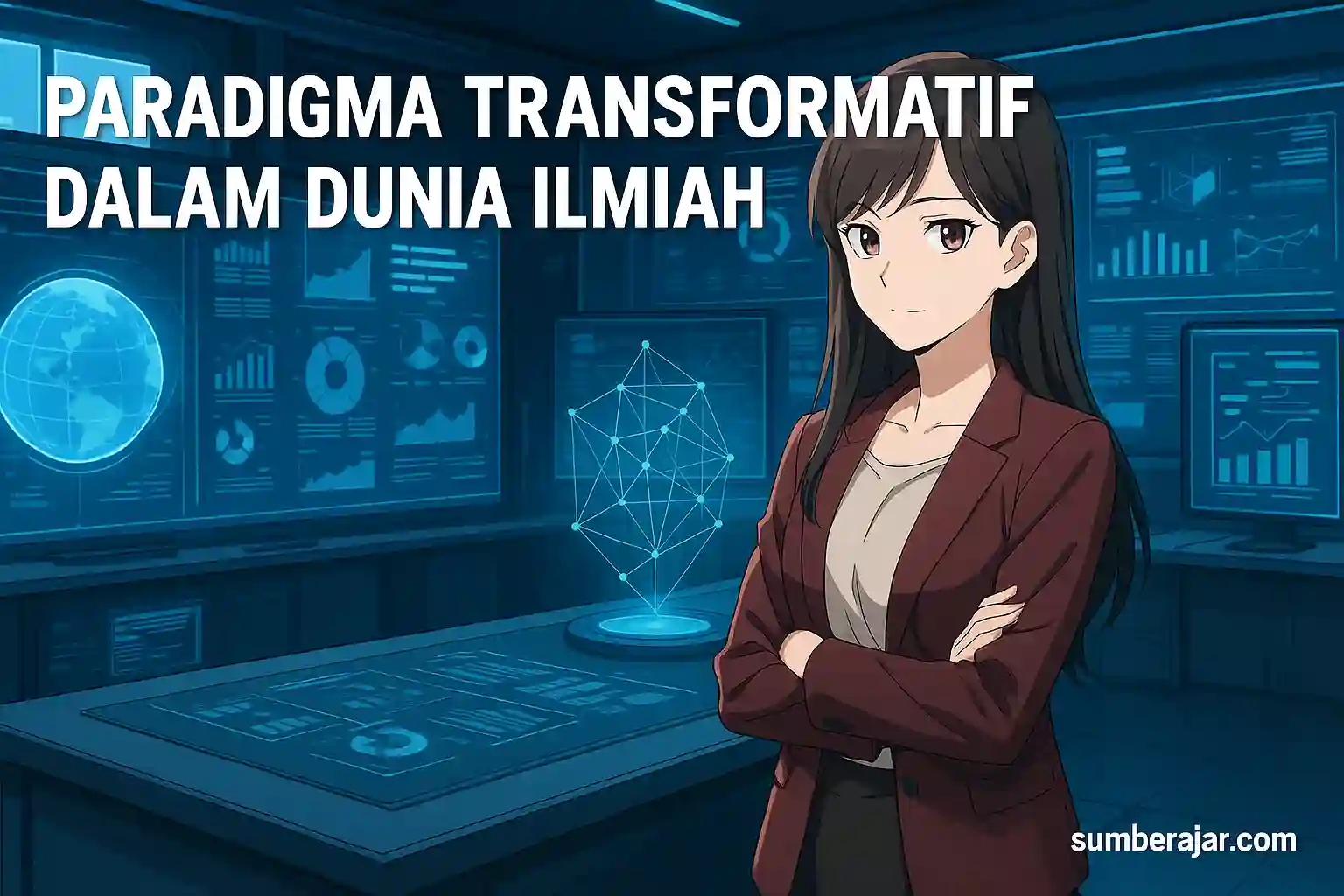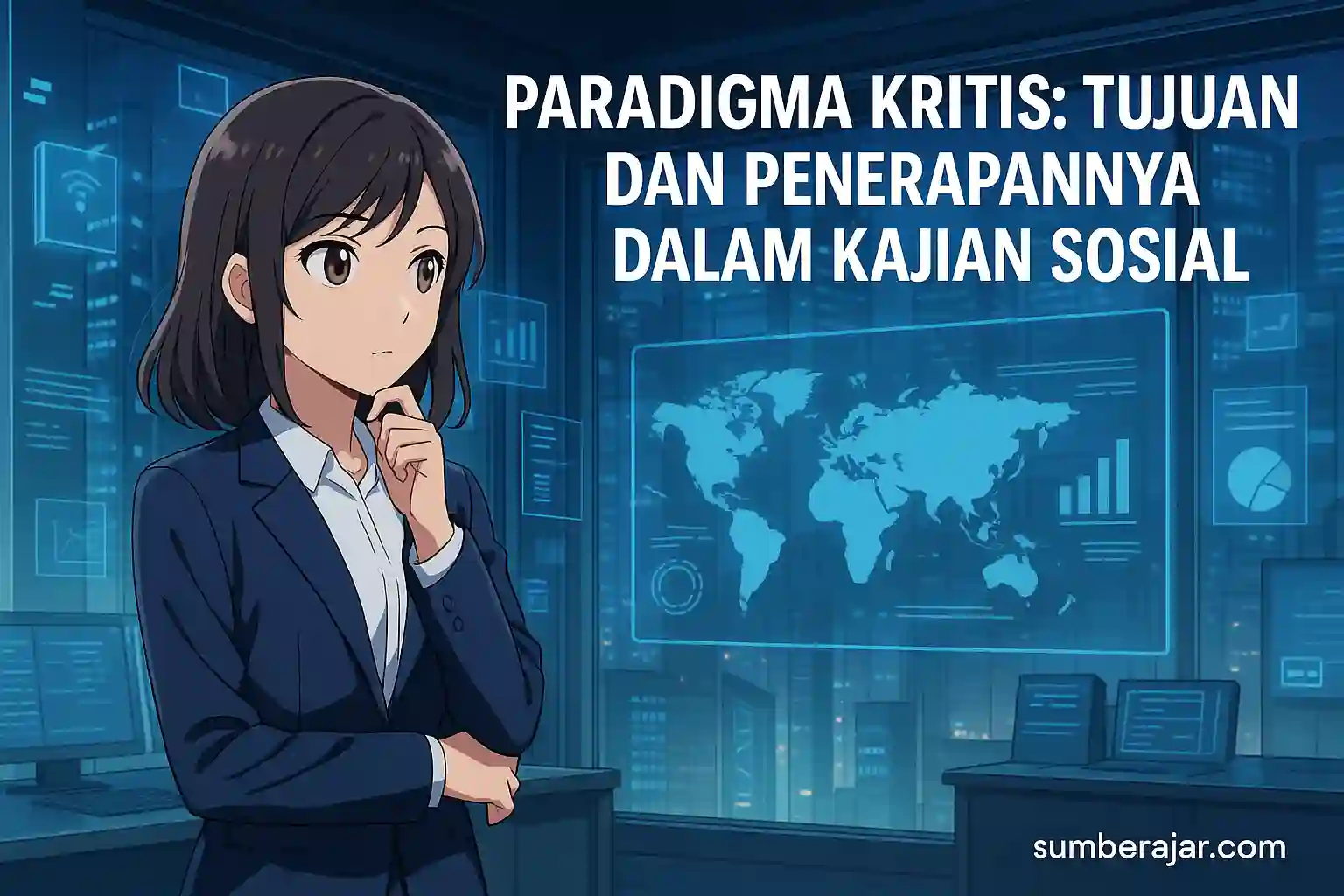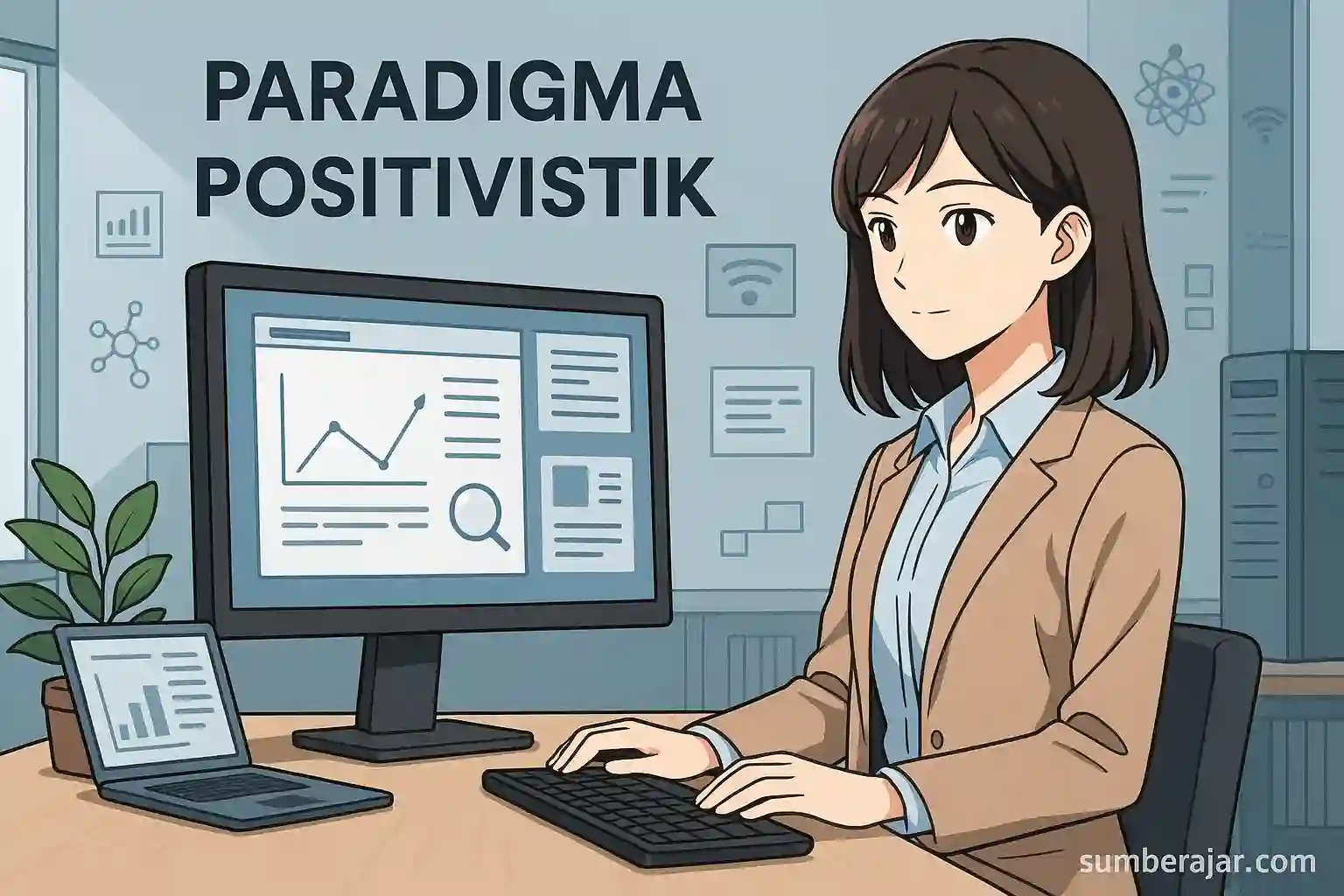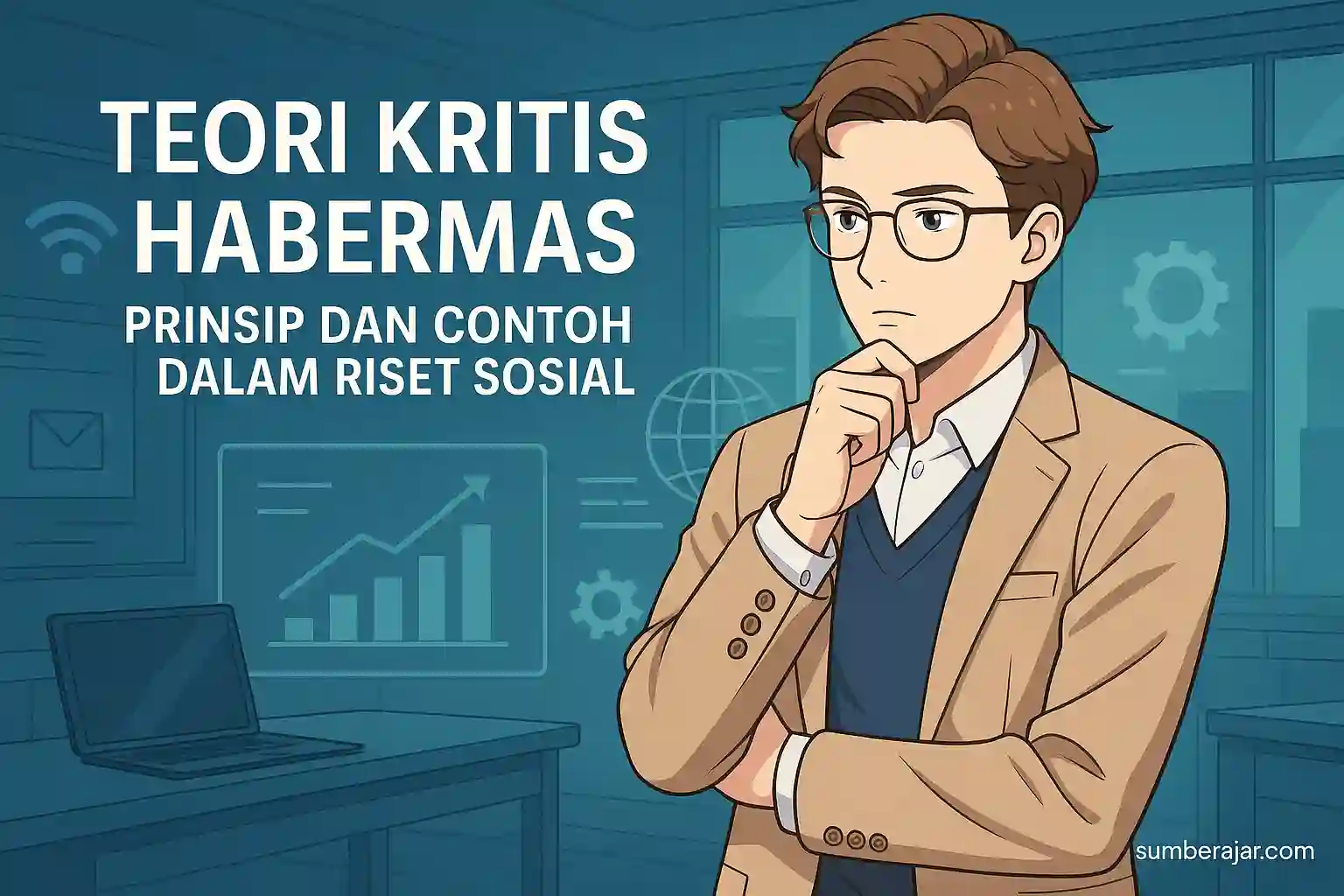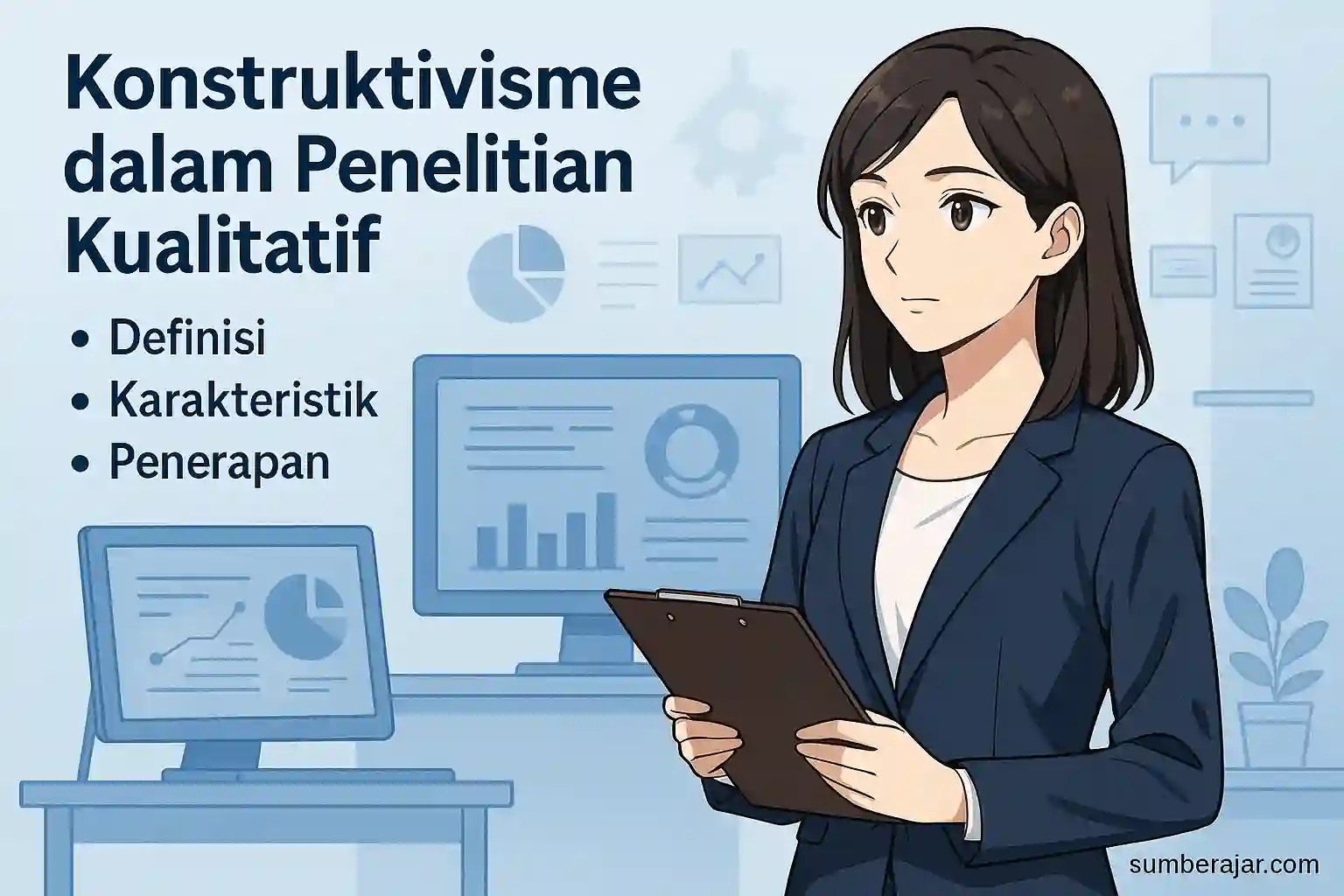Paradigma Kritis: Prinsip dan Contohnya dalam Penelitian Sosial
Pendahuluan
Dalam ranah ilmu sosial, pemilihan paradigma penelitian menjadi langkah yang sangat strategis karena akan menentukan arah, metodologi, serta makna temuan yang dihasilkan. Salah satu paradigma yang memperoleh perhatian signifikan dalam beberapa dekade terakhir adalah paradigma kritis. Paradigma ini hadir sebagai bentuk tanggapan terhadap paradigma dominan sebelumnya seperti positivisme, yang dianggap terlalu menekankan aspek objektivitas dan netralitas ilmuwan tanpa melihat dengan cukup tajam relasi kuasa, dominasi, dan struktur sosial yang tersembunyi. Dengan paradigma kritis, penelitian sosial tidak hanya sekadar memahami fenomena melainkan juga memiliki orientasi perubahan, yakni upaya mengkritisi kondisi yang timpang dan berupaya menuju tatanan sosial yang lebih adil. Dalam artikel ini akan dibahas secara komprehensif mengenai paradigma kritis: mulai dari definisi umum, definisi dalam KBBI, definisi menurut para ahli, prinsip-prinsipnya, serta contoh aplikasinya dalam penelitian sosial.
Definisi Paradigma Kritis
Definisi Paradigma Kritis Secara Umum
Secara umum, paradigma kritis dalam penelitian sosial dapat dipahami sebagai kerangka pemikiran yang menempatkan fokus pada relasi kekuasaan, struktur sosial yang menindas, proses ideologis, serta upaya pembebasan atau transformasi sosial. Paradigma ini melihat bahwa realitas sosial tidak netral atau bebas nilai, melainkan dibentuk oleh dinamika sejarah, politik, ekonomi, budaya, dan relasi kuasa. Sebagai kerangka penelitian, paradigma kritis menekankan bahwa tugas penelitian sosial bukan hanya menjelaskan keadaan yang ada, tetapi juga memberi kontribusi bagi perubahan kondisi yang lebih adil. Sebagai contoh, sebuah artikel menyatakan bahwa paradigma kritis melihat “ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkapkan struktur terdalam dalam sebuah keadaan … tujuan paradigma ini adalah untuk membangun kesadaran di dalam masyarakat untuk mengubah kondisi sosial menjadi lebih baik.” [Lihat sumber Disini - ejournal.upnvj.ac.id]
Definisi Paradigma Kritis dalam KBBI
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma umumnya diartikan sebagai “pola pikir, konsep atau kerangka acuan”, sedangkan “kritis” mengandung makna “bersifat teliti, mencermati dengan sungguh-sungguh, mengajukan pertanyaan, tidak langsung menerima” (merujuk pada definisi umum kata). Maka, jika digabungkan, secara bebas “paradigma kritis” dapat diartikan dalam KBBI sebagai kerangka pikir yang bersifat reflektif dan mempertanyakan struktur serta relasi sosial yang ada, dengan sikap tidak menerima begitu saja fenomena sosial sebagai sesuatu yang normal atau alamiah. Walaupun definisi persis dalam KBBI untuk frasa “paradigma kritis” tidak selalu tertulis secara eksplisit, penggunaan istilah ini dalam literatur menunjukkan orientasi yang sama: yaitu sikap kritis terhadap status quo sosial. Sebagai ilustrasi, portal berita akademik Universitas Gadjah Mada menyebut bahwa paradigma kritis “diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik.” [Lihat sumber Disini - feb.ugm.ac.id]
Definisi Paradigma Kritis Menurut Para Ahli
Beberapa ahli dan literatur telah merumuskan definisi paradigma kritis dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah kumpulan definisi menurut para ahli:
- Denzin & Lincoln (2009) menyatakan bahwa paradigma kritis adalah paradigma ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh epistemologi kritik Marxis dalam seluruh metodologi penelitiannya. [Lihat sumber Disini - eprints.umm.ac.id]
- Malik dan Nugroho (2016) menjelaskan bahwa paradigma penelitian kritis ialah salah satu paradigma yang muncul sebagai respons terhadap perdebatan metodologi dalam sosiologi, yang menempatkan realitas sosial sebagai dibentuk oleh kekuasaan dan nilai (value) bukan bebas nilai. [Lihat sumber Disini - ejournal.uin-suka.ac.id]
- Suharyo (2018) dalam artikel “Paradigma Kritis dalam Penelitian Wacana” menyebut bahwa paradigma kritis adalah kerangka penelitian yang memandang wacana sebagai tindakan sosial yang sarat dengan politik, ideologi, dan relasi kekuasaan. [Lihat sumber Disini - ejournal.undip.ac.id]
- Azwar (2022) memaparkan bahwa paradigma kritis dalam ilmu sosial termasuk ilmu komunikasi “berakar dari paradigma klasik” dan menempatkan periferalitas penelitian sebagai perubahan sosial: “komunikasi diharapkan menjadi jalan pembebasan” bukan sekadar instrumen dominasi. [Lihat sumber Disini - ejournal.upnvj.ac.id]
Dari keempat definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa paradigma kritis memiliki elemen-kunci seperti: orientasi terhadap perubahan, kesadaran terhadap relasi kekuasaan, keterlibatan nilai (value), dan peran aktif peneliti dalam mengubah kondisi sosial, bukan sekadar mendeskripsikannya.
Prinsip-Prinsip paradigma kritis
Untuk memahami bagaimana paradigma kritis bekerja dalam penelitian sosial, berikut beberapa prinsip utama yang perlu diketahui:
1. Asumsi Ontologis, Epistemologis, dan Metodologis
Dalam paradigma kritis:
- Ontologis: realitas sosial dilihat sebagai terbuka, historis, penuh ketegangan kekuasaan dan struktur yang tersembunyi, bukan sebagai objek yang netral dan tetap (fixed). [Lihat sumber Disini - ejournal.upnvj.ac.id]
- Epistemologis: pengetahuan tidak diproduksi secara netral atau objektif tanpa nilai atau kepentingan, melainkan sebagai hasil interaksi antara peneliti, subjek, serta struktur sosial. Peran peneliti bukan hanya pengamat pasif tetapi agen yang sadar akan posisi nilai dan keberpihakan. [Lihat sumber Disini - ejournal.upnvj.ac.id]
- Metodologis: penelitian menggunakan metode yang memungkinkan refleksi kritis, dialog, partisipasi, dan perubahan, seperti penelitian tindakan, analisis wacana kritis, partisipasi aktif komunitas. [Lihat sumber Disini - revoedu.org]
2. Keberpihakan dan Emansipasi
Paradigma kritis menuntut peneliti untuk memilih sikap yang jelas: tidak netral demi menjaga status quo, melainkan berpihak pada pihak yang lemah, tertindas atau kurang berdaya. Tujuan akhirnya adalah emansipasi, membebaskan kelompok yang terstruktur dalam ketimpangan sosial atau relasi kuasa yang timpang. Sebagai contohnya, sebuah kajian menyebut bahwa proyek utama paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. [Lihat sumber Disini - repository.unimal.ac.id]
3. Struktur, Ideologi, dan Kekuasaan
Paradigma kritis menaruh perhatian besar pada bagaimana struktur sosial (institusi, ekonomi, politik) dan ideologi mendistribusikan kekuasaan, menciptakan dominasi, dan menghasilkan kondisi sosial yang nampak “alamiah” padahal dibentuk secara historis. Penelitian kritis berusaha mengungkap “apa yang ada di balik” penampakan realitas sosial, misalnya hegemoni budaya, represif aparatus negara, ideologi pasar. [Lihat sumber Disini - ejournal.undip.ac.id]
4. Praktik Perubahan (Praxis)
Penelitian dalam paradigma kritis tidak berhenti pada analisis saja, tetapi juga memuat elemen praksis: yaitu tindakan atau rekomendasi konkret untuk mengubah kondisi sosial. Penelitian yang hanya mendeskripsikan ketimpangan tanpa orientasi perubahan dianggap belum menggambarkan paradigma kritis sesungguhnya. [Lihat sumber Disini - ejournal.upnvj.ac.id]
5. Analisis Konteks Historis dan Situasional
Paradigma kritis menuntut kajian yang memperhatikan aspek historis, budaya, sosial, dan ekonomi dari fenomena yang diteliti, karena ketimpangan sosial tidak muncul secara abrupt, melainkan terbentuk dalam sejarah dan melalui berbagai mekanisme kekuasaan. [Lihat sumber Disini - ejournal.uin-suka.ac.id]
Contoh Aplikasi Paradigma Kritis dalam Penelitian Sosial
Untuk membuat gambaran lebih nyata, berikut beberapa contoh penerapan paradigma kritis dalam penelitian sosial di Indonesia atau skema yang relevan:
Contoh 1 – Penelitian Analisis Wacana Kritik di Media
Suharyo (2018) dalam artikelnya “Paradigma Kritis dalam Penelitian Wacana” menggambarkan bahwa penelitian wacana dengan paradigma kritis melihat bahwa wacana bukanlah sekadar teks isolasi, melainkan tindakan sosial yang sarat dengan politik, kekuasaan, ideologi, dan proses marginalisasi. [Lihat sumber Disini - ejournal.undip.ac.id] Misalnya, penelitian yang memeriksa bagaimana media menggambarkan kelompok minoritas atau bagaimana unsur bahasa dan framing media menyuburkan dominasi tertentu. Dalam metode penelitian tersebut peneliti menggunakan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) untuk mengungkap bagaimana narasi dominan dibangun dan diterima secara “alamiah”.
Contoh 2 – Penelitian dalam Ilmu Komunikasi: Pergeseran Paradigma
Azwar (2022) membahas perubahan paradigma ilmu komunikasi dari paradigma klasik (positivisme) menuju paradigma kritis, dengan menyebut bahwa paradigma kritis menolak komunikasi hanya sebagai metode dominasi, tetapi mengusung komunikasi sebagai jalan pembebasan. [Lihat sumber Disini - ejournal.upnvj.ac.id] Sebagai contoh penelitian sosial-komunikasi yang menggunakan paradigma kritis yaitu memeriksa bagaimana struktur ekonomi dan industri budaya memengaruhi konten media massa sehingga mengabaikan suara kelompok marginal.
Contoh 3 – Penelitian Sosial dengan Orientasi Emansipatif
Dalam penelitian “konfrontasi keberpihakan pada komentar media digital“ (2024) disebut bahwa “proyek utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas.” [Lihat sumber Disini - journal2.um.ac.id] Sebagai contoh di lapangan: sebuah penelitian sosial yang memeriksa bagaimana komentar daring dalam media sosial memanifestasikan relasi kuasa antara kelompok mayoritas dan minoritas, dan selanjutnya mengusulkan strategi pemberdayaan komunitas minoritas melalui pelatihan literasi digital.
Contoh 4 – Penelitian Sistem Informasi dengan Tinjauan Kritis
Darono dalam “Paradigma Kritis dalam Penelitian Sistem Informasi di Indonesia: Perlukah?” menyoroti bahwa penelitian sistem informasi (SI) di Indonesia dapat menggunakan paradigma kritis untuk mengungkap bagaimana sistem-teknologi informasi tidak hanya bersifat teknikal melainkan juga membentuk relasi kekuasaan, privasi, akses, dan hambatan sosial. [Lihat sumber Disini - researchgate.net] Sebagai ilustrasi: penelitian yang melihat implementasi e-government di daerah terpencil yang ternyata memperkuat marginalisasi sosial daripada memberdayakan warga.
Kesimpulan
Paradigma kritis merupakan kerangka pemikiran yang sangat relevan dan strategis bagi penelitian sosial yang ingin bergerak lebih dari sekadar memahami fenomena, yaitu menuju perubahan sosial yang lebih adil. Dengan mengedepankan prinsip keberpihakan, analisis terhadap struktur dan ideologi kekuasaan, serta orientasi terhadap emansipasi dan praktik perubahan, paradigma ini memposisikan penelitian sebagai alat transformasi sosial. Bagi peneliti sosial, memahami dan menggunakan paradigma kritis berarti mengambil posisi aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui penelitian yang reflektif, kontekstual, dan berorientasi aksi.