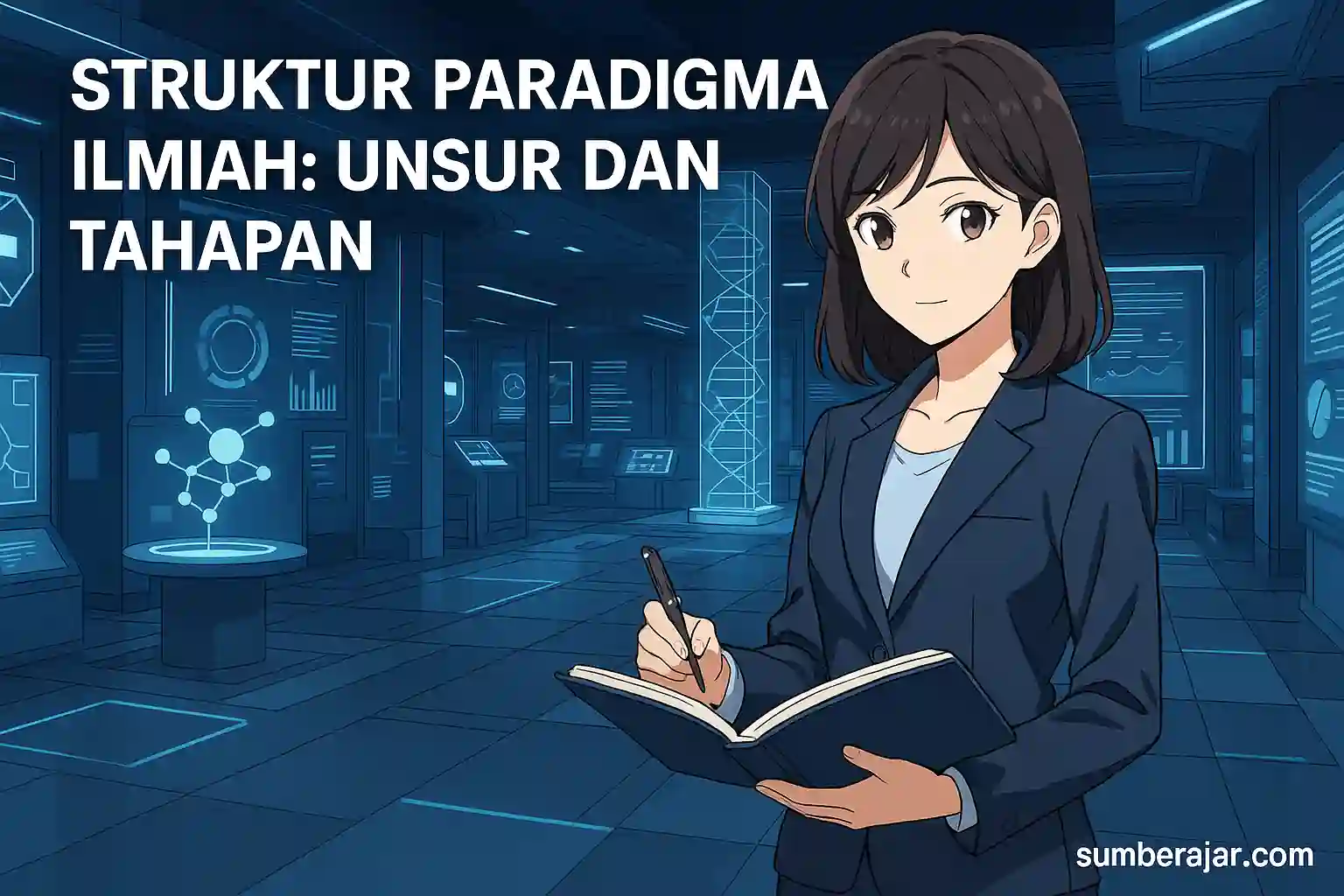Post-Positivisme: Karakteristik dan Contoh dalam Penelitian Modern
Pendahuluan
Dalam dunia ilmu pengetahuan dan penelitian, paradigma tidak hanya menentukan bagaimana penelitian dilakukan, tetapi juga menuntun cara pandang terhadap realitas, pengetahuan, serta metodologi yang digunakan. Salah satu paradigma yang semakin relevan dalam penelitian modern,terutama dalam ilmu sosial dan pendidikan,adalah post-positivisme. Paradigma ini muncul sebagai respons dan kritik terhadap paradigma tradisional: positivisme, yang dianggap terlalu kaku karena meyakini bahwa realitas hanya dapat dipahami melalui observasi objektif dan metode kuantitatif semata.
Post-positivisme mencoba mempertahankan aspek ilmiah dan empirik dari positivisme, namun dengan pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai peneliti: bahwa observasi, pengukuran, interpretasi, dan latar belakang peneliti bisa memengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, post-positivisme menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis terhadap penelitian, salah satunya menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, serta membuka ruang bagi subjektivitas, konteks, dan refleksi kritis. Pendekatan ini sangat berguna ketika objek penelitian berwujud fenomena sosial atau manusia, di mana variabel tidak bisa diukur secara sederhana layaknya fenomena alam.
Dalam artikel ini, akan dibahas definisi post-positivisme, karakteristik utamanya, serta contoh penerapannya dalam penelitian modern.
Definisi Post-Positivisme
Definisi Post-Positivisme Secara Umum
Secara umum, post-positivisme merupakan sebuah sikap metateoretis terhadap penyelidikan ilmiah: meskipun realitas dianggap ada secara objektif, pengetahuan tentang realitas tersebut dianggap hanya bisa didekati secara tentatif dan bersifat probabilistik, bukan absolut. [Lihat sumber Disini - pmc.ncbi.nlm.nih.gov]
Dalam perspektif ini, penelitian tetap menggunakan metode ilmiah, observasi, pengujian, pengumpulan data, namun peneliti menyadari bahwa pengamatan dan teori selalu rentan terhadap bias, keterbatasan alat, dan konteks sosial-kultural. Oleh karena itu, hasil penelitian di post-positivisme dipahami sebagai hipotesis atau klaim sementara yang bisa direvisi seiring temuan baru. [Lihat sumber Disini - pmc.ncbi.nlm.nih.gov]
Definisi Post-Positivisme dalam KBBI
Istilah “post-positivisme” tidak tercantum sebagai entri tersendiri di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dalam versi daring publik, setidaknya tidak dalam pencarian umum. Oleh karena itu, untuk keperluan akademik, definisi lebih sering diturunkan dari literatur filsafat ilmu dan metodologi penelitian yang membahas paradigma penelitian. Dalam konteks ini, post-positivisme didefinisikan sebagai paradigma atau pendekatan penelitian yang “setelah positivisme”, yaitu mengkritisi asumsi positivisme dan menyesuaikan dengan kenyataan bahwa pengetahuan ilmiah tentang realitas tidak pernah sepenuhnya bebas dari nilai, bias, dan keterbatasan.
Definisi Post-Positivisme Menurut Para Ahli
Berikut beberapa definisi post-positivisme menurut para ahli dan literatur akademik:
- Karl Popper, meskipun tidak secara eksplisit selalu disebut sebagai “post-positivis”, pemikirannya tentang falsifikasi (bahwa teori ilmiah tidak bisa diverifikasi secara final, hanya bisa gagal dibuktikan) menjadi fondasi penting bagi perkembangan pandangan post-positivisme terhadap pengetahuan yang bersifat sementara dan kontingent. [Lihat sumber Disini - en.wikipedia.org]
- Thomas Kuhn, melalui gagasan “paradigm shifts” dan kritik terhadap positivisme serta positivisme logis, Kuhn membantu membuka jalan bagi pendekatan post-positivisme yang mengakui bahwa ilmuwan membawa teori, latar belakang, dan asumsi ke dalam pengamatan mereka. [Lihat sumber Disini - en.wikipedia.org]
- Literature metodologi penelitian modern, menurut beberapa panduan, post-positivisme adalah pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan kesadaran bahwa semua pengukuran dan interpretasi bisa mengandung bias manusia. [Lihat sumber Disini - testbook.com]
- Dalam konteks pendidikan dan ilmu sosial di Indonesia: penelitian di bawah paradigma post-positivisme mengakui bahwa fenomena sosial dan pendidikan tidak bisa sepenuhnya direduksi ke angka atau fakta empiris saja, melainkan juga membutuhkan interpretasi subjektif. [Lihat sumber Disini - jurnal.permapendis-sumut.org]
- Menurut kajian filsafat ilmu lokal: post-positivisme hadir sebagai respons terhadap keterbatasan positivisme dalam menangkap kompleksitas realitas manusia dan masyarakat, serta sebagai upaya menjadikan ilmu pengetahuan lebih “jujur” terhadap kondisi epistemologis manusia. [Lihat sumber Disini - ejournal.undip.ac.id]
Dengan demikian, post-positivisme di mata para ahli adalah paradigma penelitian yang menggabungkan rasa hormat terhadap metode ilmiah dan empirisme, sembari tetap realistis terhadap keterbatasan pengetahuan manusia dan konteks sosial yang kompleks.
Karakteristik Post-Positivisme
Berikut karakteristik utama post-positivisme, yang membedakannya dari positivisme klasik dan pendekatan lain:
Realitas Dianggap Ada, Tapi Pengetahuan Tentangnya Bersifat Sementara
Post-positivisme berasumsi bahwa ada realitas objektif di luar pikiran manusia, realitas itu nyata, tetapi pengetahuan kita tentang realitas tersebut bersifat terbatas, bersifat dugaan (conjectural), dan selalu bisa direvisi. [Lihat sumber Disini - en.wikipedia.org]
Kesadaran atas Bias Peneliti dan Nilai yang Tak Terhindarkan
Berbeda dengan positivisme yang menganggap peneliti bisa benar-benar “netral” dan bebas nilai (value-free), post-positivisme mengakui bahwa peneliti membawa nilai, latar belakang, teori, dan pengalaman ke dalam penelitian. Karena itu, peneliti harus secara sadar mendeteksi kemungkinan bias dan berusaha meminimalkannya, serta transparan tentang keterbatasan dalam publikasi hasil. [Lihat sumber Disini - en.wikipedia.org]
Fleksibilitas Metodologis, Gabungan Kuantitatif dan Kualitatif
Post-positivisme membuka ruang untuk penggunaan metode campuran (mixed methods), yaitu kombinasi antara metode kuantitatif (angka, data terukur) dan kualitatif (narasi, wawancara, observasi partisipatif), agar bisa menangkap aspek realitas yang lebih kompleks. [Lihat sumber Disini - testbook.com]
Teori sebagai Panduan, Tapi Terbuka untuk Revisi
Penelitian post-positivis biasanya diawali dengan kerangka teori atau hipotesis, kemudian pengumpulan data dilakukan untuk menguji atau menolak hipotesis tersebut. Namun, hasil penelitian bisa saja menyebabkan revisi teori, atau bahkan pengembangan teori baru, karena pengetahuan dianggap bersifat kontingent dan berkembang. [Lihat sumber Disini - kc.umn.ac.id]
Konteks dan Subjektivitas sebagai Bagian dari Realitas Sosial
Karena objek penelitian sering berupa manusia atau fenomena sosial, post-positivisme mempertimbangkan bahwa interpretasi harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis. Realitas sosial tidak bisa disederhanakan layaknya fenomena alam sehingga post-positivisme menghargai aspek kompleksitas dan subjektivitas. [Lihat sumber Disini - kc.umn.ac.id]
Hasil Tidak Selalu Bersifat Umum/Universal (Terbatas pada Konteks)
Karena realitas sosial sangat tergantung konteks, generalisasi besar dari penelitian post-positivis sering sulit dilakukan, hasil mungkin berlaku di satu konteks tetapi tidak di konteks lain. Oleh karena itu, post-positivisme sering mendukung penelitian dengan cakupan lebih kecil, eksploratif, serta interpretatif. [Lihat sumber Disini - pmc.ncbi.nlm.nih.gov].
Contoh Penerapan Post-Positivisme dalam Penelitian Modern
Berikut beberapa contoh bagaimana paradigma post-positivisme diterapkan dalam penelitian kontemporer, khususnya di Indonesia dan dalam ilmu sosial/pendidikan:
Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Holistik
Dalam artikel terbaru, paradigma post-positivisme digunakan untuk menganalisis pendidikan dasar Islam, tidak hanya melihat aspek faktual atau kuantitatif (seperti tingkat pencapaian atau nilai akademik), tetapi juga memahami makna sosial, interpretasi religius, dan konteks kultural siswa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas pendidikan, nilai spiritual, serta interaksi sosial di lingkungan sekolah. [Lihat sumber Disini - jurnal.permapendis-sumut.org]
Kajian Filosofis dan Sosial terhadap Ilmu dan Pengetahuan
Di bidang filsafat ilmu dan perencanaan kota, paradigma post-positivisme membantu para peneliti meninjau ulang bagaimana ilmu pengetahuan dibentuk, bahwa ilmu bukan semata kumpulan fakta objektif, melainkan hasil konstruksi sosial, teori, dan interpretasi. Dalam konteks perencanaan kota, hal ini berguna untuk memahami bagaimana pilihan perencanaan dibentuk oleh nilai, kebijakan, dan asumsi masyarakat. [Lihat sumber Disini - ejournal.undip.ac.id]
Penelitian Sosial dan Ilmu Komunikasi yang Menggabungkan Metode
Penelitian di ilmu sosial, misalnya sosiologi, komunikasi, atau konseling, dengan paradigma post-positivisme sering menggunakan metode campuran: survei kuantitatif untuk mendapatkan data umum, serta wawancara atau observasi kualitatif untuk menangkap perspektif subjektif partisipan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam sekaligus validitas data yang lebih kaya. [Lihat sumber Disini - kc.umn.ac.id]
Kajian Epistemologi Ilmu Sosial di Indonesia
Beberapa penelitian literatur di Indonesia membahas bagaimana post-positivisme menjadi landasan epistemologis dalam penelitian sosial-politik, pendidikan, atau ilmu sosial pada umumnya. Studi ini menunjukkan bahwa paradigma ini membantu membuka ruang reflexivity (refleksi kritis) terhadap nilai dan asumsi peneliti, serta meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis terhadap fenomena sosial. [Lihat sumber Disini - journal.uwgm.ac.id].
Implikasi dan Kelebihan & Keterbatasan Post-Positivisme
Kelebihan
- Memberikan keseimbangan antara empirisme dan interpretasi, memungkinkan penelitian terhadap fenomena kompleks manusia dan masyarakat tanpa harus dipaksakan ke metode kuantitatif saja.
- Mengakui bias dan keterbatasan peneliti secara terbuka, sehingga hasil penelitian cenderung lebih jujur, transparan, dan reflektif.
- Fleksibilitas metodologis membuat paradigma ini cocok untuk berbagai jenis penelitian: pendidikan, sosiologi, komunikasi, kebijakan, lingkungan, dan banyak lagi.
- Membuka ruang bagi teori kritis, kontekstualisasi, dan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial.
Keterbatasan
- Karena realitas dan pengetahuan dianggap bersifat kontingent dan kontekstual, generalisasi hasil bisa sulit, hasil yang berlaku di satu konteks belum tentu berlaku di konteks lain.
- Karena melibatkan subjektivitas dan interpretasi, hasil penelitian bisa diperdebatkan, membutuhkan transparansi metodologis dan justifikasi teoretis yang kuat.
- Kadang sulit untuk “menstandarkan” kualitas penelitian, terutama di antara peneliti yang berbeda latar belakang teori, nilai, atau asumsi.
Kesimpulan
Post-positivisme merupakan paradigma penelitian yang relevan dan penting dalam penelitian modern, terutama untuk ilmu sosial, pendidikan, dan kajian manusia/masyarakat. Dengan menggabungkan rasa hormat terhadap metode ilmiah dan empirisme, serta kesadaran atas keterbatasan pengetahuan manusia, post-positivisme memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas realitas sosial secara lebih jujur, reflektif, dan kontekstual.
Melalui fleksibilitas metode (kuantitatif dan kualitatif), pengakuan terhadap bias, serta keterbukaan terhadap revisi teori, penelitian di bawah paradigma ini cenderung menawarkan pemahaman yang lebih holistik dan kritis terhadap fenomena manusia. Namun demikian, peneliti perlu tetap berhati-hati dalam interpretasi hasil dan transparan terhadap asumsi serta konteks yang melingkupinya.
Dengan demikian, post-positivisme bukan hanya sekadar opsi metodologis, melainkan sebuah pendekatan epistemologis dan filosofis yang menekankan bahwa pengetahuan ilmiah adalah proses terus-menerus, tidak statis, dan selalu terbuka untuk kritik, revisi, dan kontekstualisasi.
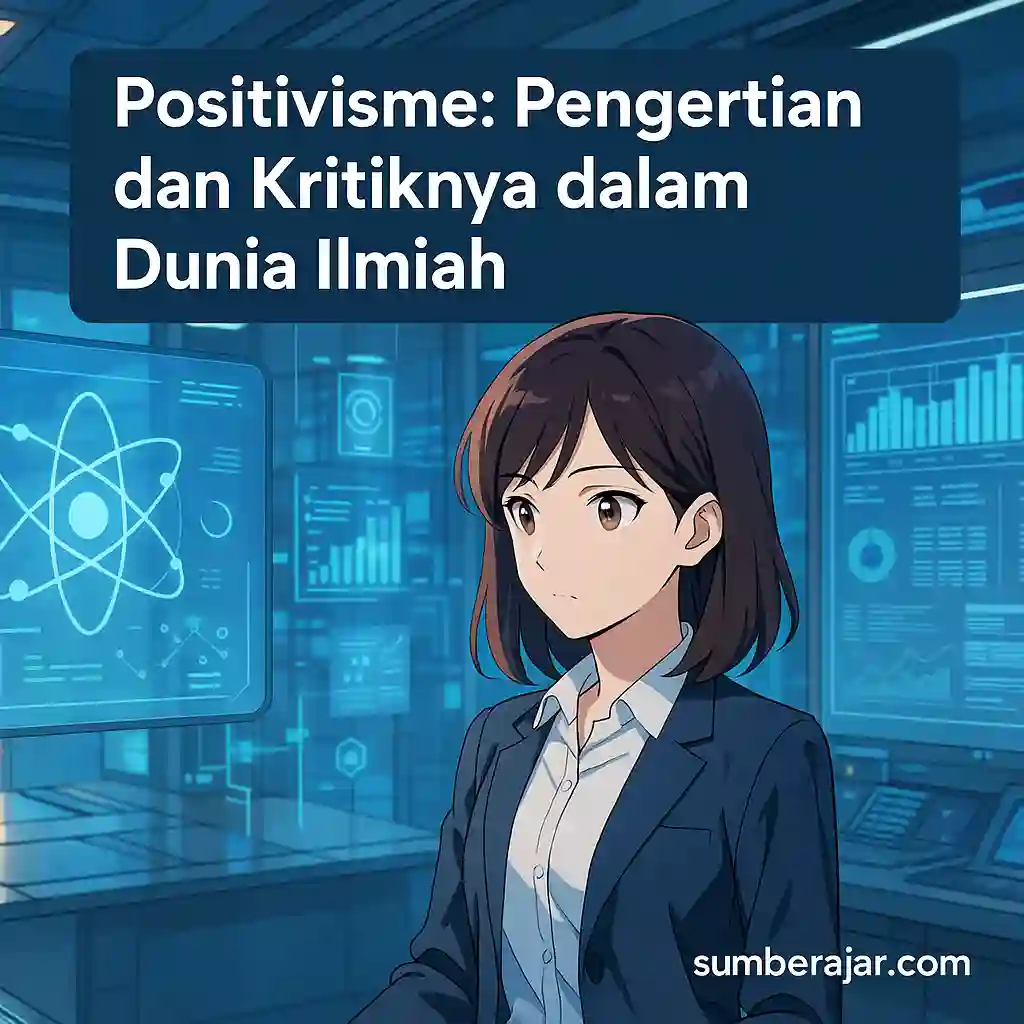


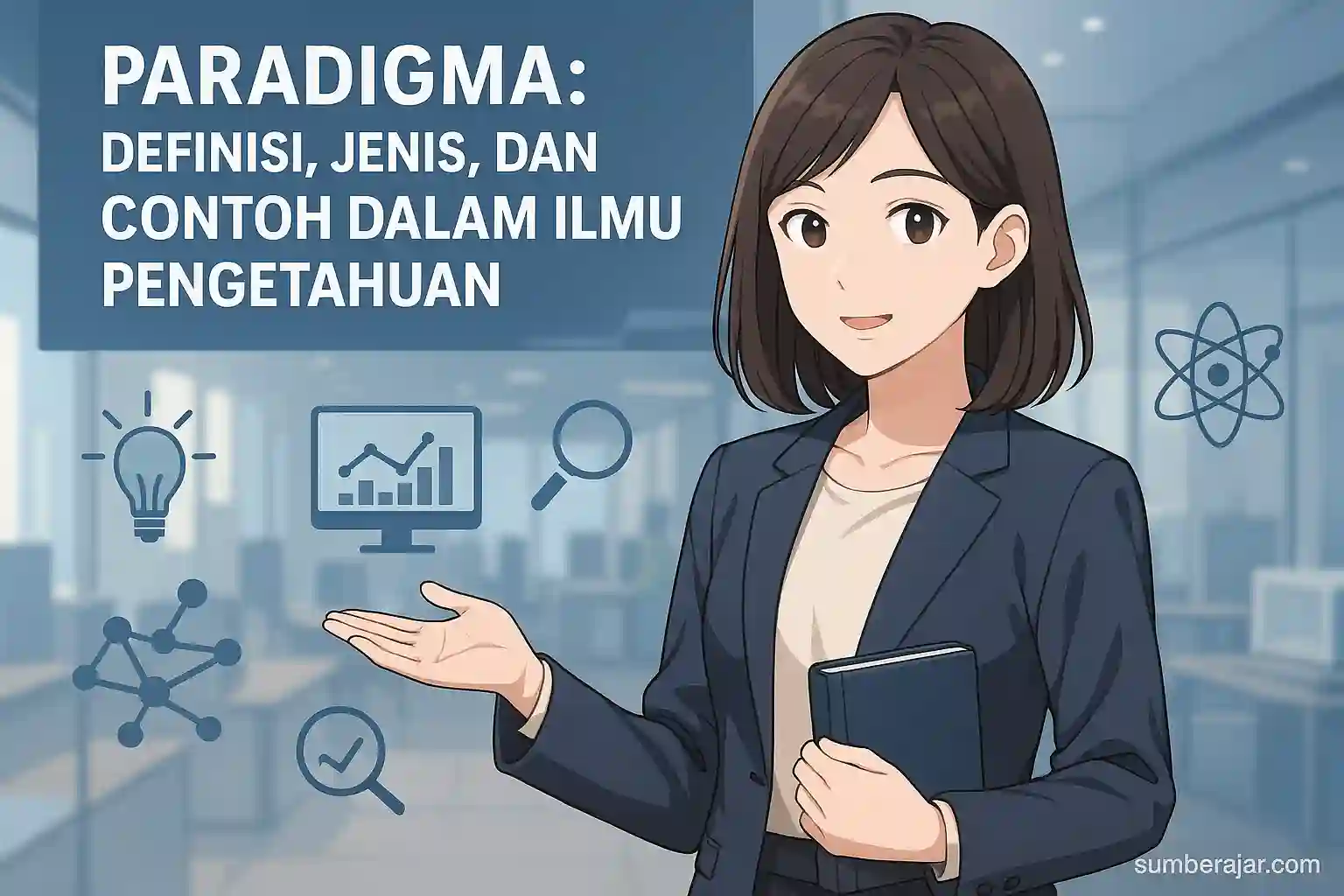
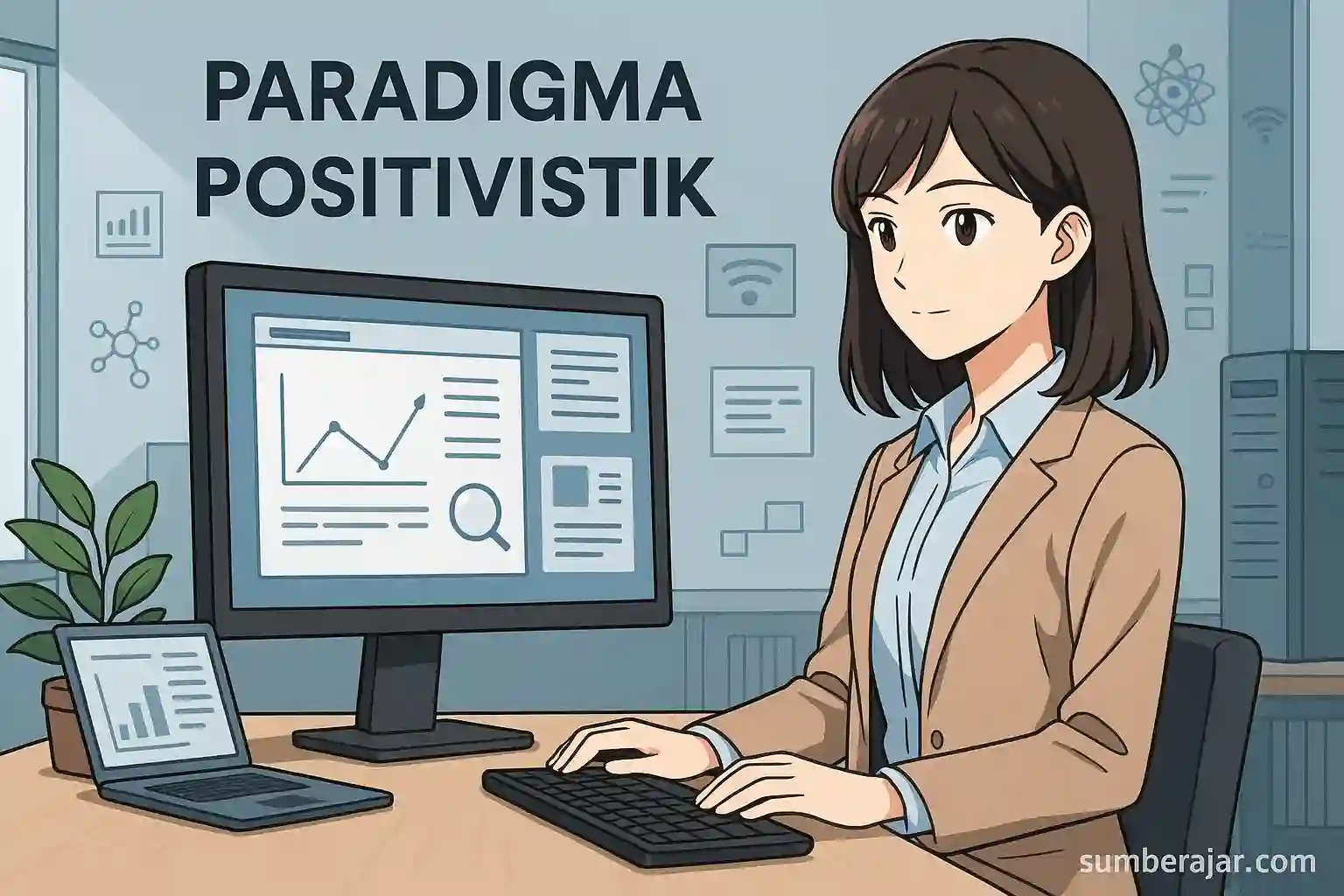

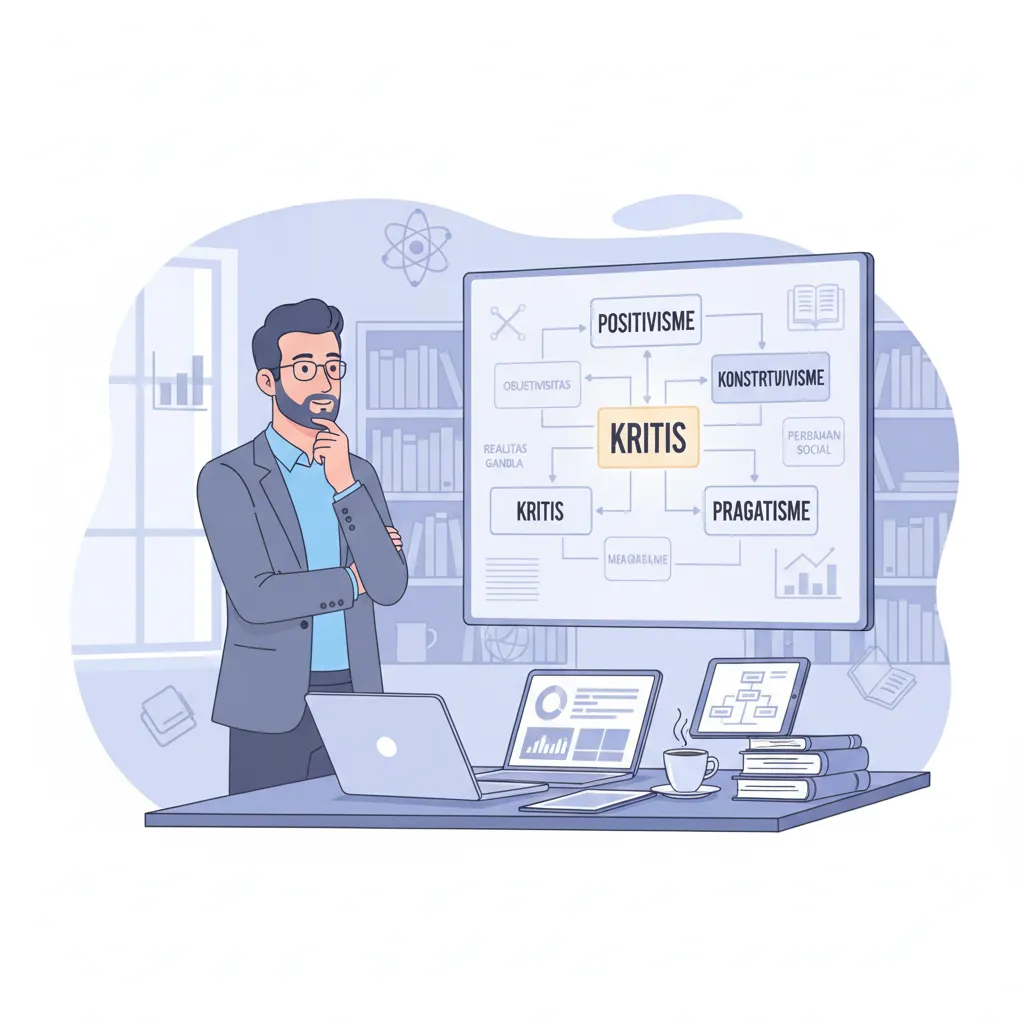



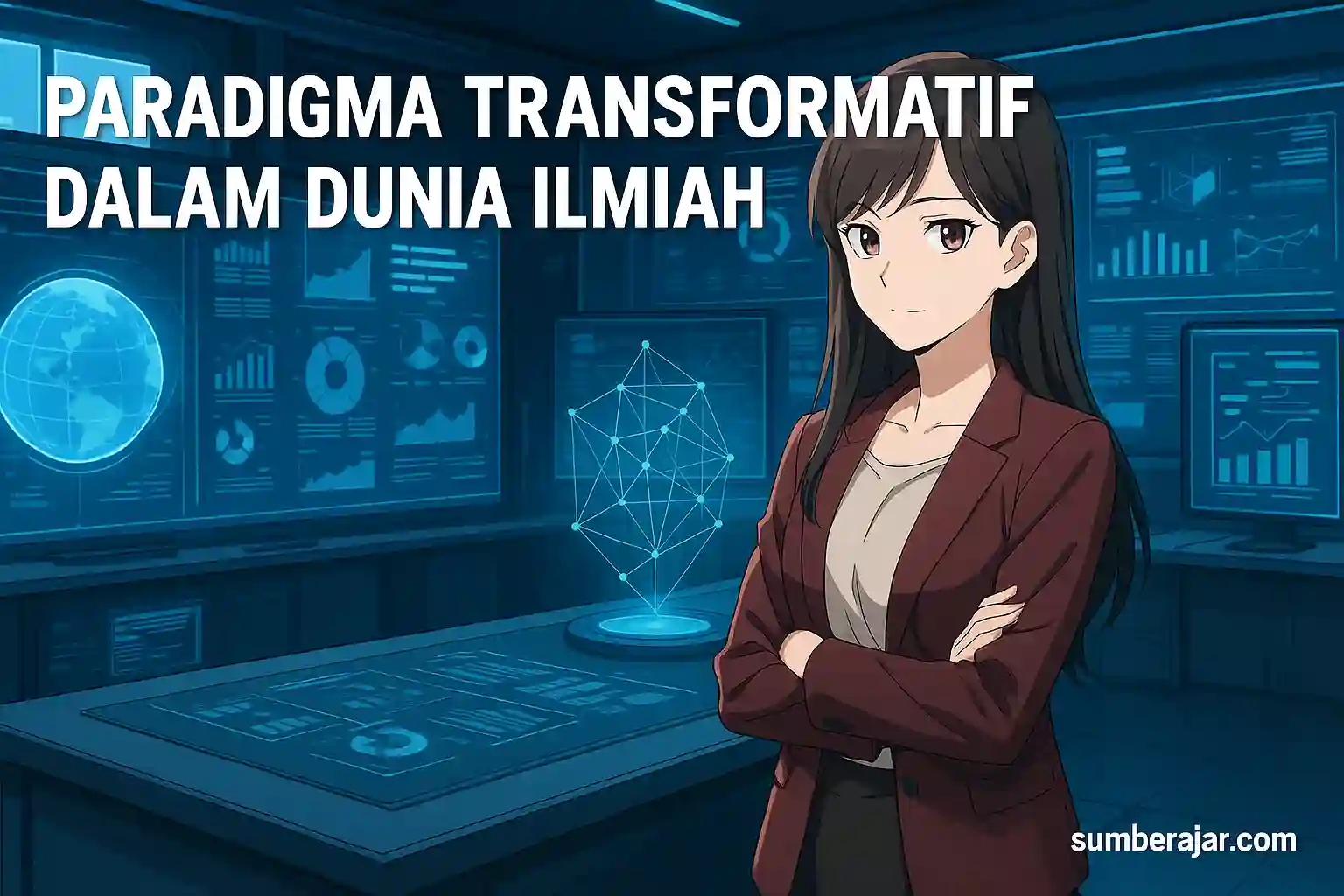





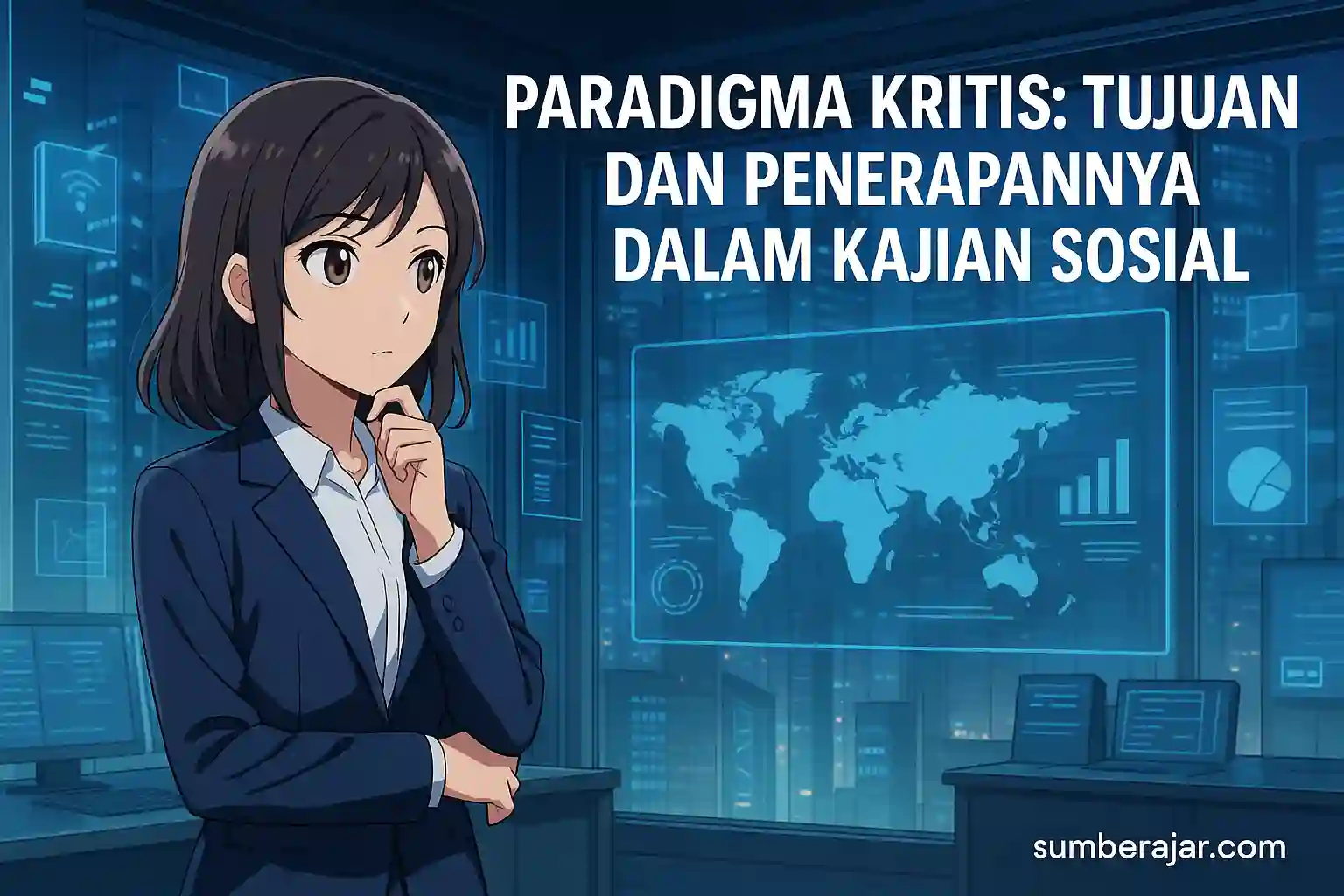
![Metodologi Penelitian: Definisi, Unsur, dan Perbedaannya dengan Metode, lengkap beserta sumber [PDF]](https://sumberajar.com/assest/uploads/2025/11/metodologi-penelitian-definisi-unsur-dan-perbedaannya-dengan-metode.webp)