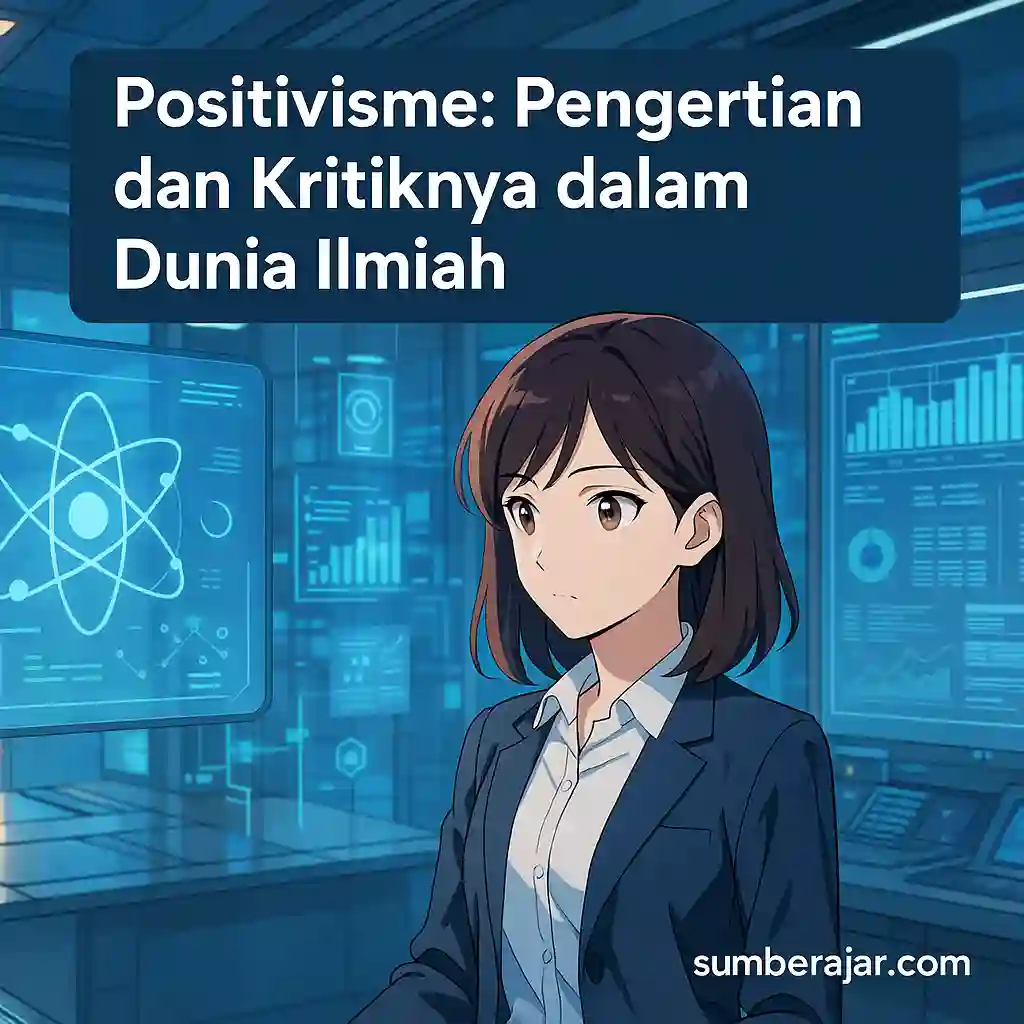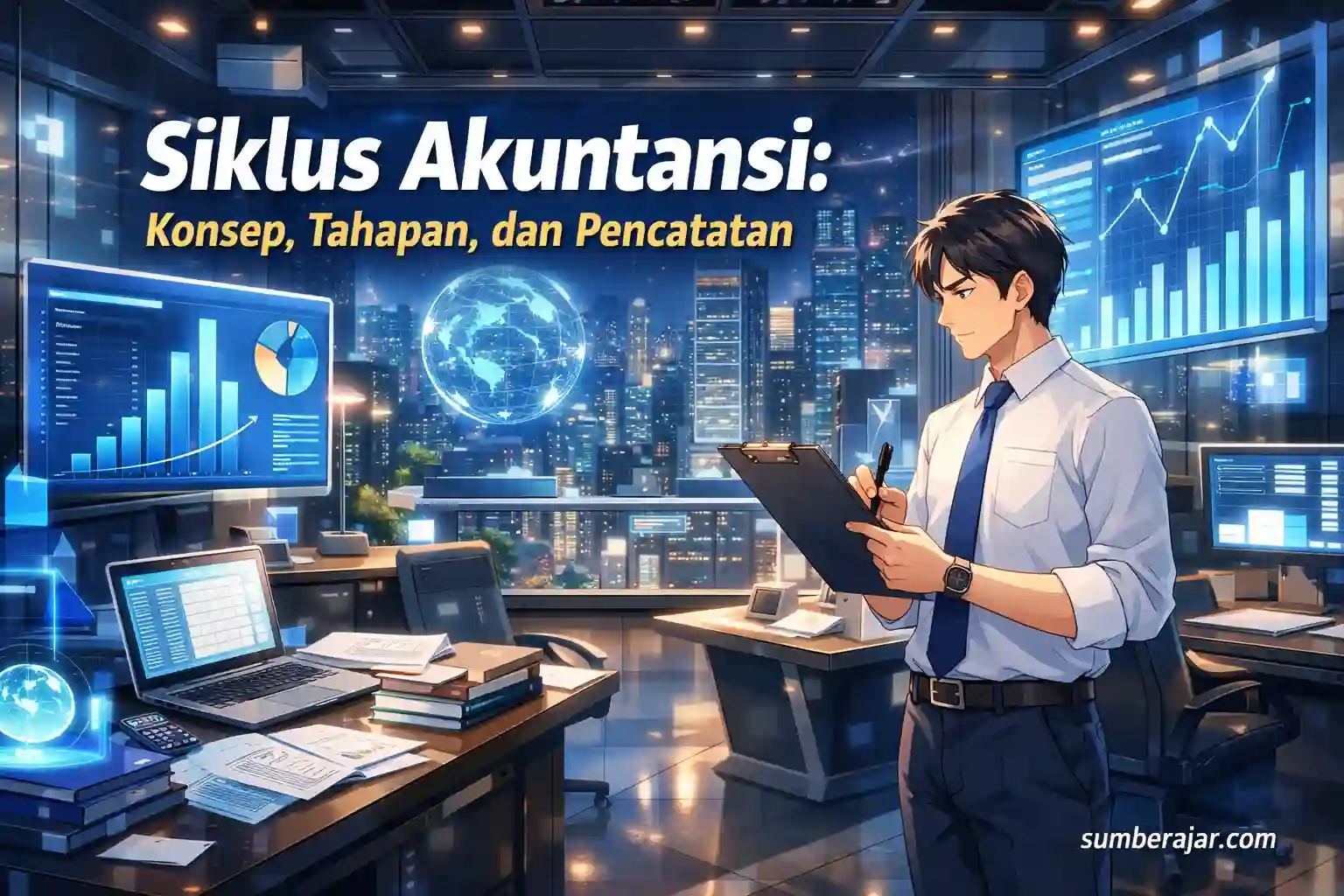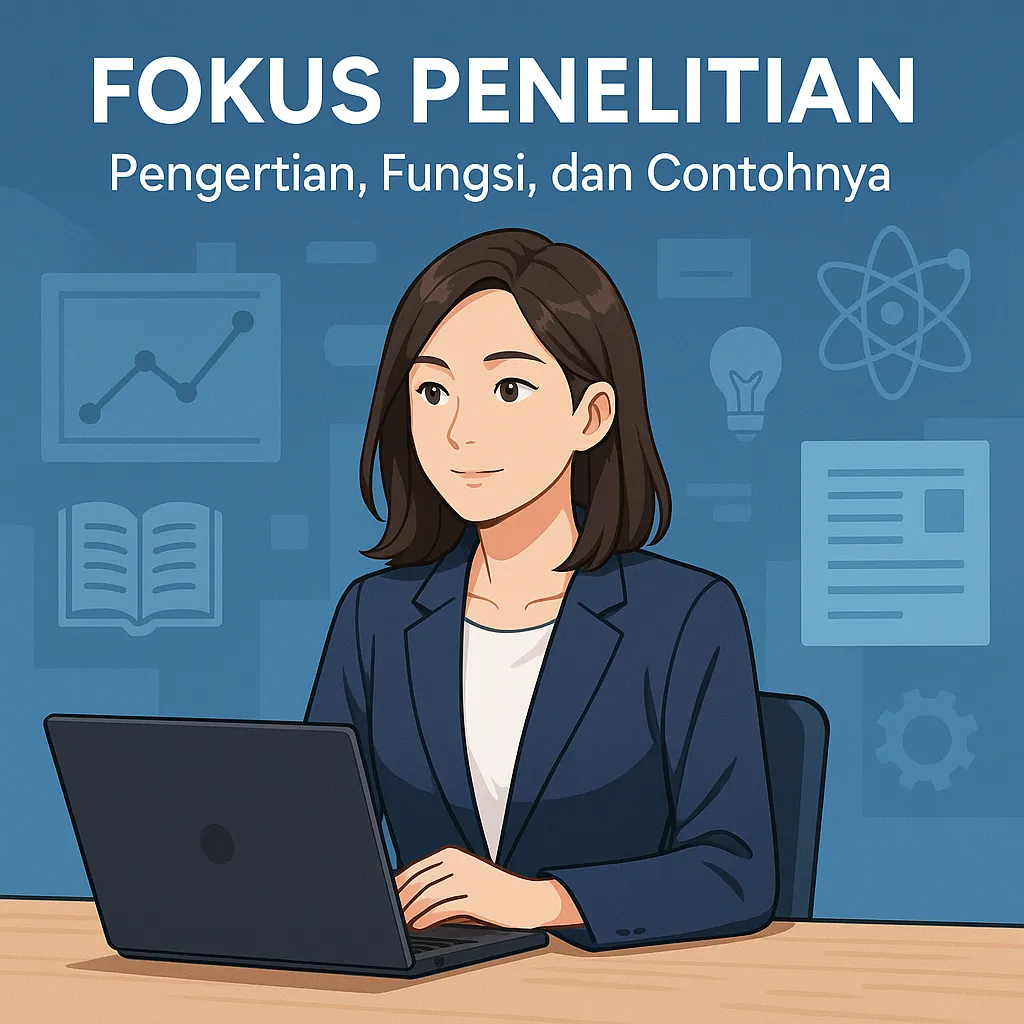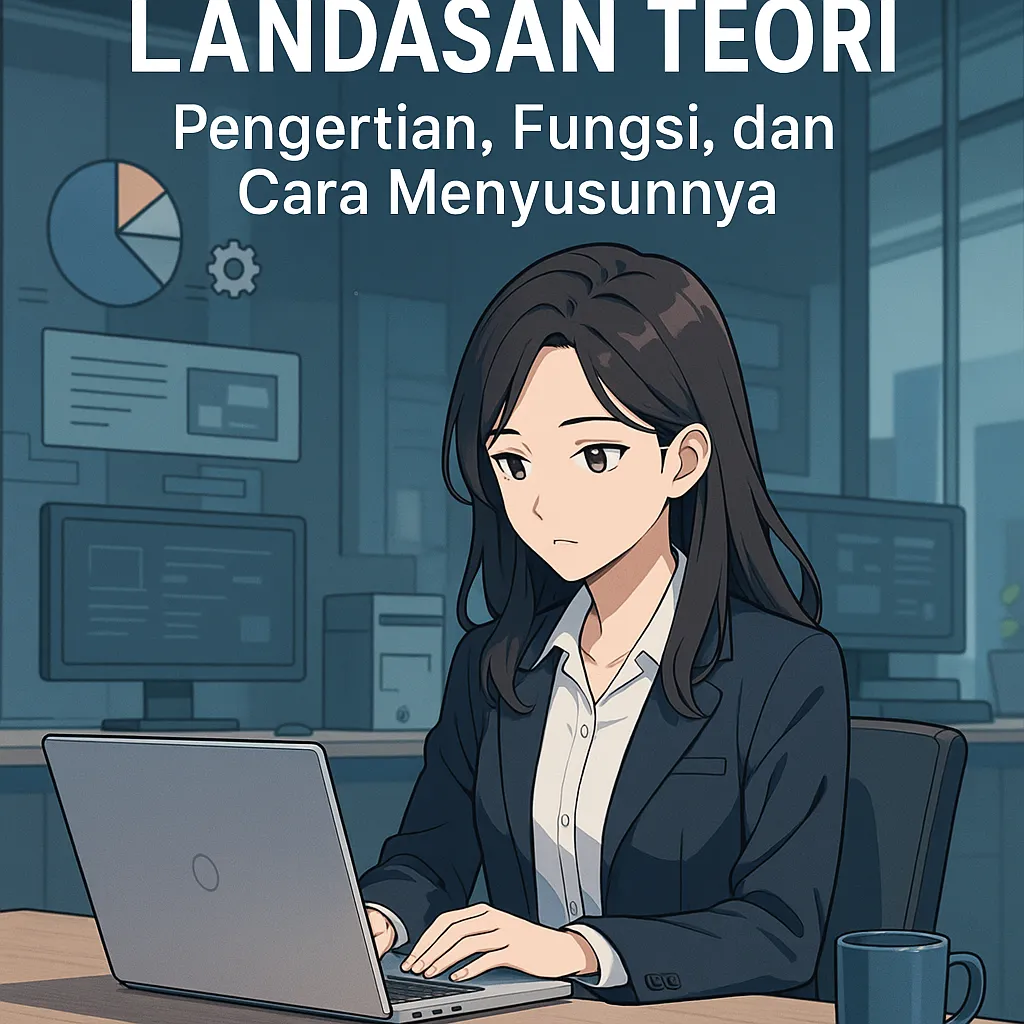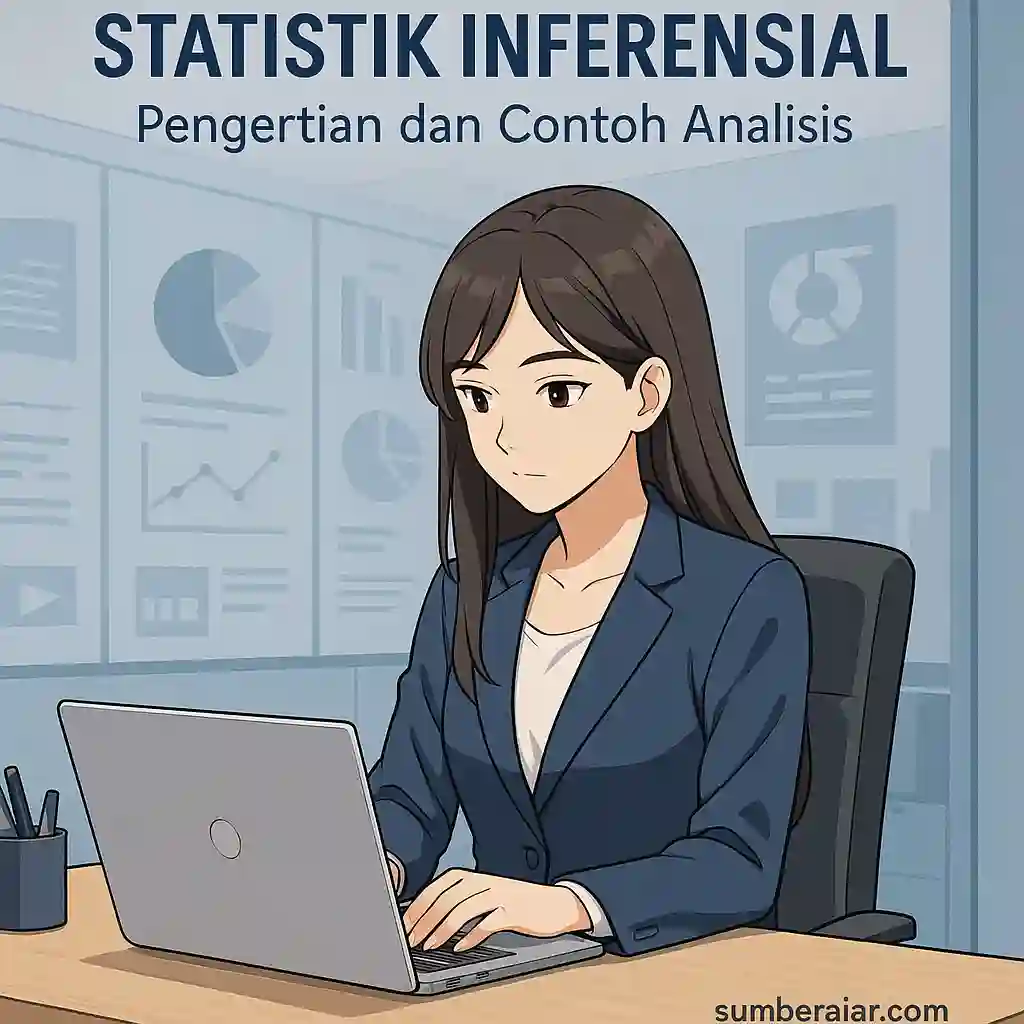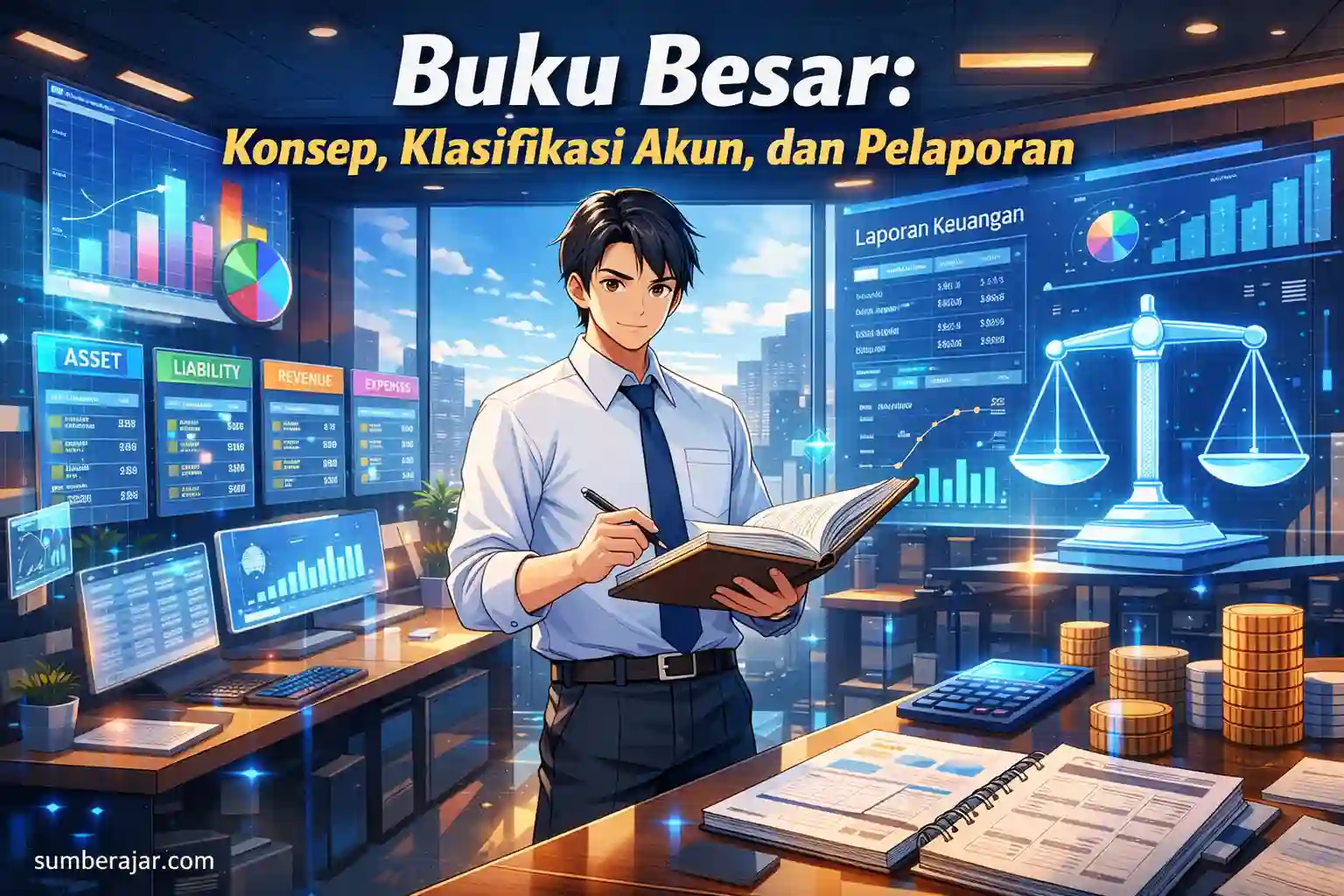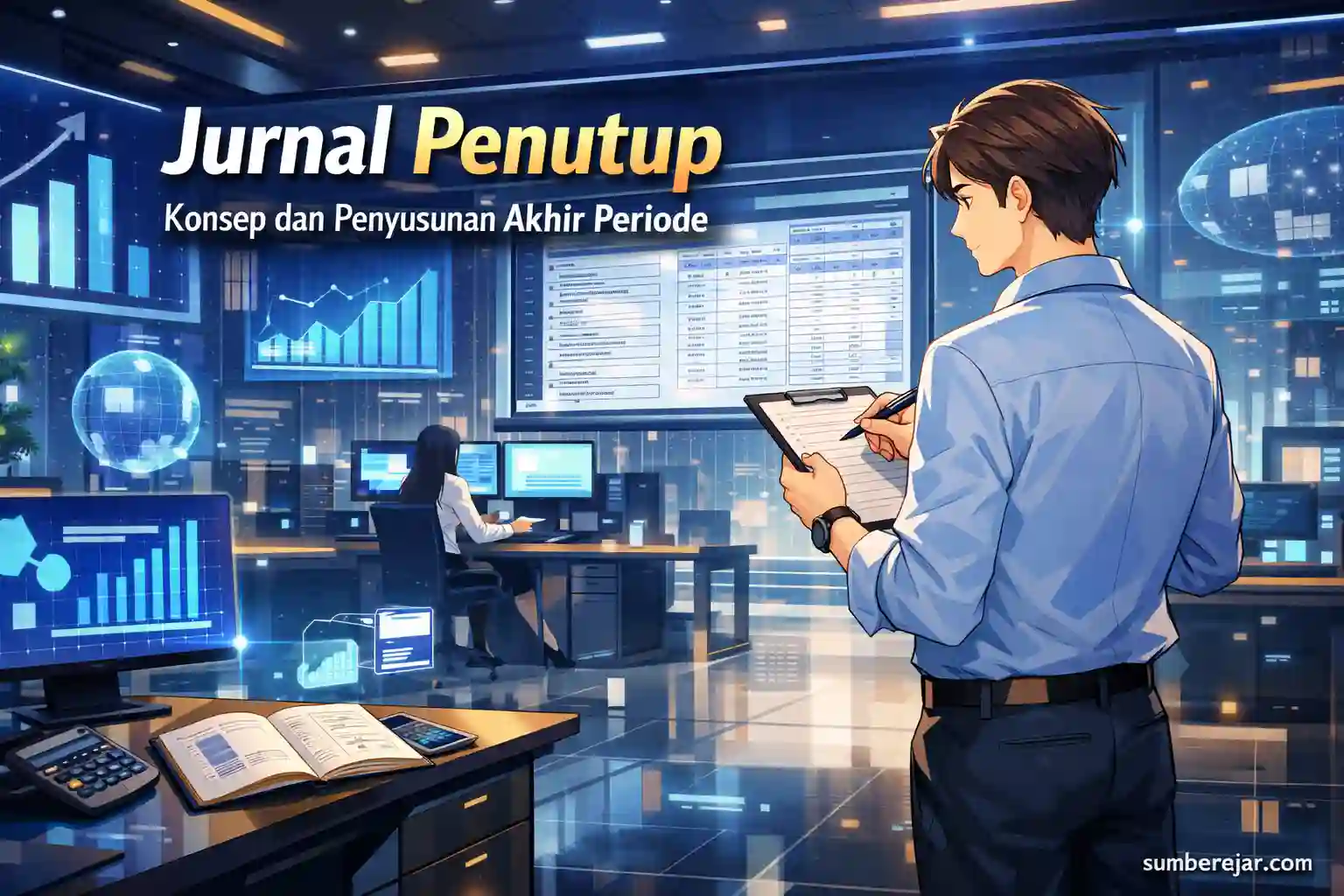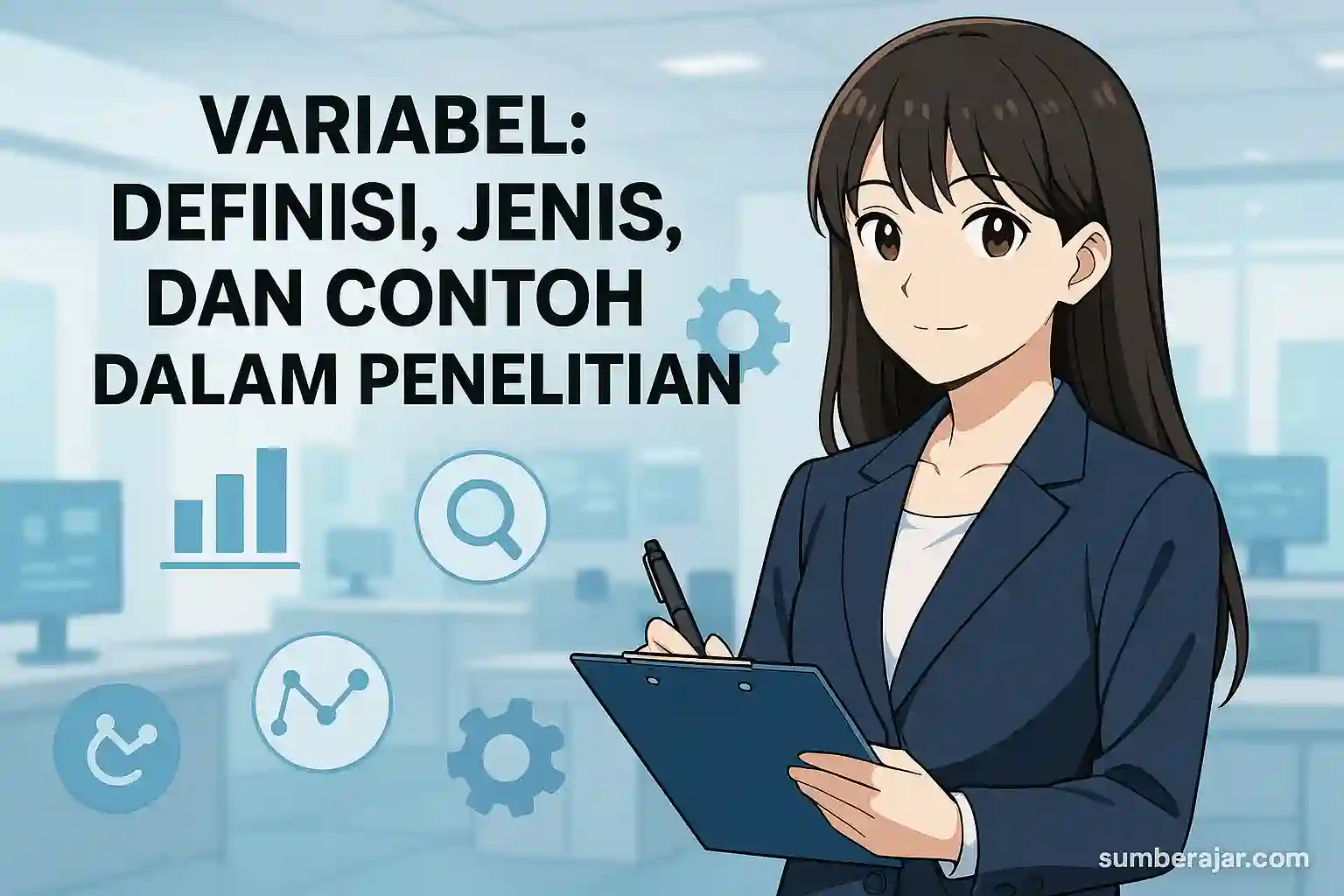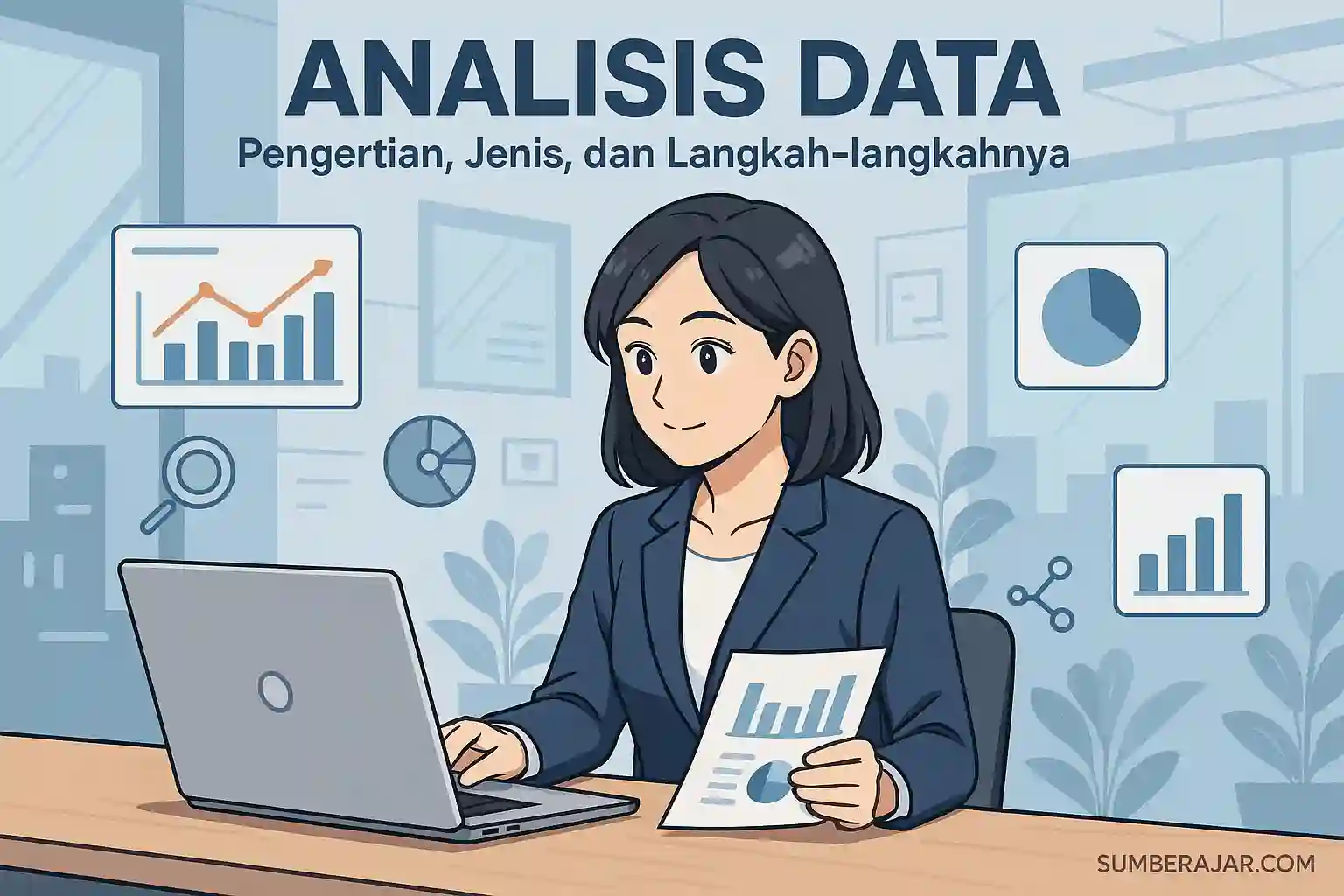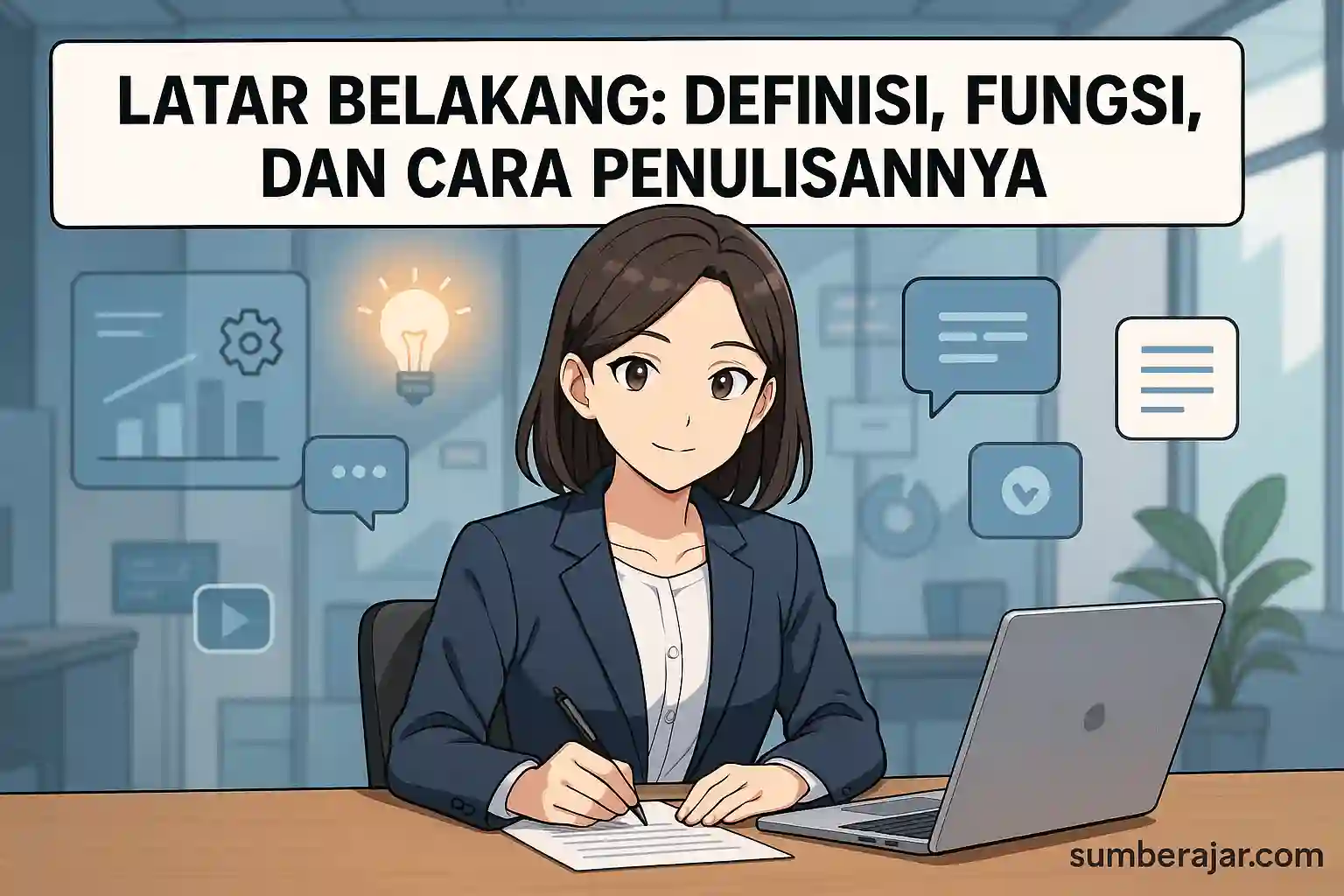Obyektivisme: Pengertian dan Kritiknya
Pendahuluan
Dalam ranah filsafat dan ilmu pengetahuan, konsep “obyektivisme” (atau objektivisme) sering muncul sebagai landasan pemikiran yang meyakini bahwa ada realitas, nilai, atau pengetahuan yang berdiri sendiri dari pikiran atau konteks sosial-kultural manusia. Pemahaman tentang obyektivisme ini penting karena ia menjadi salah satu pilar dalam ilmuwan yang ingin menghasilkan pengetahuan netral dan universal. Namun di sisi lain, paham ini juga memperoleh banyak kritik dari berbagai aliran yang mempertanyakan apakah benar pengetahuan atau realitas dapat lepas sepenuhnya dari subjek yang mengenal, konteks yang mempengaruhi, dan nilainilai yang melekat dalam aktivitas manusia. Tulisan ini akan membahas terlebih dahulu definisi obyektivisme secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan menurut para ahli; kemudian dilanjutkan dengan aspek-aspek utama dari obyektivisme; dan diakhiri dengan kritik-kritik utama terhadapnya. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai apakah dan bagaimana obyektivisme tetap relevan, sekaligus tantangannya dalam perkembangan ilmu dan pemikiran kontemporer.
Definisi Obyektivisme
Definisi Obyektivisme Secara Umum
Secara umum, obyektivisme dapat dipahami sebagai pandangan bahwa realitas atau fakta-objek berada “di luar” subjek yang mengamati; artinya objek pengetahuan atau nilai memiliki eksistensi atau kepastian yang tidak sepenuhnya bergantung pada sudut pandang individu atau kelompok. Sebagai contoh, dalam kajian metode ilmiah sering dikatakan bahwa peneliti harus bersikap objektif, yaitu berusaha agar hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh keinginan, prasangka atau kepentingan pribadi (lihat secara analog “objektivitas” dalam istilah penelitian). [Lihat sumber Disini - info.populix.co] Pendekatan umum semacam ini meletakkan bahwa ada standar yang dapat dipakai secara universal untuk menilai kebenaran, nilai atau fakta. Sebuah sumber menyebutkan bahwa “obyektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantaraan indera kita tidak berdiri sendiri, lepas dari kesadaran serta keadaan kesadaran tersebut”. [Lihat sumber Disini - jurnaliainpontianak.or.id]
Definisi Obyektivisme dalam KBBI
KBBI tidak secara langsung memberikan entri “obyektivisme” (dengan e o/y) yang lengkap, namun memberikan entri untuk kata turunan seperti “objektivitas” yang sangat dekat maknanya. Menurut KBBI daring:
objéktivitas /objéktivitas/ n sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan. [Lihat sumber Disini - kbbi.web.id]
Dengan demikian, secara terminologis di Indonesia, obyektivisme dapat diartikan sebagai sikap atau pandangan yang menekankan pengakuan terhadap fakta/realitas atau nilai yang tidak terdistorsi oleh subjektivitas individu atau kelompok.
Definisi Obyektivisme Menurut Para Ahli
Berikut ini beberapa definisi dari tokoh atau kajian akademik yang menguraikan konsep obyektivisme:
- Karl R. Popper, Dalam sejumlah tulisan disebut bahwa “pengetahuan dalam pengertian obyektivisme … sepenuhnya independen dari klaim seseorang untuk mengetahuinya” dan bahwa “pengetahuan itu terlepas dari keyakinan seseorang atau kecenderungan untuk menyetujui atau menggunakannya untuk bertindak”. (Sumber tidak disebutkan halaman persisnya) [Lihat sumber Disini - discovery.researcher.life]
- Max Scheler, Dalam kajian fenomenologi nilai disebutkan bahwa obyektivisme nilai (value-objectivism) menurut Scheler menekankan bahwa nilai-nilai bersifat objektif, artinya bukan sekadar konstruksi subjektif manusia, melainkan memiliki keberadaan independen. [Lihat sumber Disini - researchgate.net]
- Dalam artikel “Epistemologi Ilmu Dalam Perspektif Filsafat Kontemporer” disebut bahwa paradigma kontemporer telah menggugat asumsi obyektivitas dan universalisme pengetahuan. [Lihat sumber Disini - ejournal.sembilanpemuda.id]
- Dalam makalah “Memahami Objektivitas dalam Penilaian Moral” oleh Fakhruddin disebut bahwa pada zaman modern pandangan saintistik mendefinisikan obyektivitas sebagai kesetiaan terhadap realitas yang dapat dibuktikan secara publik dan lepas dari keterlibatan subjek. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa obyektivisme menekankan tiga elemen utama: (1) realitas / objek pengetahuan berdiri sendiri dari subjektivitas; (2) kemampuan manusia untuk mengenal atau menangkap objek tersebut secara tepat atau “netral”; dan (3) adanya kriteria atau standar yang universal atau setidak-nya dapat diterapkan secara umum untuk menilai kebenaran atau nilai.
Aspek-Aspek Utama Obyektivisme
Dalam pembahasan lebih lanjut, kita dapat memisahkan beberapa aspek kunci dari obyektivisme yang sering dibahas dalam filsafat ilmu, epistemologi, dan aksiologi (nilai). Beberapa di antaranya adalah:
Realitas Independen (Ontologis)
Salah satu pilar obyektivisme adalah anggapan bahwa ada sebuah realitas atau objek yang eksis secara independen dari kesadaran atau interpretasi manusia. Dengan kata lain: objek penelitian atau objek nilai bukan semata-mata hasil kreasi pikiran manusia, melainkan sesuatu “di luar” yang dapat ditemukan, diketahui, atau dikenali. Sebuah kajian menyebut bahwa “objektif (…) karena realitas itu independen dari subjek”. [Lihat sumber Disini - e-journal.stishid.ac.id]
Pengetahuan yang Netral dan Universal (Epistemologis)
Aspek selanjutnya adalah bahwa pengetahuan mengenai realitas tersebut sebaiknya diperoleh, ditransmisikan, dan dipertanggungjawabkan secara netral, yaitu dengan meminimalkan bias subjektif, kepentingan partikular, atau nilai terpendam. Dalam hal ini, peneliti atau pengamat diharapkan bersikap “jarak” terhadap objek (mind the subject-object separation). Hal ini tampak dalam tulisan yang menyebut bahwa paradigma modern menekankan bahwa ilmu harus “bebas nilai” atau netral. [Lihat sumber Disini - e-journal.stishid.ac.id]
Nilai Objektif (Aksiologis)
Obyektivisme juga muncul dalam diskusi nilai moral atau estetika: bahwa nilai-nilai tertentu bersifat objektif, bukan sekadar subjektif atau relatif terhadap individu atau budaya. Sebagai contoh, Scheler dan lainnya mengemukakan bahwa nilai-nilai baik, gugun, keadilan dapat dipahami sebagai entitas objektif yang dapat ditemukan oleh manusia yang mau memerhatikannya. [Lihat sumber Disini - researchgate.net]
Metodologi Ilmiah dan Objektivisme
Dalam wacana filsafat ilmu, obyektivisme menjadi dasar bagi metode ilmiah klasik: observasi, pengukuran, verifikasi, generalisasi, dan pemisahan antara subjek/peneliti dan objek yang diteliti. Misalnya, dalam artikel “Epistemologi Ilmu Pengetahuan…” disebut bahwa paradigma ilmiah modern menekankan rasionalitas, objektivitas, dan keterbukaan terhadap koreksi. [Lihat sumber Disini - prin.or.id]
Kritik Terhadap Obyektivisme
Walaupun obyektivisme memiliki daya tarik dalam memberi fondasi bagi pengetahuan dan nilai yang “kuat”, banyak kritik telah diarahkan terhadapnya dari berbagai sudut pandang: epistemologi kontemporer, sosiologi ilmu, filsafat post-modern, feminis, dan kajian nilai. Berikut beberapa kritik utama:
Kritik Relativisme dan Konstruktivisme
Salah satu kritik penting ialah bahwa pengetahuan atau fakta tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai “di luar” subjek atau budaya manusia, melainkan sering dibentuk oleh konteks sosial, sejarah, budaya, dan praktik ilmiah itu sendiri. Sebuah artikel menyebut bahwa epistemologi kontemporer “menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan politik dalam pembentukan pengetahuan” dan bahwa aliran seperti konstruktivisme, pragmatisme, post-struktur, dan teori pengetahuan sosial ‘mengubah cara pandang’ bahwa pengetahuan bersifat tetap atau objektif. [Lihat sumber Disini - ejournal.sembilanpemuda.id]
Contoh lainnya: Dalam makalah “Embodied Engagement, Context, and Objectivity” disebut bahwa fakta ilmiah bukan hanya temuan pasif yang mencerminkan realitas objektif, melainkan konstruksi sosial yang melibatkan negosiasi, instrumentasi, dan konsensus komunitas ilmiah. [Lihat sumber Disini - journal.unusia.ac.id]
Kritik Terhadap Netralitas Ilmu
Banyak pemikir menyoroti bahwa klaim “ilmu harus bebas nilai” atau “netral” sering mengabaikan bahwa aktivitas ilmiah dilakukan oleh manusia yang memiliki nilai, keinginan, kepentingan, dan berada dalam struktur sosial-politik tertentu. Sebagai contoh, dalam kajian “Objektivitas dan Subyektivitas dalam Sains, Ilmu…” disebut bahwa paham positivisme yang mengusung bebas nilai dan mekanisme telah mendapat kritik tajam karena tidak mempertimbangkan bahwa nilai dan subjek tetap mempengaruhi pengetahuan. [Lihat sumber Disini - e-journal.stishid.ac.id]
Kritik Moral dan Nilai yang Objektif
Dalam ranah aksiologi, kritik muncul bahwa menyatakan nilai moral sebagai objektif dan independen dari subjek seringkali mengabaikan realitas pluralitas budaya, pengalaman manusia berbeda, dan interpretasi nilai yang variatif. Fakhruddin misalnya menyebut bahwa norma moral yang diklaim objektif harus tetap mempertimbangkan bahwa subjek penilai, konteks sosial dan interpretasi manusia tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
Kritik Dari Perspektif Politik dan Kekuasaan
Lebih lanjut, kajian sosiologi ilmu menyoroti bagaimana klaim obyektivitas dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atau hegemoni tertentu, karena “apa yang dianggap fakta” atau “apa yang disebut objektif” sering ditetapkan oleh institusi, budaya, atau pihak yang berkuasa. Sebuah artikel menyebut bahwa “pengetahuan yang sah” tidak pernah netral, melainkan dibentuk oleh rezim wacana yang menentukan kebenaran dalam konteks historis tertentu. [Lihat sumber Disini - journal.unusia.ac.id]
Kritik Terhadap Absolutisme Obyektivisme
Kritik berupa bahwa paham obyektivisme seringkali memunculkan absolutisme, yaitu asumsi bahwa pengetahuan atau nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak berubah, dan dapat diakses secara sama oleh semua orang. Namun kenyataannya, kondisi manusia, batasan kognitif, budaya, bahasa, dan konteks sejarah menunjukkan bahwa akses ke ‘objek’ atau ‘nilai’ tidak semudah itu. Kritik ini juga melihat bahwa keberadaan perspektif subjek dan pengalaman manusia tidak dapat diabaikan. [Lihat sumber Disini - jurnaliainpontianak.or.id]
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa obyektivisme merupakan pandangan yang signifikan dalam pemikiran filsafat, ilmu pengetahuan, dan etika. Pandangan ini menegaskan bahwa realitas atau nilai berdiri secara independen dari subjek, bahwa pengetahuan dapat diperoleh secara netral dan universal, dan bahwa nilai-nilai tertentu mungkin bersifat objektif. Namun demikian, obyektivisme tidak luput dari kritik yang cukup tajam: bahwa pengetahuan dan nilai tidak bisa dibebaskan sepenuhnya dari konteks sosial, budaya, maupun subjektivitas manusia; bahwa klaim netralitas dan universalisme seringkali menyembunyikan kekuasaan atau ideologi; dan bahwa pengalaman manusia yang plural menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara subjek, objek, dan nilai.
Dengan demikian, dalam praktik penelitian, pengembangan ilmu, maupun penilaian nilai moral ataupun estetis, kita perlu mempertimbangkan bahwa meskipun aspirasi untuk objektivitas penting, yaitu keinginan untuk menghindari bias, memastikan kejujuran, dan obyektivitas, kita juga harus menyadari keterbatasan-keterbatasan dari asumsi obyektivisme: bahwa kita tidak sepenuhnya “di luar” objek yang kita amati, bahwa interpretasi dan konteks tetap memainkan peran, dan bahwa refleksi kritis terhadap posisi kita sebagai peneliti atau pemikir adalah perlu.
Dengan pendekatan yang sadar terhadap kelebihan dan keterbatasan obyektivisme, kita bisa mengembangkan praktik ilmiah, etika, dan pemikiran yang lebih matang: bukan sekadar mengejar “kebenaran mutlak” di luar manusia, tetapi juga memperhitungkan bagaimana manusia, konteks, dan nilai-nilai mempengaruhi proses pengenalan kita terhadap dunia dan penilaian kita terhadapnya.