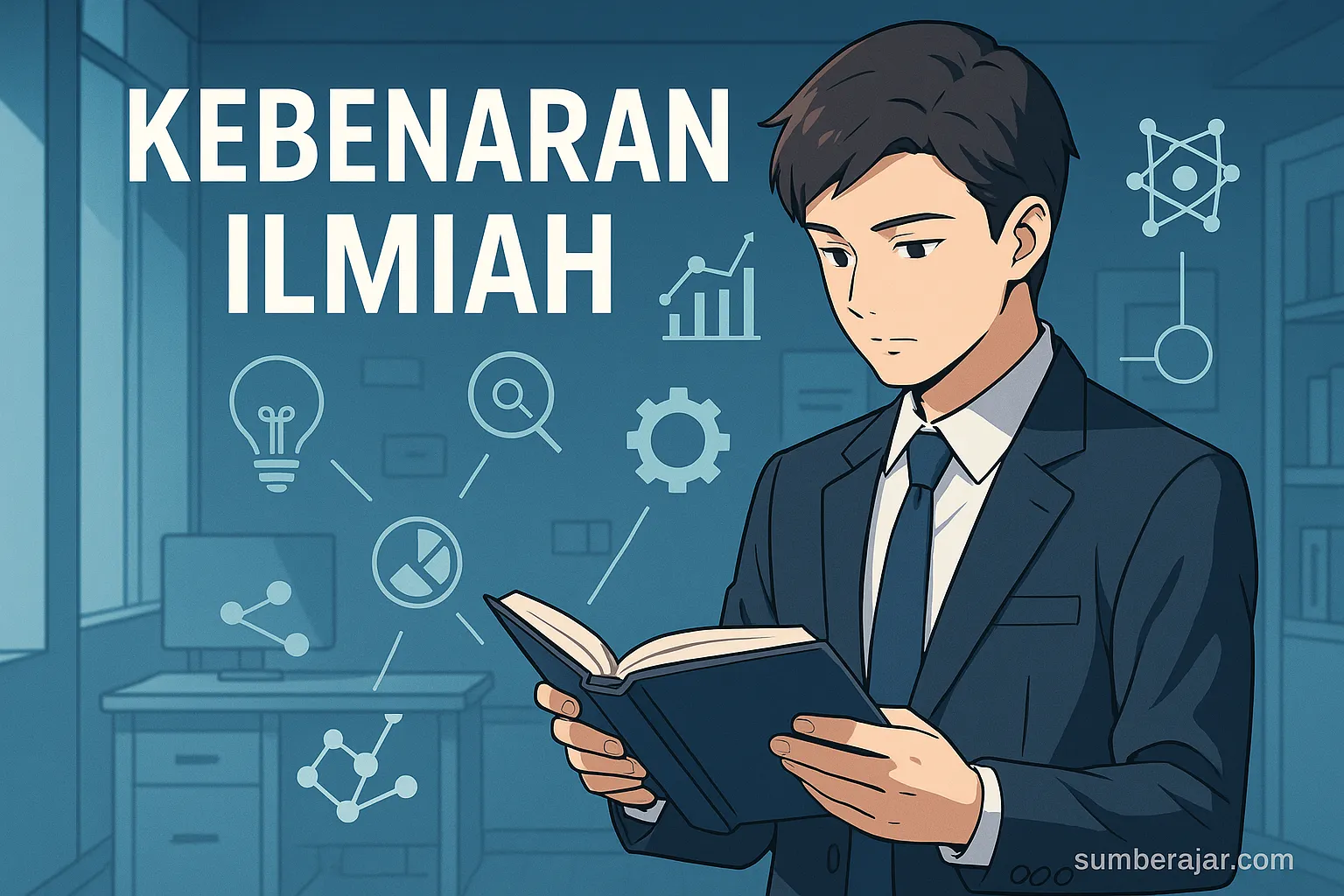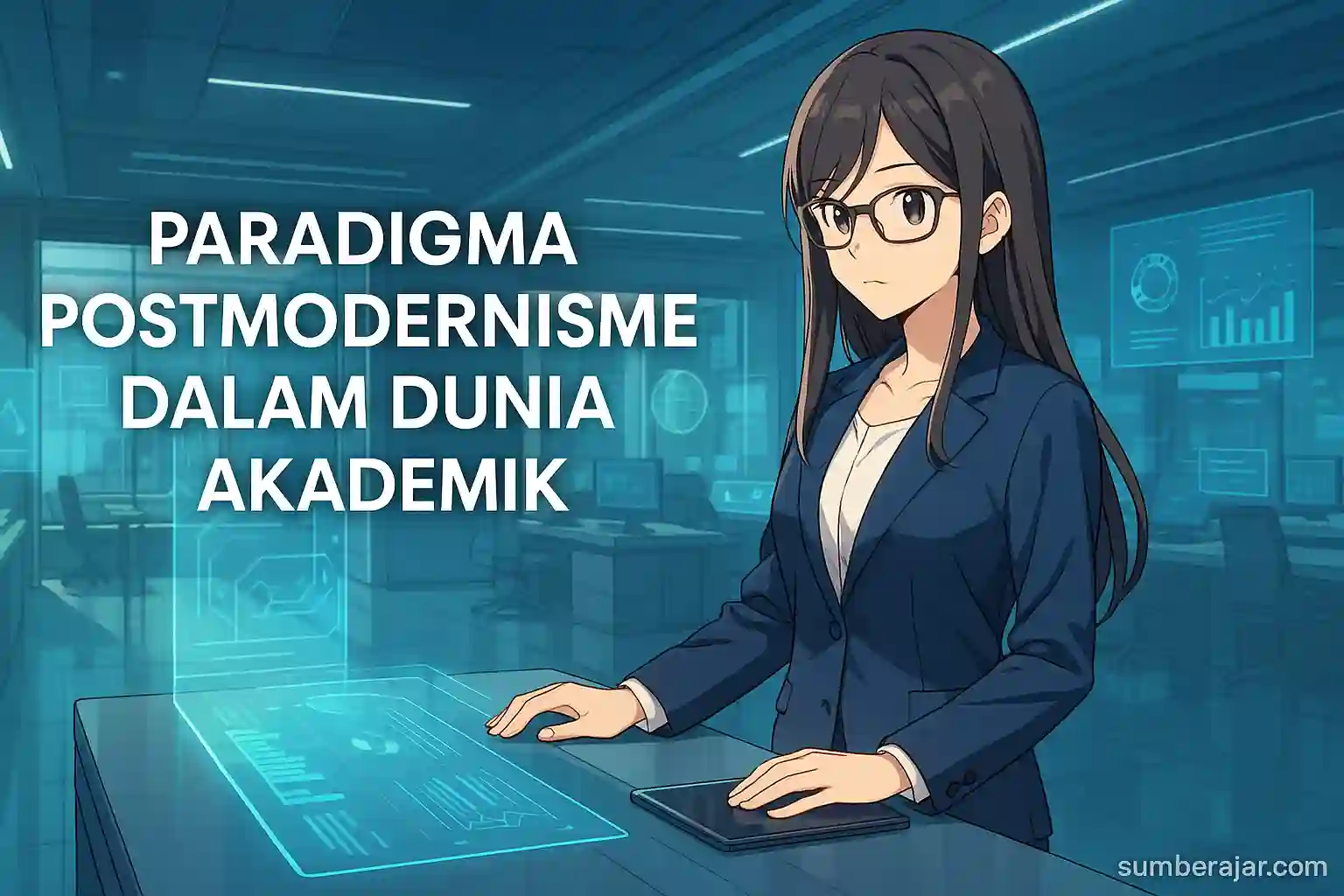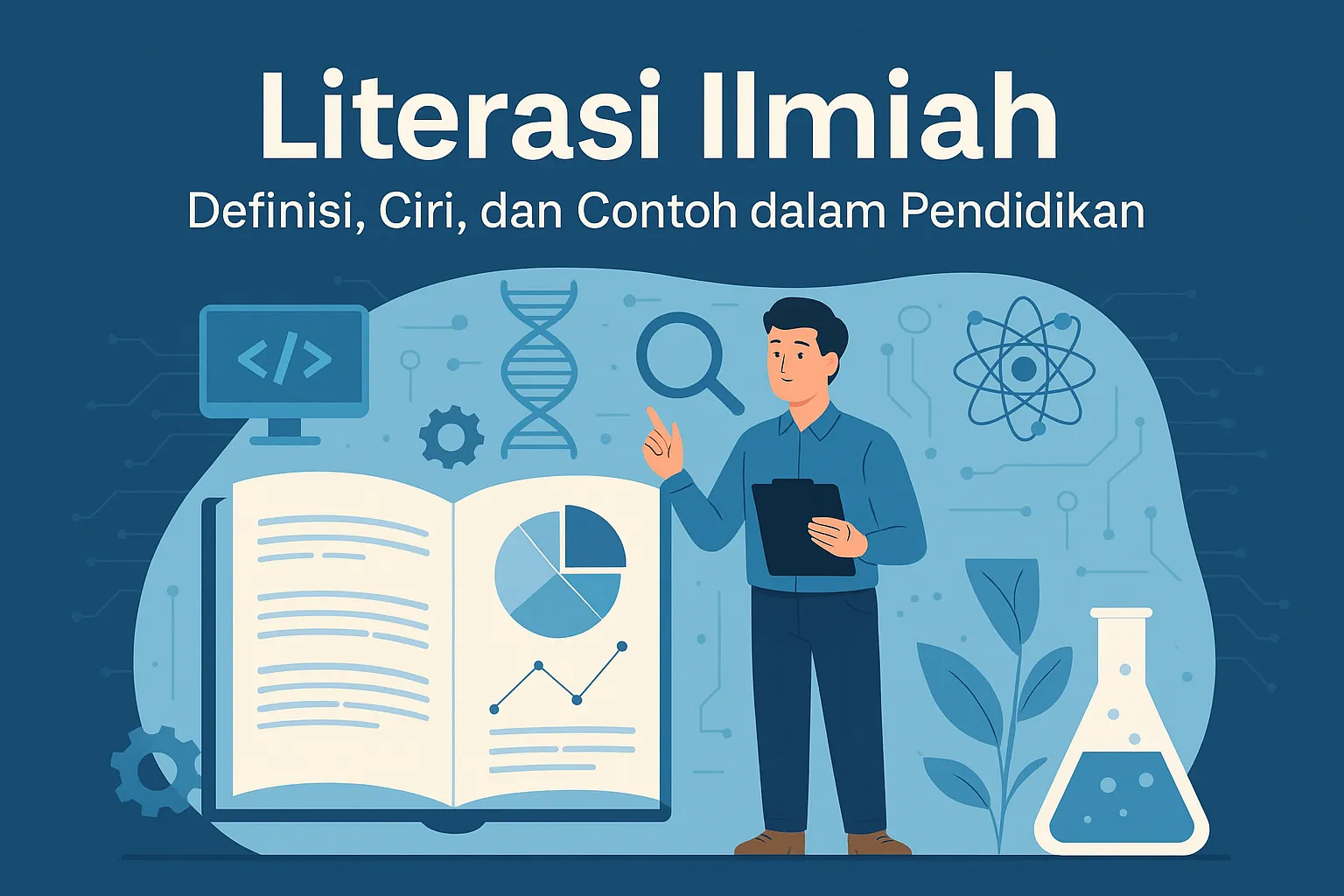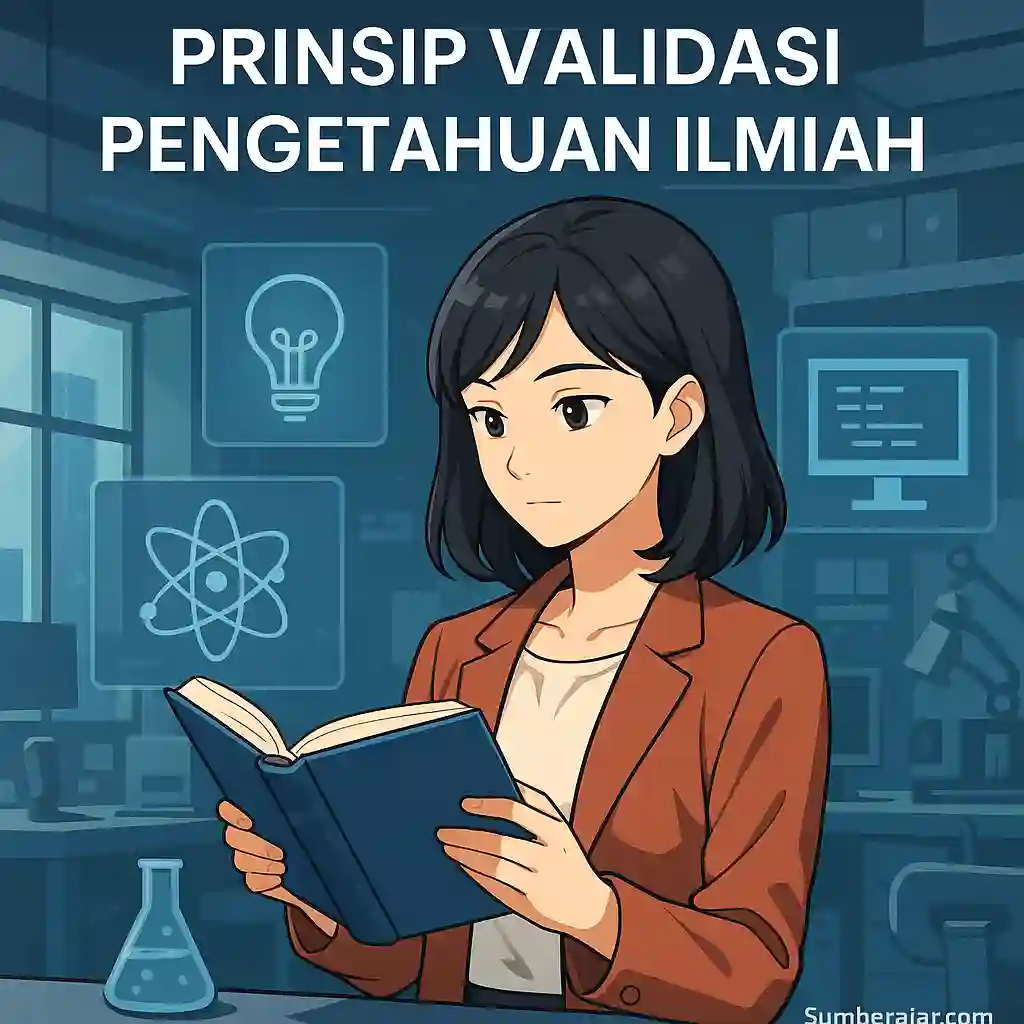Relativisme Ilmiah: Pengertian dan Kritiknya
Pendahuluan
Dalam perkembangan epistemologi dan filsafat ilmu, istilah relativisme sering muncul sebagai tantangan terhadap keyakinan lama bahwa ilmu pengetahuan bersifat mutlak, objektif, dan universal. Pada era modern dan pos-modern, muncul pertanyaan: apakah setiap klaim ilmiah benar secara universal ataukah kebenaran ilmu tergantung pada kerangka budaya, sosial, historis, atau paradigma ilmiah yang berlaku? Salah satu jawaban muncul dalam bentuk konsep relativisme ilmiah. Konsep ini menimbulkan debat yang cukup tajam: di satu sisi menjadi panggilan untuk refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi ilmiah; di sisi lain dikhawatirkan melemahkan kepercayaan terhadap ilmu dan kebenaran objektif. Artikel ini akan membahas pengertian relativisme ilmiah (termasuk definisinya secara umum, dalam KBBI, dan menurut para ahli), kemudian membahas berbagai kritik terhadapnya, serta implikasi bagi ilmu pengetahuan.
Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan membantu kita memahami: (1) apa yang dimaksud dengan relativisme ilmiah; (2) bagaimana ia muncul dalam ranah ilmu; (3) argumen-kritik yang diarahkan kepadanya; dan (4) apa relevansinya bagi praktik ilmiah dan metodologi penelitian saat ini.
Definisi Relativisme Ilmiah
Definisi Relativisme Ilmiah Secara Umum
Secara umum, relativisme dalam ranah ilmu bisa dipahami sebagai pandangan bahwa standar, metode, kerangka, atau hasil ilmiah tidak bersifat mutlak universal, melainkan bergantung pada konteks historis, sosial, budaya, atau paradigma ilmiah yang melatarbelakanginya. Sebagaimana dikemukakan: “Relativism, roughly put, is the view that truth and falsity, right and wrong, standards of reasoning, and procedures of justification are products of differing conventions and frameworks of assessment and that their authority is confined to the context giving rise to them.” [Lihat sumber Disini - plato.stanford.edu]
Dalam konteks ilmu pengetahuan, maka, relativisme ilmiah mengusulkan bahwa klaim-klaim kebenaran ilmiah dapat berubah, bergeser atau terkait kuat dengan paradigma ilmiah yang berlaku, dan bukanlah sesuatu yang absolut yang berlaku untuk semua zaman dan budaya. Pendekatan ini mengigatkan bahwa ilmu tidak hanya dibangun oleh alam semesta “apa adanya”, tetapi juga oleh manusia dalam konteks tertentu.
Definisi Relativisme Ilmiah dalam KBBI
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah relativisme belum secara spesifik didefinisikan dalam ranah “ilmiah” di entri mandiri sebagai “relativisme ilmiah”, namun definisi umum ‘relativisme’ pada KBBI mencakup: “aliran yang menyatakan bahwa nilai, ukuran, atau kebenaran tidak bersifat mutlak melainkan tergantung pada kondisi, keadaan, atau pembanding”. Dengan demikian, dalam konteks “relativisme ilmiah” maka dapat diartikan sebagai: aliran yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak tetapi bergantung pada kerangka ilmu, budaya, atau sejarah.
Definisi Relativisme Ilmiah Menurut Para Ahli
Berikut beberapa definisi menurut para ahli yang relevan dalam ranah filsafat ilmu dan metodologi penelitian:
- Thomas Kuhn (meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “relativisme ilmiah”) melalui konsep paradigma dan revolusi ilmiah menyatakan bahwa perkembangan ilmu tidak bersifat kumulatif linear melainkan melalui pergantian paradigma, di mana “apa yang dianggap ilmiah” bergantung pada paradigma yang berlaku. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
- Paul Feyerabend dalam karya-nya seperti Against Method mengemukakan bahwa tidak ada satu metode ilmiah tunggal yang superior dan bahwa sains bersaing dengan bentuk-bentuk pengetahuan lain; dengan demikian ia menunjukkan implikasi relativistik terhadap klaim keunggulan sains. [Lihat sumber Disini - yogapermanawijaya.wordpress.com]
- Richard Rorty, seorang filsuf kontemporer, menyatakan bahwa kebenaran ilmiah adalah hasil dari percakapan dalam komunitas ilmuwan, bukan cermin realitas mutlak yang bebas konteks. [Lihat sumber Disini - belaindika.nusaputra.ac.id]
- Dalam artikel akademik, Sophie Juliane Veigl menyebut bahwa “scientific pluralism” sering berhadapan dengan “epistemic relativism” yang menyatakan bahwa norma-norma epistemik tergantung pada konteks budaya atau kerangka ilmiah. [Lihat sumber Disini - link.springer.com]
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka relativisme ilmiah bisa dirumuskan sebagai: suatu posisi epistemologis dan metodologis yang menegaskan bahwa klaim, metode, dan hasil ilmu pengetahuan bergantung pada kerangka sosial, sejarah, budaya, atau paradigma ilmiah yang berlaku, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap berlaku secara mutlak dan universal.
Aspek-Aspek Utama Relativisme Ilmiah
Ketergantungan pada Paradigma dan Konteks
Relativisme ilmiah menekankan bahwa ilmu tidak berdiri di luar konteks: paradigma ilmiah, tradisi penelitian, kondisi sosial-kultural, bahasa ilmiah, dan institusi riset mempengaruhi bagaimana pertanyaan ilmiah diajukan, metode yang dipilih, serta interpretasi hasilnya. Misalnya, Kuhn menunjukkan bahwa “normal science” dalam suatu paradigma tetap beroperasi dalam asumsi-asumsi tertentu yang mungkin tidak dipersoalkan sampai terjadi krisis paradigma. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
Multiple Teori dan Pluralitas Penjelasan Ilmiah
Dalam kerangka relativisme ilmiah, tidak selalu hanya satu teori tunggal yang benar, melainkan bisa terdapat pluralitas teori atau model ilmiah yang sah dalam kerangka yang berbeda. Artikel oleh Veigl menyebut bahwa scientific pluralism dan epistemic relativism memiliki hubungan yang kompleks karena adanya pluralitas teori dalam sains. [Lihat sumber Disini - link.springer.com]
Tidak Ada Standar Tunggal dan Universal untuk Ilmu
Relativisme ilmiah mengkritik gagasan bahwa ada satu metode ilmiah tunggal yang menjamin keberhasilan atau keberlakuan universal dari ilmu. Sebagaimana Feyerabend mengemukakan, metode ilmiah tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya cara. [Lihat sumber Disini - yogapermanawijaya.wordpress.com]
Implikasi terhadap Objektivitas dan Kebenaran Ilmiah
Karena relativisme ilmiah menekankan kontekstualitas ilmu, maka pandangan klasik bahwa ilmu memiliki objektivitas mutlak, netralitas nilai, atau kebenaran universal menjadi dipersoalkan. Sebagaimana dalam tulisan populer disebut bahwa relativisme “menggoyang arti objektivitas ilmiah yang selama beradab-abad menjadi tolok ukur dari penelitian ilmiah” [Lihat sumber Disini - rumahfilsafat.com]
Kritik terhadap Relativisme Ilmiah
Kritik dari Perspektif Epistemik
Salah satu kritik klasik terhadap relativisme adalah argumen bahwa posisi “semua kebenaran bersifat relatif” secara logika sendiri menjadi sulit dipertahankan, karena jika relativisme itu mutlak maka ia sendiri menjadi klaim absolut, atau jika relatif maka relativisme itu pun “hanya relatif” dan bukan absolut. Kritik semacam ini dikenal sebagai “self-referential problem” atau “self-exceptioning fallacy”. [Lihat sumber Disini - en.wikipedia.org]
Selain itu, kritik lain menyatakan bahwa relativisme mengancam proses evaluasi ilmiah: jika semua kerangka ilmiah dianggap setara, bagaimana kita memilih antara teori yang lebih baik atau metode yang lebih valid? Artikel Veigl memuat kekhawatiran bahwa scientific pluralism jika terhubung dengan epistemic relativism bisa menjadi “apa saja boleh” (anything goes) sehingga menghancurkan kemampuan ilmiah untuk membedakan klaim yang lebih kuat. [Lihat sumber Disini - link.springer.com]
Kritik dari Perspektif Praktis Ilmu
Relativisme ilmiah juga dikritik karena dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan: jika metode dan hasil ilmu dianggap bergantung konteks saja, maka masyarakat bisa mempertanyakan validitas riset, standar ilmiah, atau rekomendasi ilmiah. Dengan kata lain, relativisme berpotensi menurunkan legitimasi ilmu.
Lebih lanjut, ilmu pengetahuan modern membutuhkan standar yang cukup konsisten untuk melakukan replikasi, verifikasi, dan penyempurnaan teori,relativisme yang ekstrem bisa menghambat hal tersebut.
Kritik dari Perspektif Nilai dan Etika Ilmu
Ilmu pengetahuan juga memiliki aspek nilai,misalnya dalam hal etika penelitian, penggunaan teknologi, pengaruh terhadap masyarakat,relativisme dapat menyebabkan anggapan bahwa “nilai-nilai ilmiah” pun bersifat relatif, sehingga standar etika dan tanggung jawab sosial ilmuwan bisa dipertanyakan. Sebagai contoh, dalam konteks moral ilmiah dan kebijakan riset, relativisme bisa digunakan untuk membenarkan perbedaan standar etika antar budaya.
Kritik Spesifik dalam Konteks Ilmu di Indonesia
Dalam tulisan “Problem Doktrin Relativisme” oleh Faisal Fauzi, disebut bahwa relativisme yang masuk ke dalam world-view intelektual dapat menghasilkan keraguan terhadap kebenaran; “Menurut paham ini kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak mutlak alias relatif.” [Lihat sumber Disini - ejournal.unida.gontor.ac.id] Hal ini menjadi kritik khusus dalam konteks epistemologi keilmuan di lingkungan Indonesia yang berkait dengan tradisi keilmuan, agama, dan nilai lokal.
Ringkasan Kritik Utama
- Ketidakmampuan mempertahankan klaim relativisme tanpa memunculkan kontradiksi internal.
- Potensi menjadikan ilmu tidak dapat dibedakan antara teori yang kuat atau lemah.
- Efek negatif bagi legitimasi dan praktik ilmiah (replikasi, standar, validitas).
- Potensi melemahkan tanggung jawab nilai dan etika dalam ilmu.
- Konsekuensi khusus dalam konteks budaya dan lokal yang menginginkan jaminan kebenaran atau objektivitas.
Relevansi dan Implikasi bagi Ilmu Pengetahuan Kontemporer
Implikasi Metodologis
Relativisme ilmiah mendorong peneliti untuk lebih sadar terhadap konteks penelitian: bagaimana paradigma, institusi, bahasa, budaya atau nilai sosial mempengaruhi pertanyaan, metode dan interpretasi. Artinya, transparansi kontekstual menjadi penting dalam publikasi ilmiah.
Implikasi Epistemologis
Dengan menerima bahwa ilmu bisa bersifat kontekstual, maka ilmu pengetahuan tidak lagi dilihat sebagai kumpulan fakta yang benar mutlak, tetapi sebagai proses yang terus berkembang, diperbaiki, dan dipengaruhi oleh kerangka ilmiah dan sosial. Hal ini menuntut sikap ilmiah yang lebih reflektif dan kritis terhadap asumsi dasar penelitian.
Implikasi Praktis dan Kebijakan
Dalam kebijakan riset, pendanaan, regulasi dan komunikasi ilmiah kepada publik, muncul kebutuhan untuk menjelaskan bukan hanya “apa riset itu”, tetapi “dalam konteks apa riset itu dilakukan”, serta bagaimana batas-generalitas hasil riset. Ini juga relevan untuk riset inter-disipliner dan global di mana perbedaan budaya dan konteks penelitian signifikan.
Implikasi Pendidikan Ilmu
Dalam pendidikan ilmu dan filsafat ilmu, siswa dan mahasiswa perlu diajak memahami bahwa sains bukan hanya “metode baku” semata, tetapi juga aktivitas sosial-kultural. Dengan demikian, diskusi mengenai relativisme ilmiah menjadi relevan dalam kurikulum filsafat ilmu untuk meningkatkan kematangan epistemik.
Implikasi bagi Penelitian di Lingkup Indonesia
Dalam konteks Indonesia, di mana pluralitas budaya, bahasa, institusi riset berbeda-beda, kesadaran terhadap relativisme ilmiah dapat membantu peneliti menyadari bias lokal atau paradigma dominan yang mungkin tidak universal. Namun, sekaligus penting untuk menyeimbangkan antara kesadaran kontekstual dan kebutuhan akan standar ilmiah yang sahih agar penelitian tetap kredibel.
Kesimpulan
Relativisme ilmiah merupakan posisi epistemologis dan metodologis yang mengusulkan bahwa ilmu pengetahuan dan klaim-kebenaran ilmiah tidak selalu bersifat mutlak dan universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, sejarah, dan paradigma ilmiah yang berlaku. Definisi ini dapat diuraikan secara umum, serta melalui perspektif kamus dan beberapa ahli (Kuhn, Feyerabend, Rorty, Veigl).
Meskipun menawarkan refleksi kritis yang penting terhadap asumsi-asumsi dominan dalam sains,termasuk objektivitas, universalitas, dan netralitas,relativisme ilmiah juga menghadapi kritik serius: dari kesulitan logis, potensi melemahkan praktik ilmiah, hingga implikasi nilai dan legitimasi sains.
Implicasi dari posisi ini cukup luas: bagi metodologi penelitian, kebijakan riset, pendidikan ilmu, dan konteks lokal seperti Indonesia. Sebagai peneliti atau praktisi ilmu, penting untuk tidak begitu saja menerima relativisme ekstrem yang menghapuskan standar ilmiah, tetapi juga tidak mengabaikan bahwa ilmu berkembang dalam kerangka kontekstual dan bahwa kesadaran terhadap kondisi tersebut dapat memperkuat kualitas penelitian. Dengan keseimbangan antara kepekaan kontekstual dan komitmen terhadap standar metodologis, discipline ilmu pengetahuan dapat terus berkembang secara bertanggung jawab dan relevan.
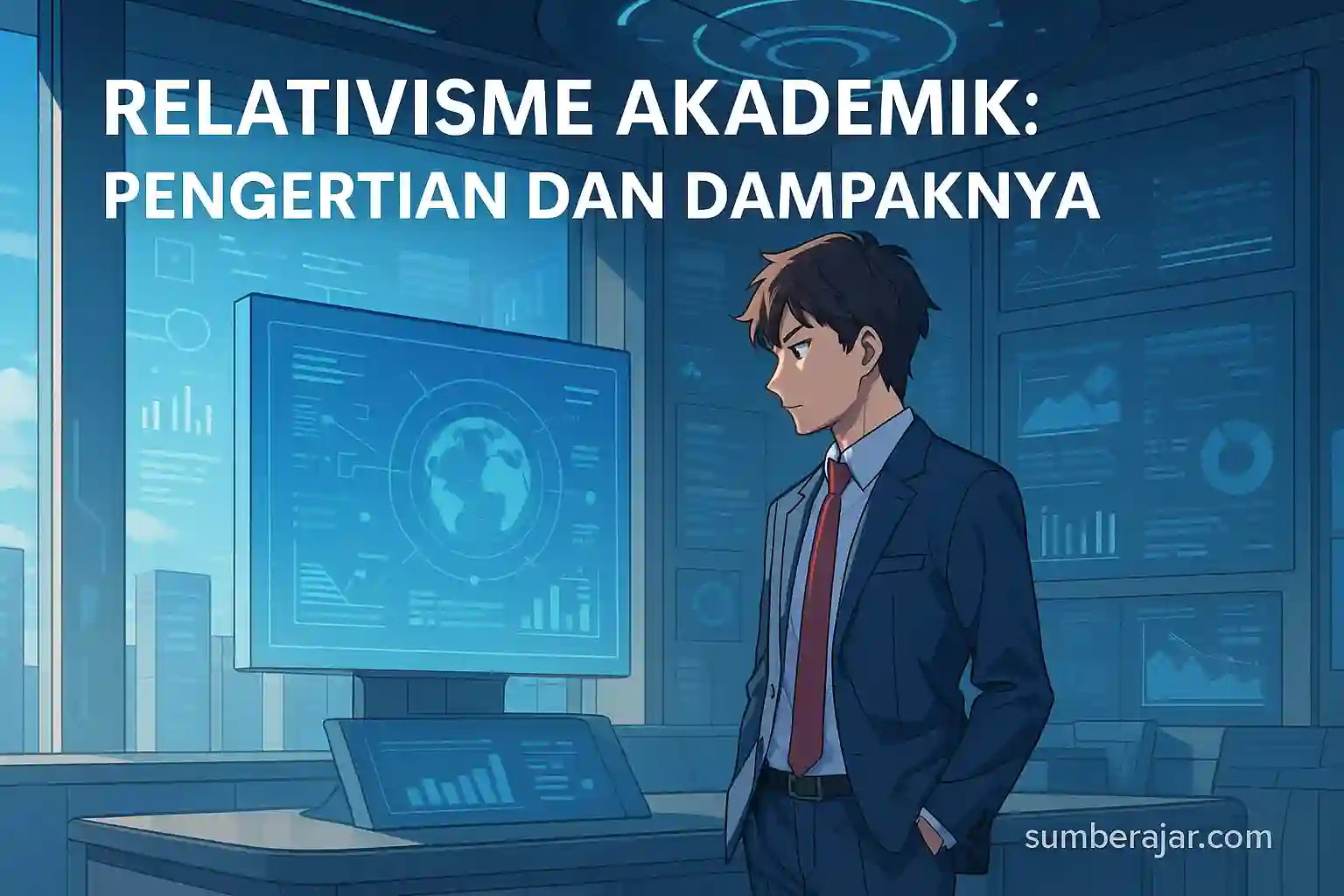
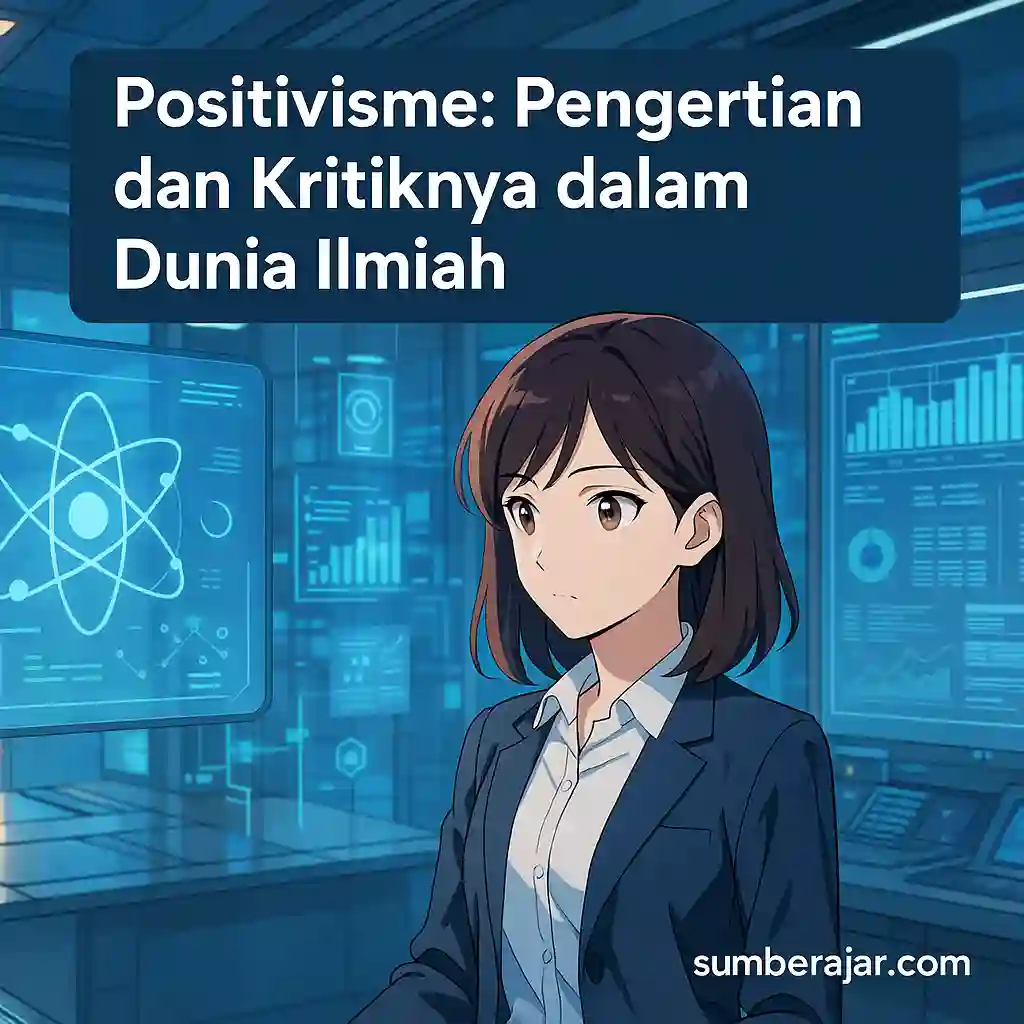



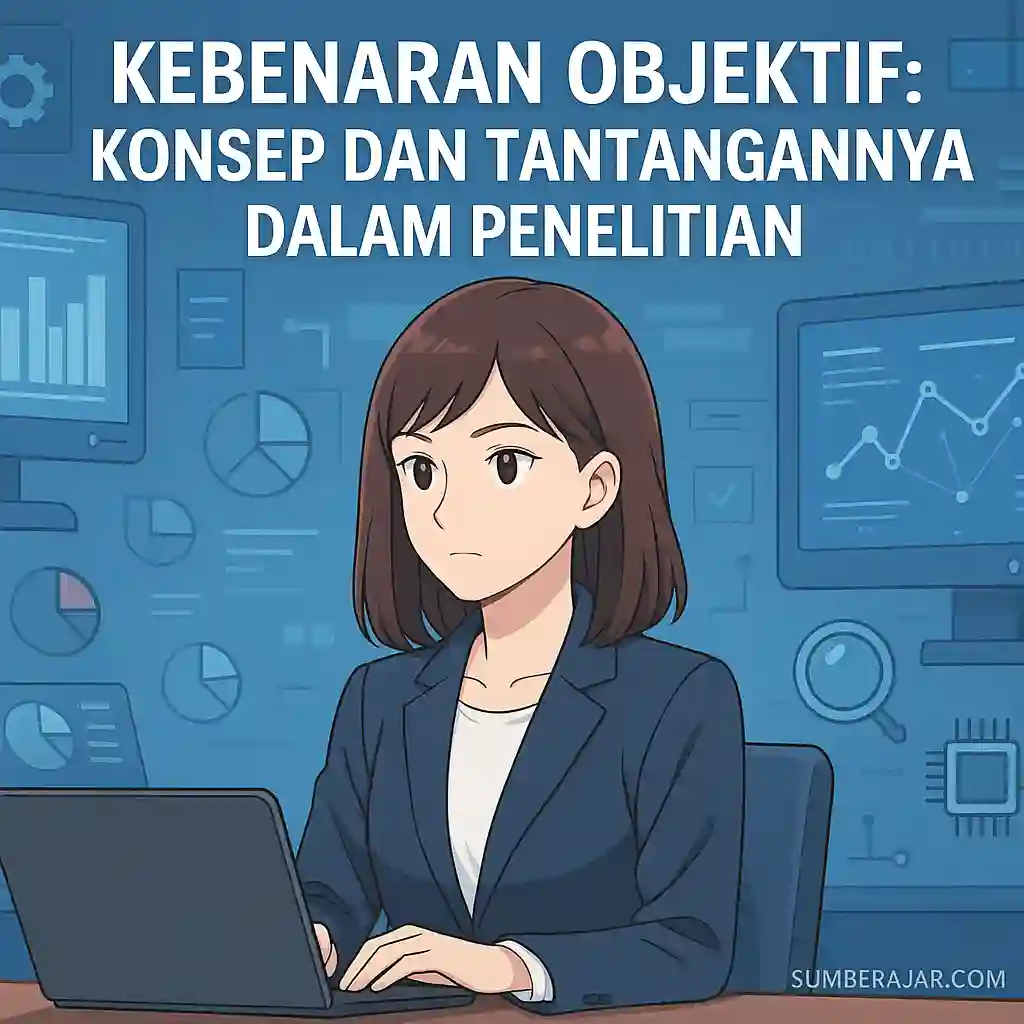




![Jurnal Ilmiah: Pengertian, Struktur, dan Contoh penulisan beserta sumber [pdf]](https://sumberajar.com/assest/uploads/2025/11/jurnal-ilmiah-pengertian-struktur-dan-contoh-penulisan.webp)