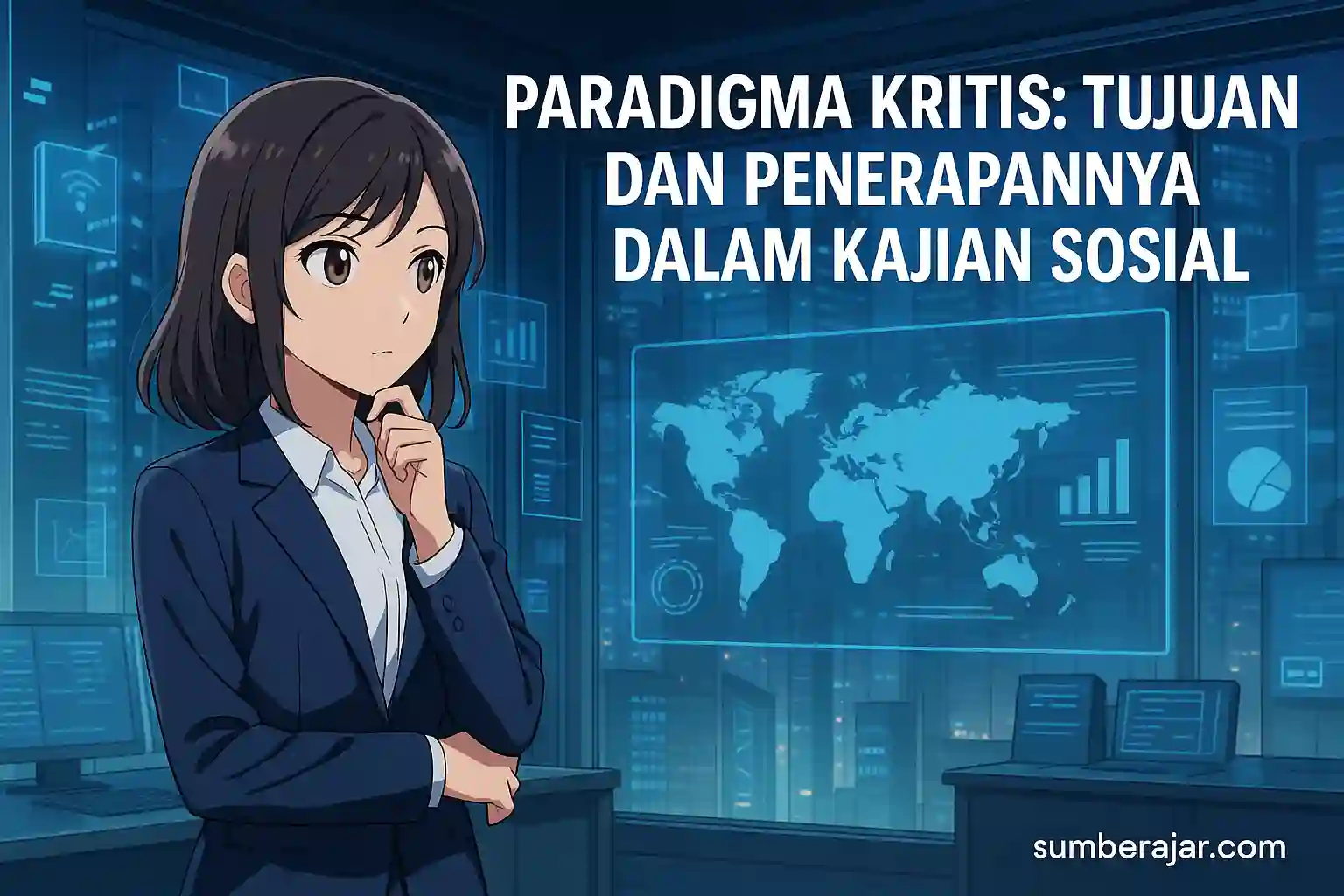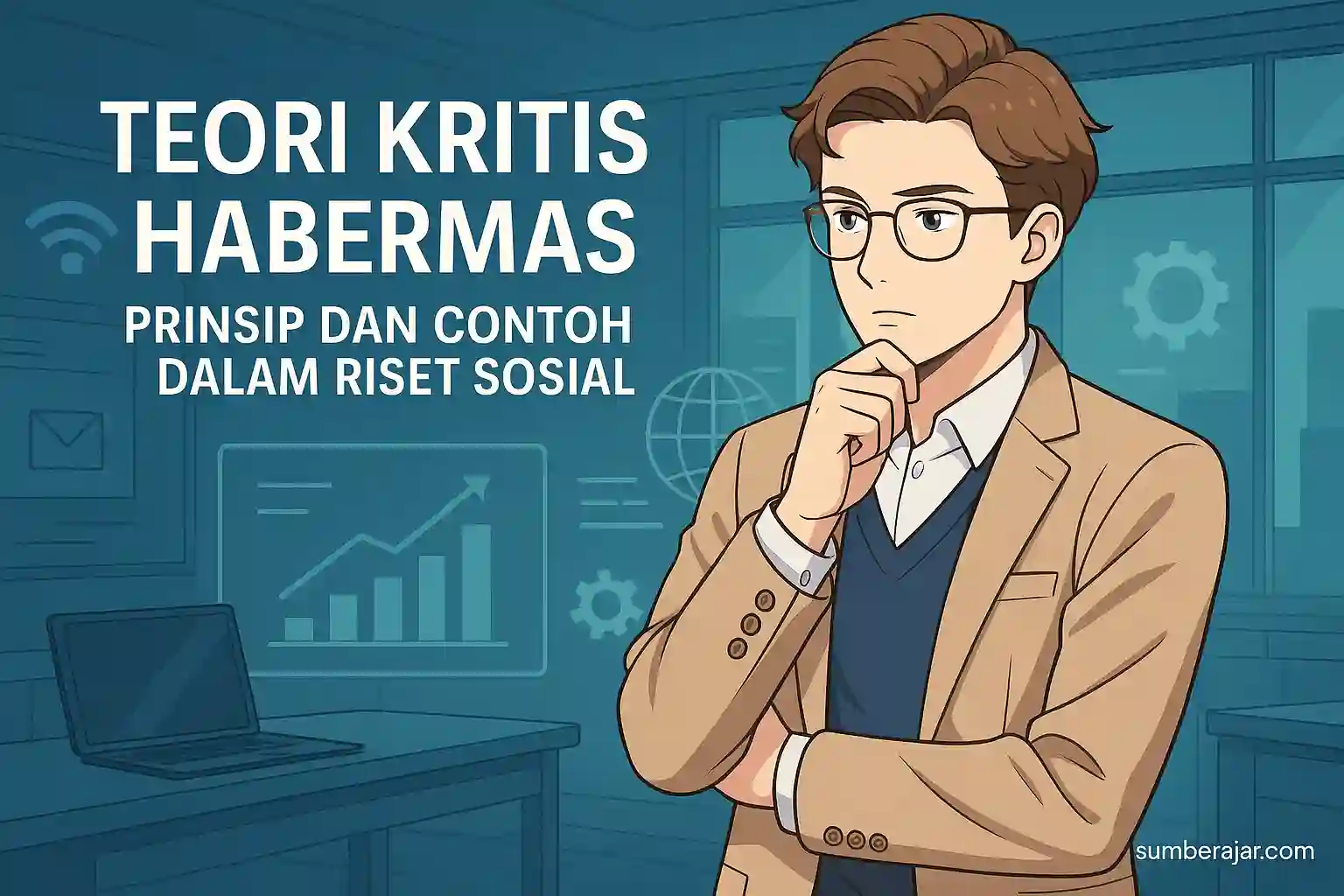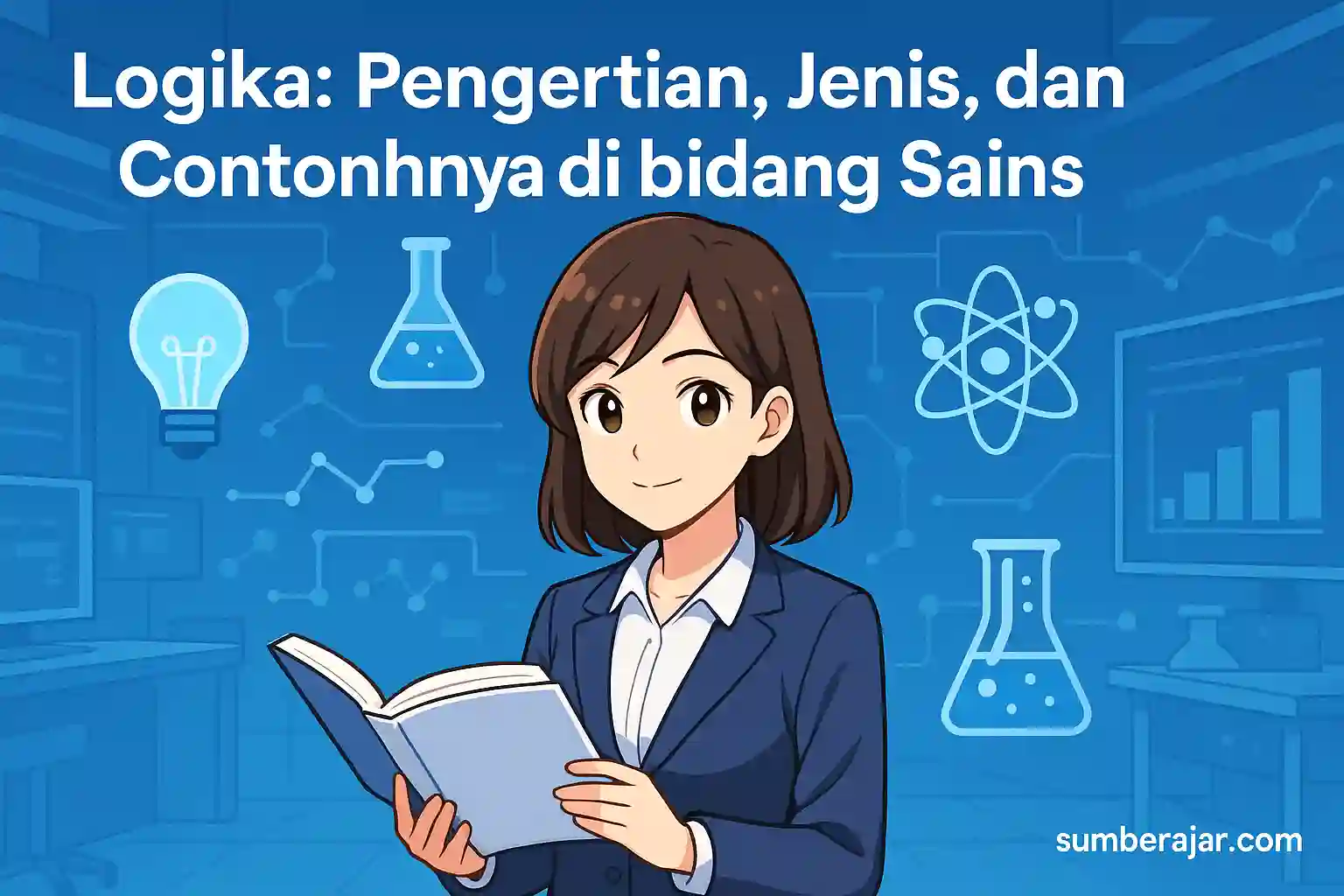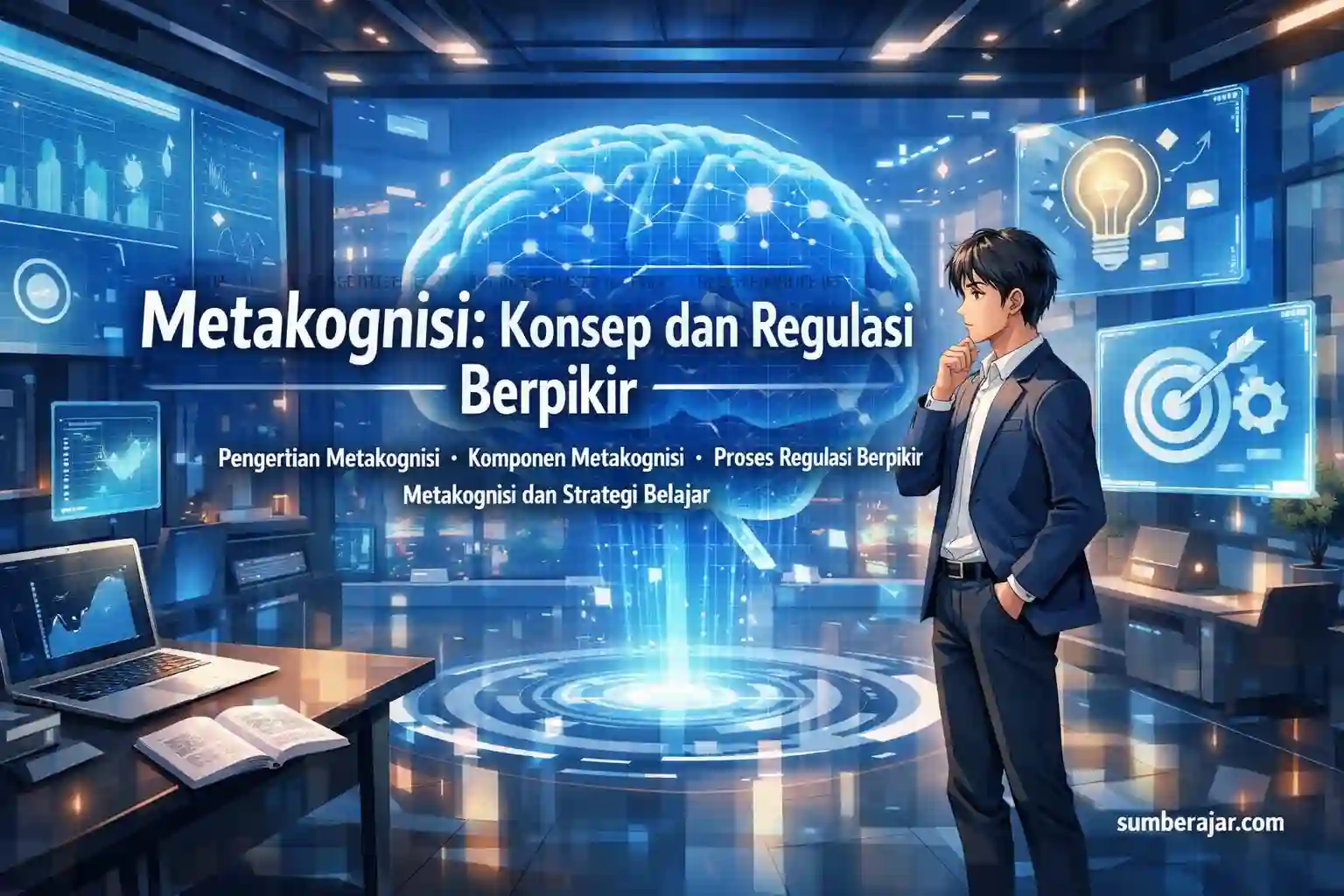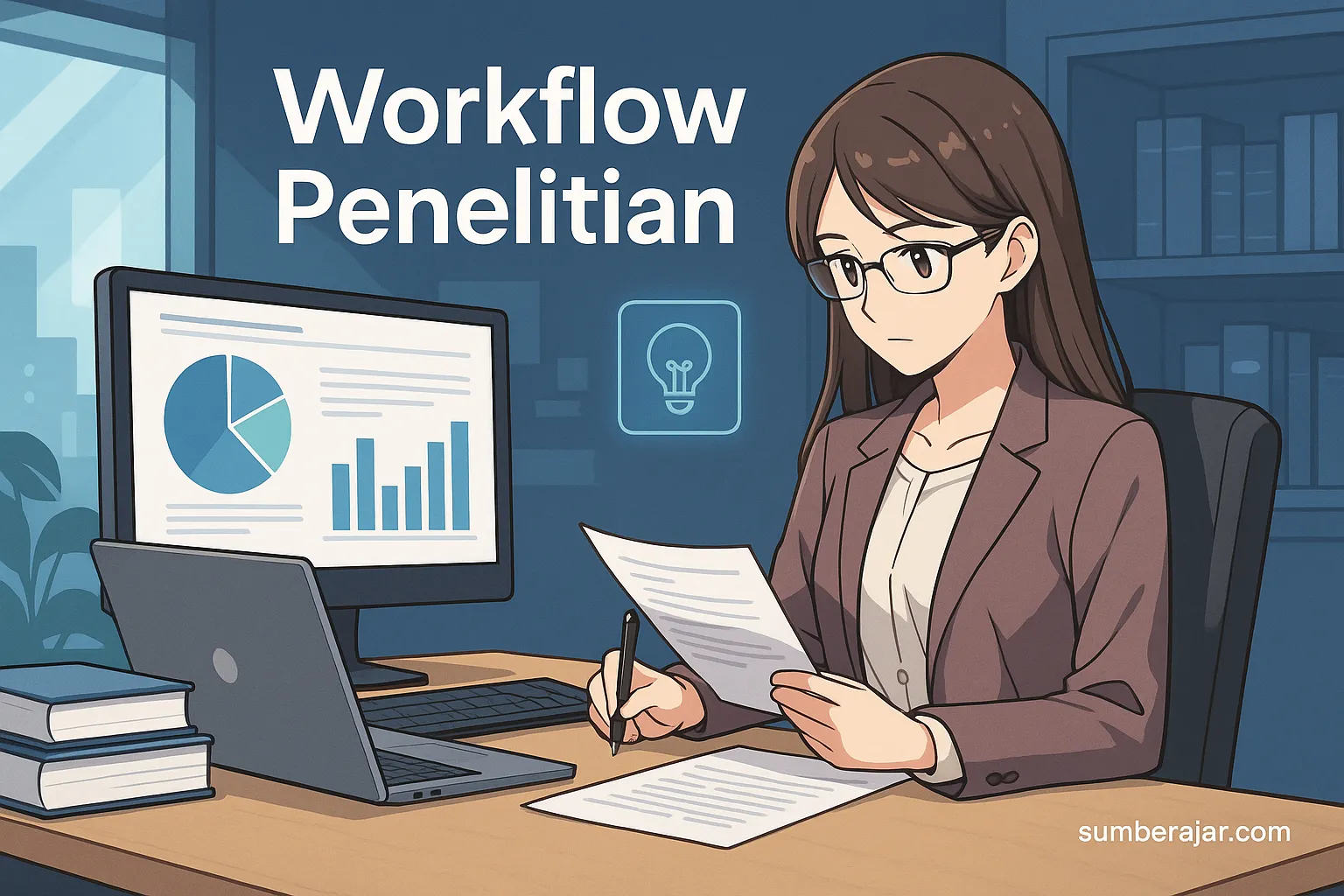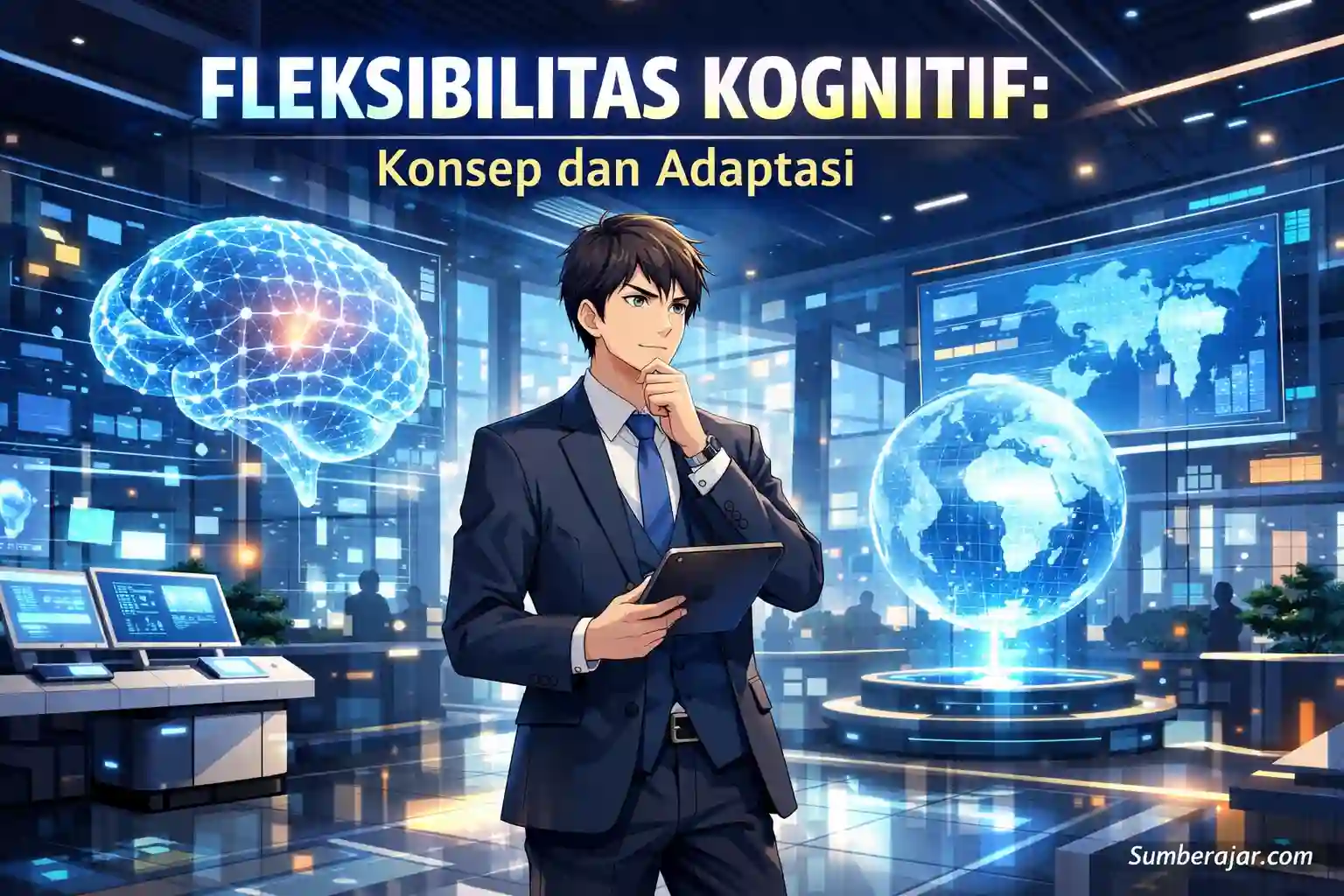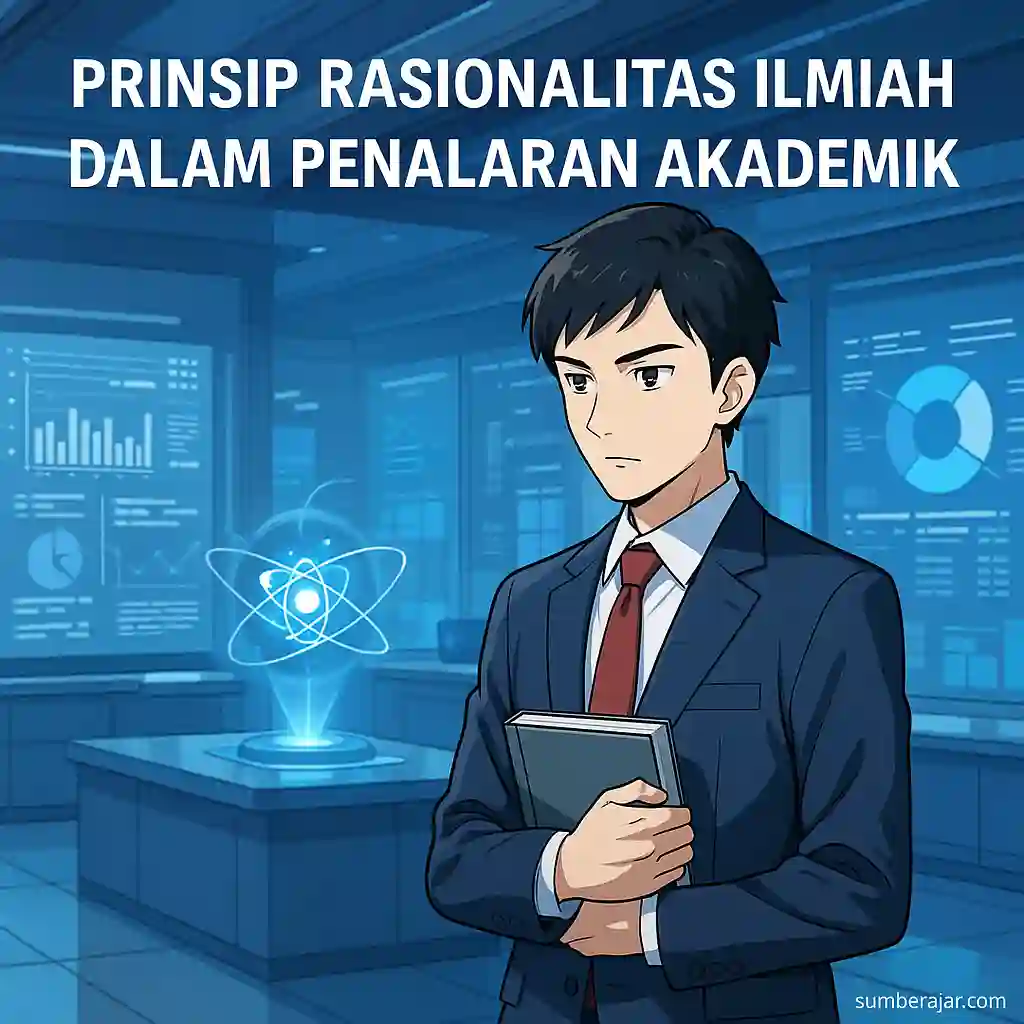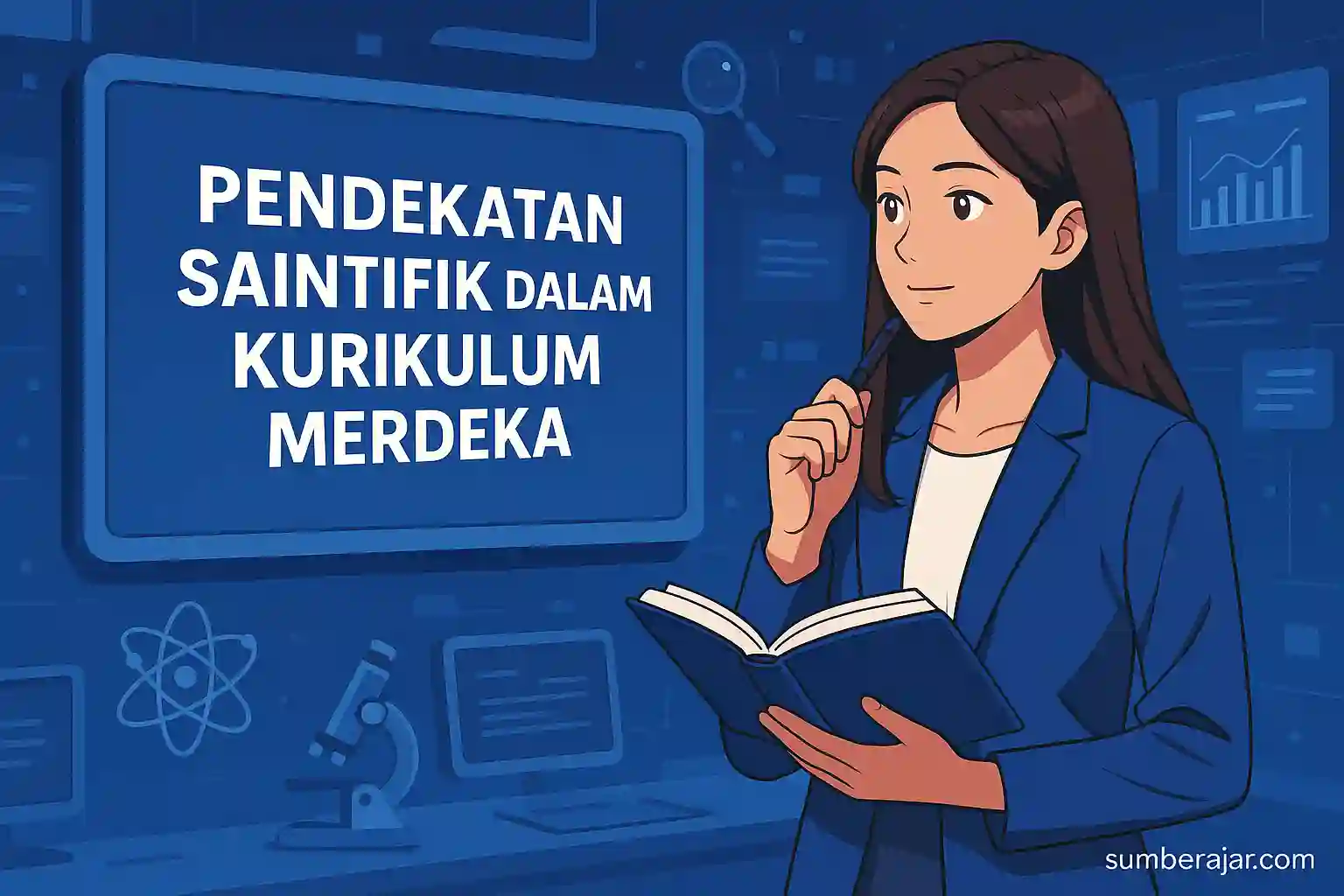Berpikir Kritis: Pengertian, Tahapan, dan Contohnya
Pendahuluan
Di era informasi yang sangat cepat dan kompleks ini, kemampuan seseorang untuk berpikir secara kritis menjadi semakin penting. Dengan hadirnya beragam sumber informasi mulai dari media sosial, berita daring, iklan, hingga komunikasi antar-pribadi tidak cukup hanya menerima secara pasif. Individu dituntut untuk menganalisis, mengevaluasi, serta mampu membuat keputusan atau kesimpulan yang berdasar dan logis. Dalam ranah pendidikan, dunia kerja, hingga pengambilan keputusan ke-hidupan sehari-hari, keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi kunci abad ke-21. Penelitian di konteks Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan melalui strategi pembelajaran yang tepat. [Lihat sumber Disini]
Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai pengertian berpikir kritis baik secara umum, menurut KBBI, maupun menurut para ahli kemudian membahas tahapan (proses) berpikir kritis, dan diakhiri dengan contoh-aplikasi supaya gambarnya makin konkret.
Definisi Berpikir Kritis
Definisi Berpikir Kritis Secara Umum
Secara umum, berpikir kritis (critical thinking) dapat dipahami sebagai proses mental di mana seseorang secara aktif, teliti, dan rasional menganalisis informasi atau masalah, mengevaluasi argumen atau bukti, kemudian menarik kesimpulan atau membuat keputusan yang relevan. Sebagai ilustrasi, sebuah artikel menyebutkan bahwa “berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk kritis dan objektif dalam mempertimbangkan informasi, argumen, dan bukti yang diberikan”. [Lihat sumber Disini]
Dalam konteks pendidikan, kemampuan berpikir kritis berarti siswa tidak hanya menghafal fakta, namun mampu menghubungkan, mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, dan memilih solusi yang paling tepat. Sebagai contoh penelitian di Indonesia: “kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari salah satu elemen projek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis. Pelajar yang berpikir kritis mampu secara objektif memproses informasi, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya.” [Lihat sumber Disini]
Dengan demikian, secara umum berpikir kritis adalah “cara berpikir dengan baik dan merenungkan atau mengkaji proses berpikir orang lain” (untuk memperluas perspektif). [Lihat sumber Disini]
Definisi Berpikir Kritis dalam KBBI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kata kritis memiliki makna: “bersifat tidak lekas percaya; bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; tajam dalam penganalisisan.” [Lihat sumber Disini]
Sedangkan “berpikir” diartikan sebagai menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. [Lihat sumber Disini]
Jika digabungkan – maka secara KBBI berpikir kritis bisa diartikan sebagai upaya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dengan pendekatan yang tajam, tidak langsung percaya, dan menganalisis secara seksama.
Contoh: seseorang menerima berita viral, kemudian tidak langsung membagikannya, melainkan mengecek sumber, mempertanyakan fakta-dasar, menguji kemungkinan bias sebelum memilih sikap.
Definisi Berpikir Kritis Menurut Para Ahli
Berikut ini beberapa pendapat ahli-ahli tentang berpikir kritis:
- Robert H. Ennis menyatakan bahwa berpikir kritis adalah “proses berpikir yang rasional, reflektif, dan terfokus pada apa yang harus dipercayai atau dilakukan.” [Lihat sumber Disini]
- John Dewey menyebut bahwa berpikir kritis adalah cara seseorang yang aktif, gigih, dan memiliki pertimbangan yang cermat mengenai suatu keyakinan atau bentuk pengetahuan apa pun yang diterima, lalu dilihat dari berbagai sudut alasan yang mendukung dan menyimpulkannya. [Lihat sumber Disini]
- Michael Scriven & Richard Paul (dalam banyak literatur tentang critical thinking) mengartikan berpikir kritis sebagai proses intelektual yang menggunakan aktif dan juga terampil dalam mengonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, serta mengevaluasi isu yang dikumpulkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi untuk membimbing keyakinan dan tindakan. [Lihat sumber Disini]
- Helen (H.) Siegel (2021) dalam penelitian Indonesia disebut bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen-argumen secara kritis, mengambil keputusan berdasarkan bukti dan rasional, serta memecahkan masalah secara efektif dengan cara proses mental yang sistematis dan logis. [Lihat sumber Disini]
- Selain itu, beberapa penelitian di Indonesia menyebut bahwa berpikir kritis adalah “upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang suatu topik atau situasi, serta kesediaan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan atau menyimpulkan.” [Lihat sumber Disini]
Dari berbagai definisi ini, bisa disimpulkan bahwa berpikir kritis melibatkan elemen-sebagai berikut: refleksi, evaluasi, analisis, logika, objektivitas, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan kesadaran akan asumsi atau bias.
Tahapan Berpikir Kritis
Dalam praktiknya, berpikir kritis bukan kegiatan tunggal yang instan, melainkan melalui serangkaian tahapan atau proses. Berikut beberapa kerangka tahapan yang sering diterapkan di literatur pendidikan di Indonesia.
- Tahap Clarification (klarifikasi) Di tahap ini individu berupaya memahami atau merumuskan masalah dengan jelas: menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, mengidentifikasi asumsi dasar. Sebagai contoh penelitian di Indonesia menyebut tahapan clarification sebagai tahap di mana siswa “menyebutkan informasi yang diketahui dalam soal secara tepat dan jelas” sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. [Lihat sumber Disini]
- Tahap Assessment (penilaian atau asesmen) Individu memilah-milah informasi yang relevan, mengevaluasi kredibilitas sumber atau bukti, menanyakan pertanyaan penting yang harus dijawab. Dalam salah satu kajian disebut bahwa “tahap assessment merupakan tahap dimana siswa menemukan pertanyaan yang penting dalam masalah.” [Lihat sumber Disini]
- Tahap Inference (menarik kesimpulan) Berdasarkan informasi dan evaluasi sebelumnya, individu membuat kesimpulan atau inferensi atau deduksi/induksi yang logis. Misalnya: “siswa dapat menemukan langkah untuk menyelesaikan soal dan menarik kesimpulan.” [Lihat sumber Disini]
- Tahap Strategies (strategi dan/atau tindakan) Tahap ini melibatkan kemampuan untuk memilih atau merumuskan alternatif solusi, mengatur strategi dalam menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan berdasarkan kesimpulan. Dari hasil penelitian: “siswa dapat menemukan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah serta menjelaskan langkah penyelesaian yang sudah ia temukan.” [Lihat sumber Disini]
Beberapa literatur lain menambahkan atau memvariasikan tahapan, misalnya menurut Ennis:
- Basic Clarification → The Basic for Decision → Inference → Advanced Clarification → Supposition & Integration. [Lihat sumber Disini]
- Atau dalam pembelajaran matematika ditemukan empat tahapan: pemberian pertanyaan → pembagian kelompok → berpikir bersama → pemaparan jawaban. [Lihat sumber Disini]
Dalam konteks penerapan pembelajaran di Indonesia, tahapan-ini dapat dimaknai sebagai berikut:
a. Identifikasi Masalah: Siswa atau individu menyadari ada suatu persoalan yang perlu dipecahkan. (mirip Clarification)
b. Analisis dan Evaluasi: Individu mengevaluasi informasi, mempertanyakan asumsi, menimbang bukti. (mirip Assessment + Inference)
c. Pemilihan Strategi & Aksi: Setelah menyimpulkan, individu memilih strategi atau tindakan yang relevan dan efektif. (mirip Strategies)
Penting juga dicatat bahwa proses ini tidak selalu linear atau berurutan beberapa penelitian menemukan bahwa siswa tidak selalu menjalani tahapan dengan urutan yang sama atau bisa kembali ke tahap sebelumnya. [Lihat sumber Disini]
Contoh Berpikir Kritis
Untuk memperjelas bagaimana berpikir kritis bekerja dalam kehidupan sehari-hari atau konteks pembelajaran, berikut beberapa contoh:
- Contoh dalam dunia kerja
Seorang manajer menerima laporan penjualan yang menurun. Ia tidak langsung menyalahkan tim, tetapi mengecek data: apakah laporan lengkap? Apakah ada faktor eksternal seperti musim atau pandemi? Apakah asumsi bahwa “penjualan menurun karena tim malas” benar? Ia kemudian mengumpulkan bukti, mempertimbangkan alternatif (mis. produk tidak sesuai pasar, promosi kurang, kondisi ekonomi), lalu memilih strategi (mis. pelatihan tim, revisi promosi, riset pasar) berdasarkan data. Ini menunjukkan tahapan klarifikasi (apa yang terjadi), assessment (cek bukti & asumsi), inference (kesimpulan penyebab), strategies (tindakan yang diambil). - Contoh dalam pendidikan/pembelajaran
Seorang siswa menerima soal yang meminta untuk memecahkan masalah matematika real-life: “Mengapa penjualan produk X di toko menurun padahal promosi sudah dilakukan?” Siswa pertama-tama membaca soal, menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan (klarifikasi). Kemudian ia memilah data yang relevan, membandingkan periode promosi sebelumnya (assessment). Ia kemudian menyimpulkan bahwa promosi dilakukan tetapi target pasar berubah (inference). Terakhir, ia menjelaskan langkah alternatif yang bisa dilakukan: mengubah target, memperbaiki promosi, evaluasi harga (strategies). - Contoh dalam kehidupan sehari-hari
Ketika menerima informasi viral di media sosial bahwa “Produk suplemen Y dapat menyembuhkan penyakit Z”, seseorang yang berpikir kritis akan:
- Clarification: Apa klaimnya? Siapa yang membuatnya? Apakah ada bukti?
- Assessment: Cek fakta, sumber independen, apakah studi ilmiah mendukung, apakah ada konflik kepentingan.
- Inference: Berdasarkan bukti yang ada, kesimpulan: Tidak cukup bukti, mungkin klaim berlebihan.
- Strategies: Memutuskan untuk tidak membeli produk berdasarkan klaim tersebut tanpa verifikasi, memberitahu orang lain untuk berhati-hati, atau mencari alternatif yang terbukti.
- Contoh di kelas sekolah
Guru memberikan proyek: “Analisis mengapa kebiasaan membaca siswa menurun di zaman digital.” Siswa akan:
- Clarification: Rumuskan masalah – kebiasaan membaca menurun, apa indikatornya? Mengapa penting?
- Assessment: Kumpulkan data – survei siswa, waktu layar gadget, akses buku, lingkungan; mengevaluasi apakah benar faktor gadget atau mungkin faktor lain seperti kurangnya minat atau akses.
- Inference: Berdasarkan data, siswa menyimpulkan bahwa penyebab utama bukan gadget semata tetapi kurangnya ruang bacaan dan dukungan orang tua.
- Strategies: Siswa membuat rekomendasi – mengadakan klub baca, menyediakan e-book gratis, mengatur jadwal bebas gadget, kampanye membaca.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa berpikir kritis bukan hanya “berpendapat” atau “mengkritik” tanpa dasar, tetapi melibatkan proses yang sistematis dan beralasan untuk mencapai keputusan atau pemahaman yang lebih baik.
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan penting yang melibatkan analisis, evaluasi, refleksi, dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan logika. Secara umum, berpikir kritis adalah proses aktif dan rasional dalam menghadapi informasi atau masalah. Menurut KBBI, berpikir kritis berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dengan sifat tidak mudah percaya serta tajam dalam analisis. Para ahli menambahkan bahwa berpikir kritis mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengonseptualisasi, dan mengambil tindakan atau keputusan yang tepat. Tahapan seperti klarifikasi, assessment, inference, dan strategi memberikan kerangka agar berpikir kritis lebih terstruktur. Contoh-nyata dari dunia kerja, sekolah, dan kehidupan sehari-hari menunjukkan bagaimana berpikir kritis diterapkan. Dengan mengembangkan kemampuan ini, individu akan lebih siap menghadapi tantangan zaman, membuat keputusan yang lebih matang, dan berkontribusi secara lebih bermakna dalam lingkungan sekitarnya.