Hegemoni: Pengertian, Karakteristik, dan Contoh dalam Kajian Sosial beserta link Sumber [PDF]
Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali tidak sadar bahwa cara kita berpikir, bertindak, bahkan menentukan pilihan, dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja secara halus di balik layar. Fenomena ini dalam kajian ilmu sosial disebut sebagai hegemoni. Konsep ini menjelaskan bagaimana kelompok dominan dapat mempertahankan kekuasaannya bukan hanya lewat paksaan atau kekerasan, melainkan dengan membentuk konsensus sosial dan menjadikan nilai-nilai mereka sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak terbantahkan. Hegemoni menjadi penting untuk dipahami karena ia menyelinap ke dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari media, pendidikan, budaya populer, hingga kebijakan negara.
Kajian mengenai hegemoni berkembang pesat setelah diperkenalkan oleh Antonio Gramsci pada awal abad ke-20, dan hingga kini tetap relevan untuk membaca dinamika sosial-politik. Di Indonesia, konsep ini banyak digunakan untuk meneliti wacana media, iklan, karya sastra, bahkan praktik kebijakan daerah. Dengan memahami hegemoni, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan bekerja secara tidak kasat mata, serta mengenali bentuk-bentuk dominasi yang tersamar sebagai “kebenaran umum”. Kesadaran kritis inilah yang menjadi langkah awal untuk membuka ruang bagi resistensi dan terciptanya wacana alternatif yang lebih adil.
Definisi Hegemoni
Definisi Hegemoni Secara Umum
Secara umum, hegemoni ditafsirkan sebagai bentuk dominasi atau pengaruh yang dijalankan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Tapi penting dicatat: dominasi ini tidak selalu lewat kekerasan kasar atau paksaan eksplisit melainkan bisa melalui persetujuan, legitimasi, dan penyebaran wacana dominan yang tampak “normal” atau “lumrah”.
Artinya, kelompok yang berkuasa atau mendominasi berusaha agar nilai-nilai, ide, norma, dan cara berpikir mereka diterima sebagai sesuatu yang alami oleh masyarakat. Dalam proses ini, orang-orang yang “dikuasai” kadang tidak merasa bahwa mereka sedang dikuasai karena mereka sudah menginternalisasi pandangan dunia dari kelompok dominan tersebut.
Beberapa media populer bahkan menyebutnya sebagai “dominasi kekuasaan berdasarkan persetujuan” yaitu kekuasaan yang tidak selalu mendorong paksa, tetapi bekerja lewat cara yang halus agar tampak wajar dan diterima publik. (contoh: framing media, wacana budaya populer)
Dalam konteks sosial, hegemoni bisa terjadi di banyak level: antar kelas sosial, antar kelompok etnis, antar gender, antar kelompok budaya, dan sebagainya. Intinya, bukan hanya tentang siapa yang punya senjata atau uang, tetapi siapa yang bisa mengendalikan makna, persepsi, dan kesepakatan umum.
Definisi Hegemoni dalam KBBI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hegemoni memiliki arti:
“pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya oleh suatu negara atas negara lain atau negara bagiannya.”
Definisi KBBI ini lebih menekankan aspek negara dan hubungan antarnegara atau bagian negara (dominan negara terhadap negara lain atau terhadap wilayah dalam satu negara).
Namun dalam kajian sosial kontemporer (sosiologi, politik budaya, kajian media) kita perlu memperluas makna tersebut agar mencakup relasi kekuasaan dalam masyarakat sehari-hari bukan hanya antarnegara, tetapi antar kelompok sosial, antar institusi, dan antar lapisan budaya. Artinya, hegemoni tidak hanya berlaku di panggung besar negara, tetapi juga di panggung kecil (lingkungan keluarga, sekolah, media, organisasi).
Definisi Hegemoni Menurut Para Ahli / Teori
Antonio Gramsci: Pemikiran Sentral
Antonio Gramsci (lahir 1891 – wafat 1937) adalah tokoh penting dalam teori hegemoni. Pemikirannya memberi kerangka bagaimana kekuasaan bisa bekerja lewat budaya, ideologi, dan lembaga-lembaga sosial, bukan semata lewat kekuatan fisik. Beberapa poin utama:
- Hegemoni sebagai kepemimpinan ideologis + konsensus
Gramsci menolak pandangan bahwa kekuasaan hanya bergantung pada kekerasan dan dominasi langsung. Baginya, kekuasaan yang efektif harus dibangun lewat kepemimpinan intelektual dan moral, serta melalui konsensus bahwa mayoritas masyarakat “setuju” atau menerima gagasan dominan. Ini penting agar dominasi tak selalu tampak kasar atau tak wajar. (ini tercermin di banyak literatur Gramsci) - Internalisasi nilai dan “common sense”
Agar dominasi ideologis berhasil, nilai-nilai dominan harus dijadikan “common sense” yaitu sesuatu yang dianggap wajar, alamiah, atau tak perlu dipertanyakan. Dengan demikian, kritik terhadap sistem dominan menjadi sulit karena nilai itu sendiri sudah diterima luas. - Masyarakat Politik vs Masyarakat Sipil
Gramsci membedakan antara dua ruang kekuasaan:- Masyarakat politik (political society): institusi formal negara hukum, militer, polisi, pemerintahan
- Masyarakat sipil (civil society): ruang institusi non-negara sekolah, media, lembaga budaya, asosiasi, gereja/masjid, serikat pekerja
Menurutnya, hegemoni lebih banyak beroperasi melalui masyarakat sipil, karena kekuasaan lewat paksaan langsung tidak selalu efektif atau diterima.
- Kaum Intelektual Organik & Tradisional
Gramsci membagi kaum intelektual menjadi:- Intelektual tradisional: mereka yang sudah lama memiliki otoritas intelektual (misalnya guru besar, ulama, intelektual akademik)
- Intelektual organik: mereka yang muncul dari kelompok masyarakat dan langsung mewakili kepentingan kelas tertentu tugas mereka adalah menyebarkan ide dan mendukung hegemoni kelas dominan
- Konflik & kontra-hegemoni
Hegemoni tidak pernah bersifat absolut dan stabil tanpa tantangan. Kelas subordinat atau kelompok minoritas bisa muncul sebagai agen kontra-hegemoni mereka menyodorkan narasi alternatif, budaya tandingan, kritik terhadap sistem dominan. Gramsci menyebut ini sebagai “perang posisi” (war of position) untuk membangun kekuatan ideologis sebelum konfrontasi terbuka (“war of movement”). - Proses historis & dinamis
Hegemoni bukan sesuatu yang statis atau sekali jadi; melainkan proses yang terjadi dalam waktu, melalui pertarungan ideologis, kompromi, penyesuaian, dan pergeseran sosial. Hegemoni lama bisa tergeser kalau kelompok dominan gagal mempertahankan konsensus atau nilai-nilai mereka usang.
Interpretasi & Kritik Lanjutan (Termasuk dari Peneliti Indonesia)
Para peneliti dan ahli di Indonesia maupun global telah mengembangkan, mengkritik, atau mengaplikasikan teori Gramsci dalam konteks lokal. Berikut beberapa pandangan dan temuan menarik:
- Adaptasi konsep “blok historis” dan kepemimpinan moral-intelektual
Dalam penelitian Arasta (2021), konsep hegemoni Gramsci dikaitkan dengan bagaimana institusi media dan pemerintah menjalankan dominasi ideologis melalui wacana berita. Ia menyebut bahwa Gramsci menolak determinisme kelas yang terlalu kaku; alih-alih, hegemoni bisa terbentuk lewat blok sosial yang lebih luas dengan kepemimpinan moral dan intelektual. [Lihat sumber Disini] - Aplikasi dalam kebijakan publik / otonomi daerah
Dalam “Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta” (2021), ABM Kamim meneliti bagaimana alokasi dana khusus (keistimewaan) dipakai sebagai instrumen kekuasaan yang mempertahankan relasi hegemoni ekonomi dan politik antara pusat dan daerah. [Lihat sumber Disini] - Hegemoni dalam kajian sastra & budaya
- Penelitian “Potret Hegemoni Negara dalam Kumpulan Cerpen Corat-Coret di Toilet” (2024) oleh Maratussholihah dkk. menganalisis bagaimana citra negara, kepercayaan populer, dan wacana gender muncul sebagai bentuk hegemoni dalam karya sastra, lengkap dengan unsur masyarakat sipil vs masyarakat politik dan peran intelektual. [Lihat sumber Disini]
- “Representasi Hegemoni Gramsci dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar” (2025) menyoroti bagaimana novel itu menyajikan wacana dominan, simbol-simbol ideologis, dan perlawanan di dalam narasi. [Lihat sumber Disini]
- Dalam “Hegemoni Ideologi Gramsci dalam Novel Negeri Para Bedebah” (2025), peneliti mencoba mendeskripsikan bentuk dan makna hegemoni ideologis di novel tersebut. [Lihat sumber Disini]
- Kritik & batasan konsep
- Beberapa kritik menyebut bahwa teori hegemoni terlalu fokus pada ideologi dan wacana, sehingga kadang mengabaikan struktur materi (ekonomi, infrastruktur) atau faktor teknis kekuasaan.
- Ada yang mengatakan bahwa tidak semua individu menerima “common sense” tanpa resistensi karena ada agen sosial yang kritis dan kreatif.
- Dalam konteks globalisasi dan media digital, hegemoni bisa lebih kompleks di mana wacana global (misalnya budaya Korea / Korean Wave) mempengaruhi konstruksi sosial lokal ini menantang bagaimana hegemoni lokal dipertahankan atau diubah. Contohnya: “Hyperreality dalam Globalisasi Budaya: Hegemoni Korean Wave terhadap Konstruksi Sosial Indonesia (2021-2022)” yang mengeksplorasi bagaimana budaya pop Korea (K-pop, drama Korea) menjadi medium hegemoni budaya global di Indonesia. [Lihat sumber Disini]
- Konsep hegemoni dalam antropologi & budaya
Artikel “Hegemoni Antonio Gramsci: Sejarah dan Perkembangannya dalam Ranah Antropologi” (2024) mencoba memposisikan pemikiran Gramsci dalam diskursus antropologi, menjelaskan bagaimana ide-grup dominan bisa mengendalikan praktik budaya lewat wacana dan simbol budaya. [Lihat sumber Disini]
Karakteristik Hegemoni
Berdasarkan teori Gramsci dan penelitian-penelitian dalam konteks sosial, budaya, dan politik (termasuk di Indonesia), berikut karakteristik utama hegemoni beserta penjelasan mendalaminya dan contoh dari penelitian:
1. Dominasi melalui Konsensus (Bukan Semata Paksaan)
Salah satu karakteristik paling khas dari hegemoni adalah bahwa dominasi kelas atau kelompok berkuasa dilakukan bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui konsensus sosial, yakni membentuk persetujuan luas terhadap ide, norma, dan struktur kekuasaan mereka.
- Gramsci menekankan bahwa kekuasaan yang tahan lama adalah kekuasaan yang “disetujui” atau diterima masyarakat, bukan yang selalu memaksa lewat kekerasan. [Lihat sumber Disini]
- Dengan konsensus, sebagian besar masyarakat akan “menerima” atau “menganggap wajar” aturan-aturan dominan, tanpa merasa bahwa mereka sedang dijajah secara kultural atau ideologis.
- Konsensus ini dibangun lewat pendidikan, wacana, media, budaya populer bukan semata intimidasi.
Contoh penelitian lokal: Dalam penelitian “Hegemoni Sosial, Budaya, dan Kekuasaan dalam Wacana Sastra Buku Teks Bahasa Indonesia SMA”, Mafrukhi dkk menunjukkan bagaimana buku teks pelajaran dimanfaatkan untuk menanamkan wacana dominan agar masyarakat tidak mempertanyakan kekuasaan (yakni konsensus yang terbentuk lewat materi pelajaran). [Lihat sumber Disini]
2. Penanaman Ideologi & Wacana Dominan
Hegemoni juga ditandai dengan usaha sistematis untuk menanamkan ideologi dan wacana yang menguntungkan kelompok dominan ke dalam semua aspek kehidupan sosial agar orang awam “menelan” ide itu sebagai sesuatu yang benar, wajar, atau tak dapat dipertanyakan.
- Ideologi dominan bisa berupa gagasan tentang “kemajuan”, “modernitas”, “nilai universal”, “cara hidup ideal”, maupun penafsiran sejarah yang menguntungkan pihak dominan.
- Media massa, pendidikan, institusi budaya, agama, hiburan, hingga simbol-simbol keseharian bisa digunakan untuk menyebarkan wacana tersebut.
Contoh: Dalam penelitian “Representasi Hegemoni Gramsci dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar” (2025), ditemukan bentuk-bentuk “hegemoni pikiran” dan “hegemoni media massa” dalam narasi novel yang mendukung nilai kapitalistik, konservatif, dan alamiahkan struktur sosial dominan. [Lihat sumber Disini]
3. Institusi sebagai Wahana Penyebaran
Institusi formal dan informal seperti sekolah, universitas, media, gereja/masjid, organisasi budaya, lembaga negara menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hegemoni.
- Institusi pendidikan (kurikulum, materi, guru) bisa menjadi medium untuk menyebarkan nilai-nilai dominan kepada generasi muda sejak dini.
- Media massa (televisi, surat kabar, media daring) memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan cara pandang masyarakat tentang apa yang normal atau tidak.
- Lembaga budaya dan agama bisa menyebarkan nilai moral, kepercayaan, norma tradisi yang konsisten dengan kepentingan kelompok dominan.
- Dalam ranah negara, regulasi, kebijakan, hukum, dan lembaga negara (misalnya lembaga penegak hukum) turut mempertahankan struktur kekuasaan melalui legitimasi formal.
Misalnya, dalam studi “Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di DIY” (2021), Kamim menunjukkan bagaimana lembaga negara (pengelolaan dana keistimewaan) menjadi alat hegemoni lokal kebijakan negara dan lembaga birokrasi mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami keistimewaan sebagai sesuatu yang “wajib disetujui”. [Lihat sumber Disini]
4. Sikap Pasif atau Internalisasi (Inkorporasi Ide Dominan)
Sebagian kelompok subordinat bisa menerapkan sendiri nilai-nilai ideologi dominan ke dalam kesadaran mereka tanpa disadari ini disebut internalisasi. Dengan internalisasi, dominasi menjadi hal yang “alami” dan hampir tak dipertanyakan lagi.
- Individu mungkin merasa bahwa cara berpikir, selera, gaya hidup, bahkan cita-cita yang mereka miliki adalah “pilihan bebas”, padahal sebagian besar telah dibentuk oleh wacana dominan.
- Karena internalisasi, kritik terhadap struktur kekuasaan menjadi sulit sebab sebagian orang sudah menganggap bahwa standar dominan itu adalah “benar”.
Penelitian “Praktik Hegemoni Mahasiswa Senior Terhadap Junior” (202X) (dokumen lokal) menyinggung bagaimana norma dan struktur kekuasaan kampus bisa diinternalisasi generasi junior karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang menerima struktur senioritas tertentu sebagai sesuatu yang lumrah. [Lihat sumber Disini]
5. Kontestasi & Resistensi (Kontra-Hegemoni)
Hegemoni tidak pernah absolut atau monolitik selalu ada ruang bagi penolakan, kritik, dan wacana tandingan. Ini disebut kontra-hegemoni.
- Kelompok subordinat, intelektual kritis, gerakan sosial, subkultur, media alternatif bisa menawarkan narasi tandingan yang menantang dominasi wacana utama.
- Pertarungan ideologis (war of position) sering terjadi dalam ranah budaya, pendidikan, dan media, sebelum pertarungan terbuka (war of movement).
- Resistensi bisa bersifat halus (misalnya kritik lewat seni, literatur, media alternatif) atau nyata (protes, aktivisme, gerakan sosial).
Artikel “Hegemoni dan Perlawanan: Dinamika Kekuasaan” (2023) menyebut bahwa teori hegemoni menunjuk pada pengaruh kepemimpinan moral maupun intelektual yang membentuk sikap yang dipimpin, tapi bahwa dominasi tersebut selalu berpotensi ditolak atau digugat. [Lihat sumber Disini]
6. Dinamis & Berubah Sesuai Konteks Temporal & Sosial
Hegemoni bukanlah kondisi tetap; ia berubah sesuai perkembangan zaman, teknologi, konflik sosial, tekanan eksternal.
- Apa yang dianggap “wajar” pada satu masa bisa dipertanyakan di masa berikutnya.
- Kegagalan kelompok dominan dalam merespons dinamika sosial (misalnya perubahan ekonomi, teknologi, aspirasi baru) bisa melemahkan hegemoni mereka.
- Pergeseran identitas, generasi baru, globalisasi, media digital menjadi tantangan baru bagi hegemoni lama.
Contoh: Dalam kajian budaya, film Humba Dreams (2025) dianalisis sebagai manifestasi dinamika hegemoni budaya lokal yang dipengaruhi oleh globalisasi di mana simbol budaya lokal berhadapan dengan wacana budaya dominan global. [Lihat sumber Disini]
7. Penyembunyian Kekerasan atau Dominasi Struktural
Meskipun hegemoni sering berwajah “lunak”, dominasi struktural atau aspek kekerasan tetap ada, namun disamarkan agar tidak terlihat sebagai opresi langsung.
- Kekerasan atau paksaan bisa tersembunyi di balik norma, regulasi, hukum, “kebijakan wajar”, atau penafsiran sejarah.
- Struktur ekonomi yang timpang (akses modal, kepemilikan, infrastruktur) juga bisa menjadi aspek dominasi yang tersembunyi.
- Dasar ketidaksetaraan struktural seperti kelas ekonomi, etnis, gender tetap menjadi fondasi di balik wacana “keadilan universal”.
Dalam penelitian representasi sastra “Representasi Hegemoni dalam Novel Gadis Kretek” (2024), peneliti menemukan bahwa dominasi kekuasaan terhadap perusahaan kretek dan keluarga digambarkan lewat intervensi politik dan regulasi (struktur ekonomi dan politik), bukan hanya wacana semata. [Lihat sumber Disini]
Contoh Hegemoni dalam Kajian Sosial + Analisis
Berikut contoh-contoh konkret hegemoni yang telah diteliti di Indonesia atau dalam konteks serupa, lengkap dengan kutipan jurnal / artikel:
1. Media & Politik Wacana
Studi: Arasta (2021) “Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat Dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia” [Lihat sumber Disini]
- Penelitian ini menyoroti bagaimana media massa dapat membingkai berita, memilih idiom politik, dan menggunakan framing tertentu agar wacana publik sesuai dengan kepentingan kekuasaan. [Lihat sumber Disini]
- Dalam artikel itu disebut bahwa negara / elite mencoba menciptakan “persetujuan” melalui wacana yang disebarkan lewat media agar publik menerima kebijakan atau narasi dominan sebagai sesuatu yang wajar. [Lihat sumber Disini]
- Media massa, dalam kerangka ini, bukan sekadar penyampai berita, tetapi aktor ideologis yang memilih narasi, menentukan apa yang ditonjolkan dan apa yang diabaikan. [Lihat sumber Disini]
Analisis tambahan: Kasus ini menunjukkan hegemoni sebagai dominasi ideologis media sebagai instrumen penyebaran wacana dominan. Publik yang kurang kritis atau tidak memiliki akses ke media alternatif bisa “terbius” framing dominan dan akhirnya menyetujui kebijakan atau interpretasi yang dikehendaki kekuasaan.
2. Iklan & Representasi Gender
Studi: Indarto, Apriliansyah & Waluyo (2021) “Representasi Hegemoni Laki-laki Terhadap Perempuan dalam Iklan Teh Sari Wangi Tahun 2021” [Lihat sumber Disini]
- Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika untuk melihat adegan-adegan iklan, simbol, dialog, dan struktur naratif yang menampilkan bagaimana laki-laki memiliki kuasa dominan dalam iklan tersebut, sementara perempuan cenderung mengikuti atau pasif. [Lihat sumber Disini]
- Hasil analisis menunjukkan bahwa laki-laki diposisikan sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan digambarkan sebagai pihak yang lebih pasif atau “mengikuti”. [Lihat sumber Disini]
- Kesimpulannya: iklan itu memperkuat norma patriarki bahwa laki-laki “sempat berfungsi sebagai pemimpin keluarga / pengonsep keputusan”, sedangkan perempuan hanya bagian dari tatanan domestik. [Lihat sumber Disini]
Contoh lain:
- Penelitian “Representasi Bias Gender pada Iklan Susu Ultramilk Pure Passion” juga menunjukkan elemen hegemoni gender, di mana iklan menampilkan ayah / laki-laki sebagai figur aktif dalam produksi dan pengetahuan produk, sedangkan ibu dan anak perempuan hanya sebagai penerima / konsumen. [Lihat sumber Disini]
- Dalam iklan tersebut, anak perempuan dan ibu digambarkan kurang memahami proses produksi susu dibandingkan anak laki-laki / ayah. [Lihat sumber Disini]
Analisis tambahan: Iklan sering dianggap “ringan” dan hiburan, tapi sangat efektif menjadi medium hegemoni karena mampu menyusup ke pikiran masyarakat lewat simbol, narasi visual, dan dialog sehari-hari. Ketika publik melihat berulang-ulang bahwa “laki-laki memimpin, perempuan mengikuti”, itu mengokohkan norma dominan.
3. Dominasi Pemilik Media & Wacana Regulasi
Studi: Mokhammad Naigam Mahriva & Eka Wenats Wuryanata (2021) “Dominasi Kekuasaan Pemilik Media dalam Wacana Pembaruan UU Penyiaran” [Lihat sumber Disini]
- Penelitian ini mengulas bagaimana pemilik media (stasiun TV besar, korporasi media) berperan dalam mendominasi wacana seputar perubahan regulasi penyiaran (UU Penyiaran tahun 2002 dan pembaruan ke media digital / OTT). [Lihat sumber Disini]
- Mahriva et al. menunjukkan bahwa media yang menguasai platform penyiaran utama memiliki kapasitas untuk memilih wacana yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri memfilter, menonjolkan, membingkai argumen, atau menyembunyikan kritik. [Lihat sumber Disini]
- Bentuk dominasi ini bukan lewat kekerasan fisik, tetapi lewat kontrol terhadap saluran komunikasi dan wacana publik sejatinya hegemoni ideologis di ranah media regulasi.
Analisis tambahan: Kasus ini menunjukkan bahwa hegemoni tidak hanya soal konten media (apa yang ditayangkan), tetapi juga soal siapa yang punya kendali atas media itu sendiri. Jika pemilik media punya kepentingan, mereka bisa menggunakan media itu sebagai alat hegemoni terhadap publik.
4. Kontra-Hegemoni & Aktivisme Digital
Studi: Muhammad Alif Kanzul Arfan (2025) “Strategi Kontra-Hegemoni Dalam Wacana Politik di Akun Instagram @BangsaMahardika” [Lihat sumber Disini]
- Penelitian ini menganalisis bagaimana akun Instagram @BangsaMahardika berupaya membongkar narasi resmi negara / kekuasaan yang dianggap menyesatkan dan membungkus realitas. [Lihat sumber Disini]
- Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (Norman Fairclough) terhadap postingan gambar, teks, hashtag, dan komentar melihat praktik teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. [Lihat sumber Disini]
- Hasilnya: akun tersebut menggunakan strategi strategi kontra-hegemonik untuk menyajikan narasi tandingan, kritik terhadap kebijakan publik, ekspos realitas yang disembunyikan, dan mengajak publik berpikir kritis. [Lihat sumber Disini]
Analisis tambahan: ini contoh bahwa hegemoni tidak pasif: selalu ada ruang untuk melawan melalui media alternatif, digital, media sosial. Kontra-hegemonik menggunakan alat wacana juga mengusung ide yang berbeda, membingkai ulang realitas, menyodorkan kritik terhadap dominasi.
Kesimpulan
Hegemoni merupakan salah satu konsep penting dalam kajian sosial dan politik yang menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak hanya bertahan lewat paksaan langsung, tetapi juga melalui dominasi ideologis, legitimasi, dan penciptaan konsensus. Secara umum, hegemoni dapat dipahami sebagai bentuk dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain melalui proses yang halus, misalnya lewat pendidikan, media, agama, budaya, maupun institusi negara. Definisi KBBI memang menekankan hubungan antarnegara, namun dalam praktik sosial sehari-hari, hegemoni juga terjadi di berbagai ranah kehidupan masyarakat.
Pemikiran Antonio Gramsci memberikan fondasi teoritis untuk memahami bagaimana kelas dominan mempertahankan kekuasaan dengan menjadikan nilai, norma, dan ideologi mereka sebagai sesuatu yang “biasa” atau “wajar” di mata masyarakat luas. Hegemoni menurut Gramsci bukanlah kondisi yang statis, melainkan dinamis, penuh konflik, dan selalu membuka ruang bagi perlawanan atau kontra-hegemoni. Dengan demikian, masyarakat subordinat tidak selamanya pasif, tetapi bisa menciptakan wacana alternatif yang menantang struktur dominan.
Karakteristik utama hegemoni mencakup dominasi melalui konsensus, penanaman ideologi dominan, penggunaan institusi sebagai sarana penyebaran, hingga kemampuan menyembunyikan ketidakadilan struktural di balik wajah normalitas. Namun karena sifatnya yang dinamis, hegemoni selalu rentan dipertanyakan, digugat, dan digoyahkan oleh perubahan zaman, media baru, serta gerakan sosial.
Contoh nyata di Indonesia (2021–2025) menunjukkan bahwa hegemoni hadir dalam berbagai ranah:
- Media massa yang membingkai berita agar sesuai kepentingan elite (Arasta, 2021, jurnal.usahid.ac.id),
- Kebijakan publik seperti dana keistimewaan DIY yang menjadi instrumen politik (Kamim, 2021, [Lihat sumber Disini]),
- Sastra dan budaya yang merepresentasikan hegemoni negara dan kelas dominan dalam cerita fiksi (Maratussholihah dkk, 2024, [Lihat sumber Disini]),
- Iklan dan representasi gender yang memperkuat norma patriarki dalam iklan komersial (Indarto dkk, 2021, [Lihat sumber Disini]),
- Hingga aktivisme digital yang menghadirkan kontra-hegemoni lewat media sosial (Arfan, 2025, [Lihat sumber Disini]).
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hegemoni adalah realitas yang melekat dalam kehidupan sosial kita, sering kali hadir dalam bentuk yang tidak kasat mata. Oleh sebab itu, kesadaran kritis menjadi kunci agar kita mampu mengenali wacana dominan, memahami siapa yang diuntungkan, dan bagaimana cara berpikir kita dibentuk. Dengan kesadaran itu pula, kita bisa ikut serta menciptakan ruang bagi wacana alternatif, resistensi, dan perubahan sosial yang lebih adil.
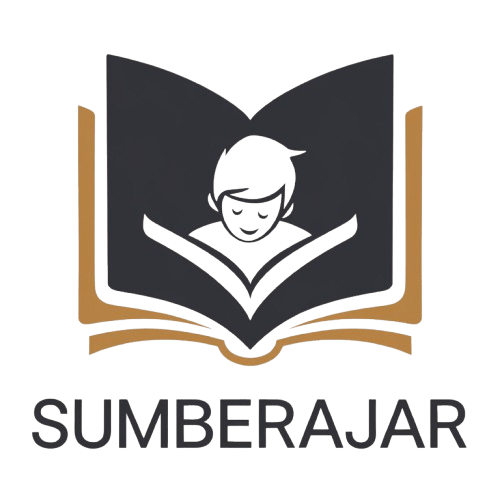
![Hegemoni: Pengertian, Karakteristik, dan Contoh dalam Kajian Sosial beserta link Sumber [PDF] - SumberAjar.com Hegemoni: Pengertian, Karakteristik, dan Contoh dalam Kajian Sosial beserta link Sumber [PDF] - SumberAjar.com](https://sumberajar.com/assest/img/blogs/Hegemoni Sumberajar.com.webp)