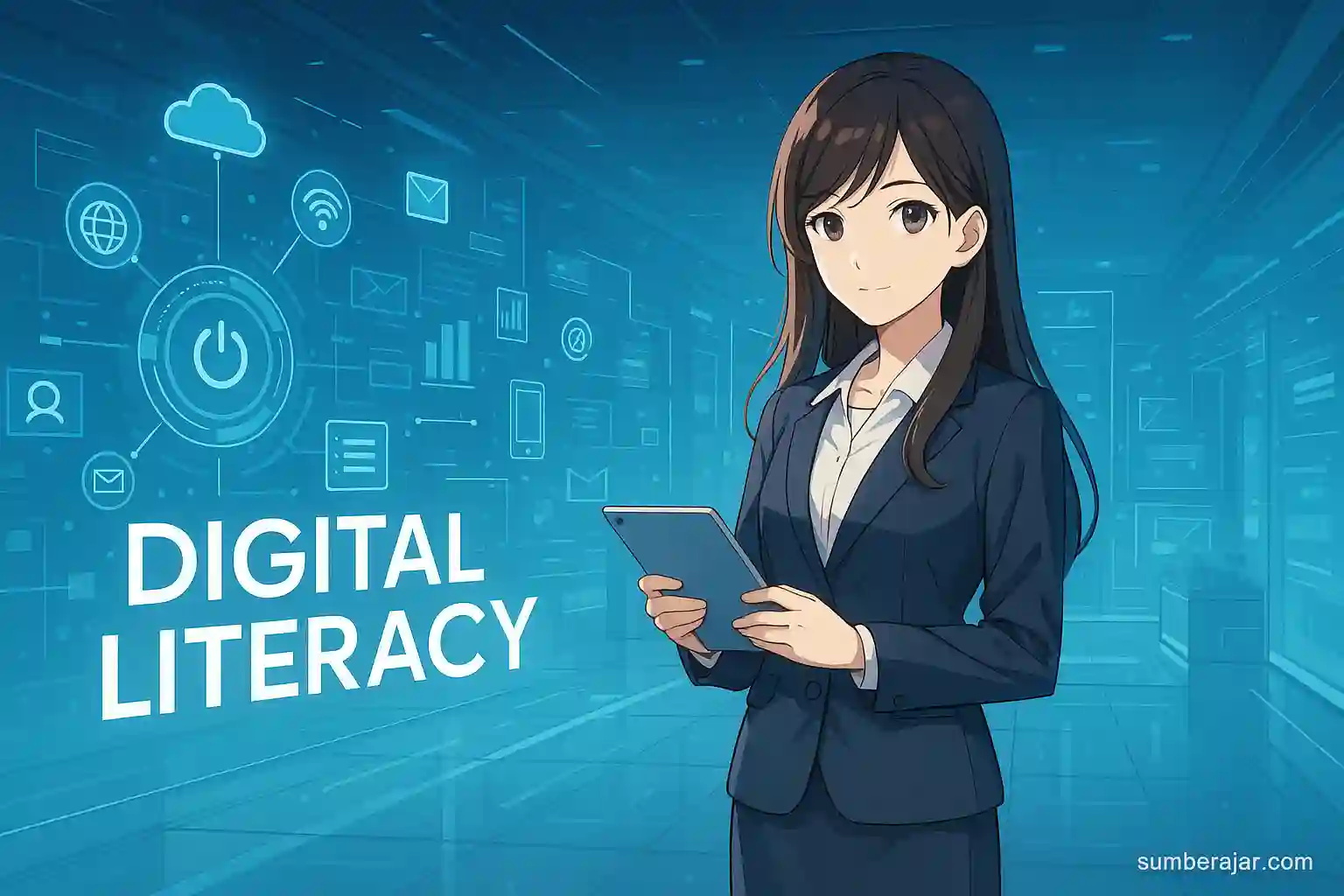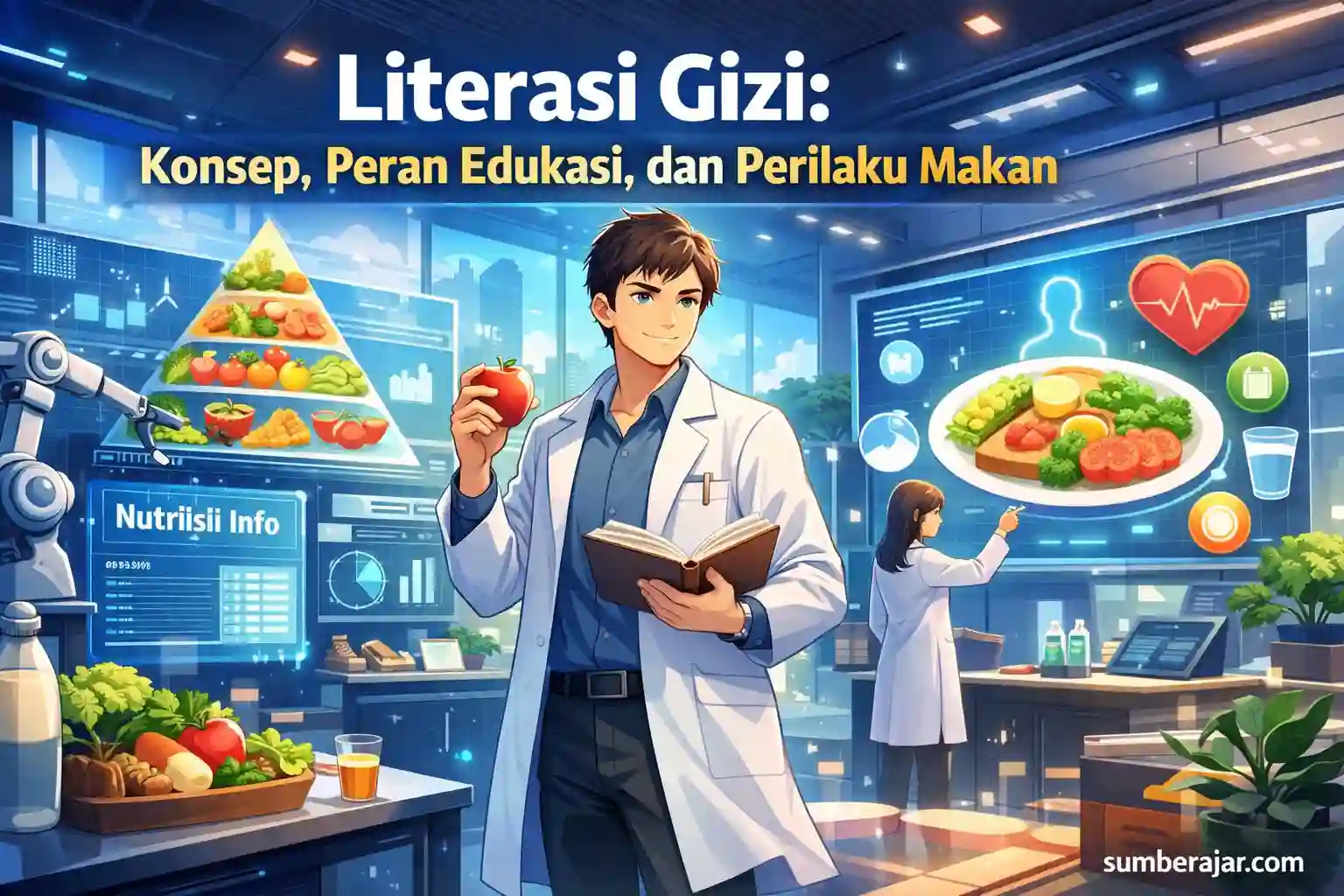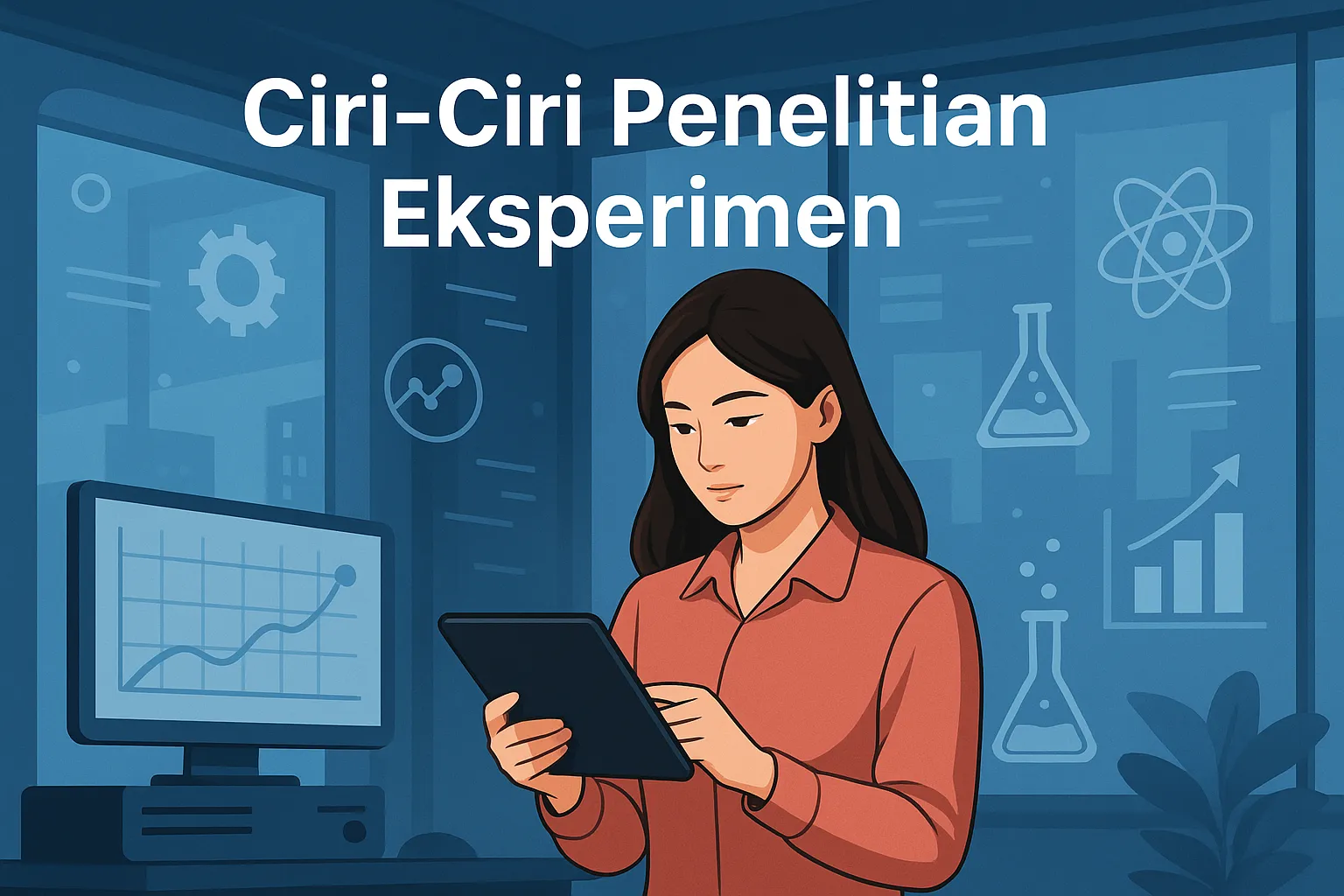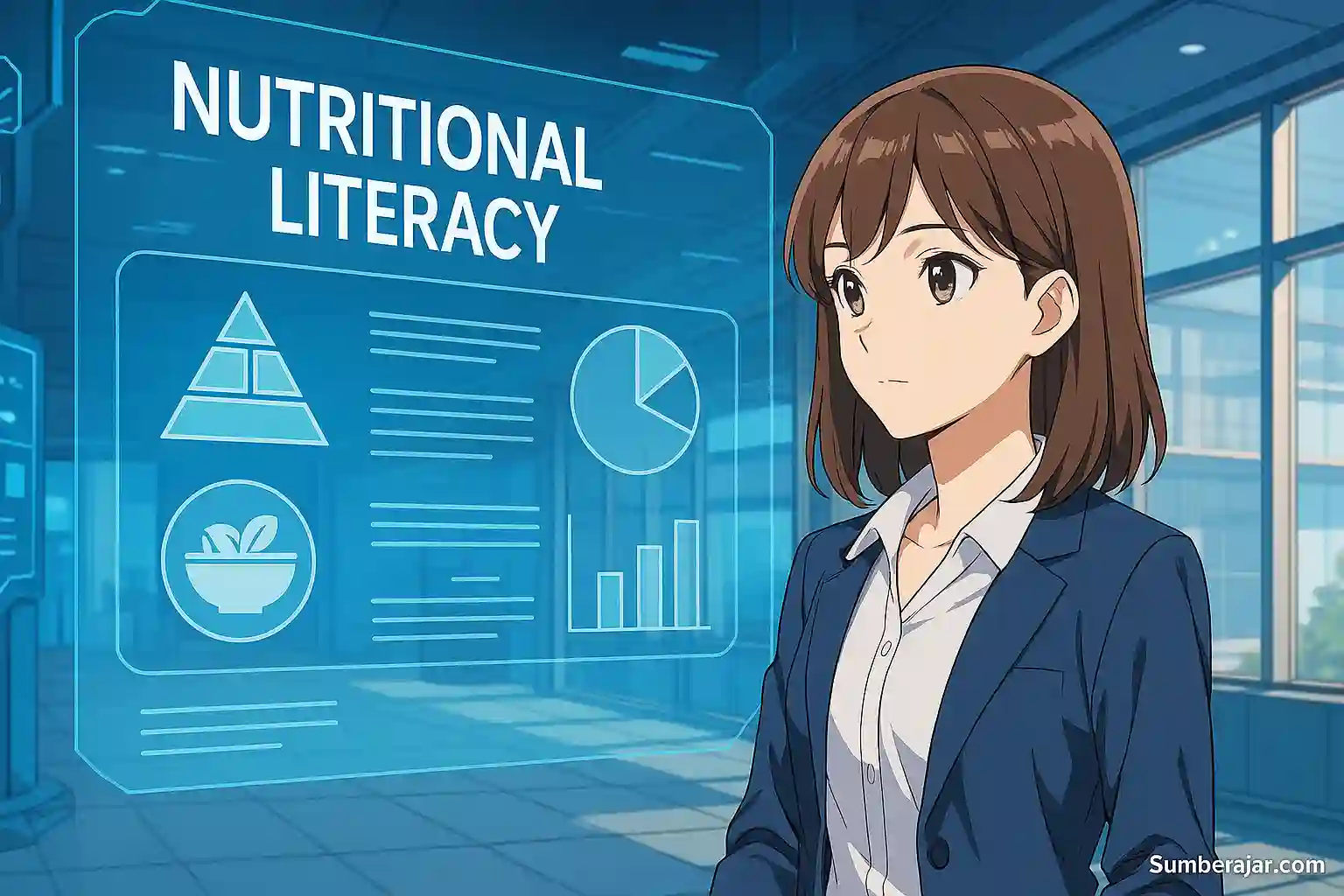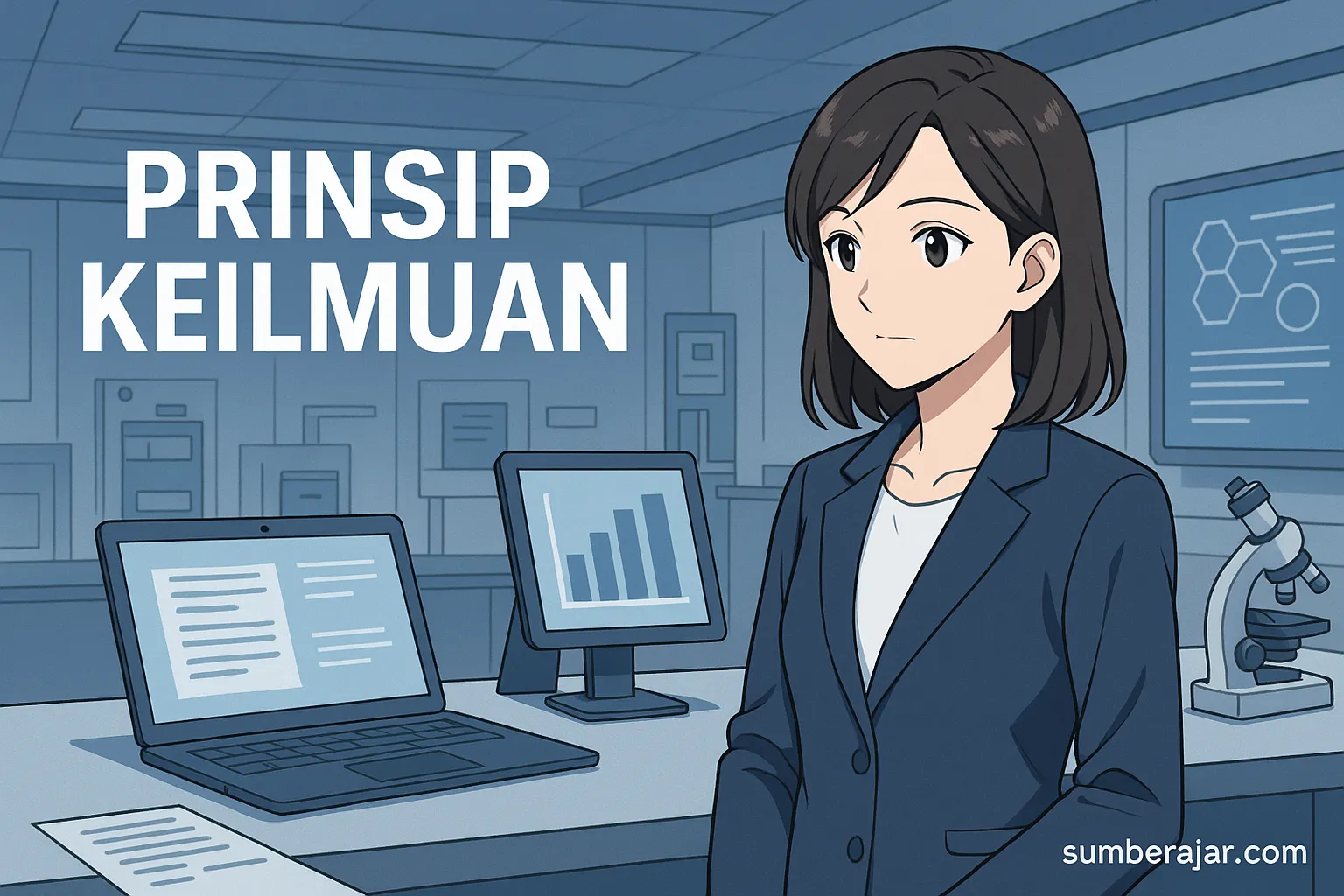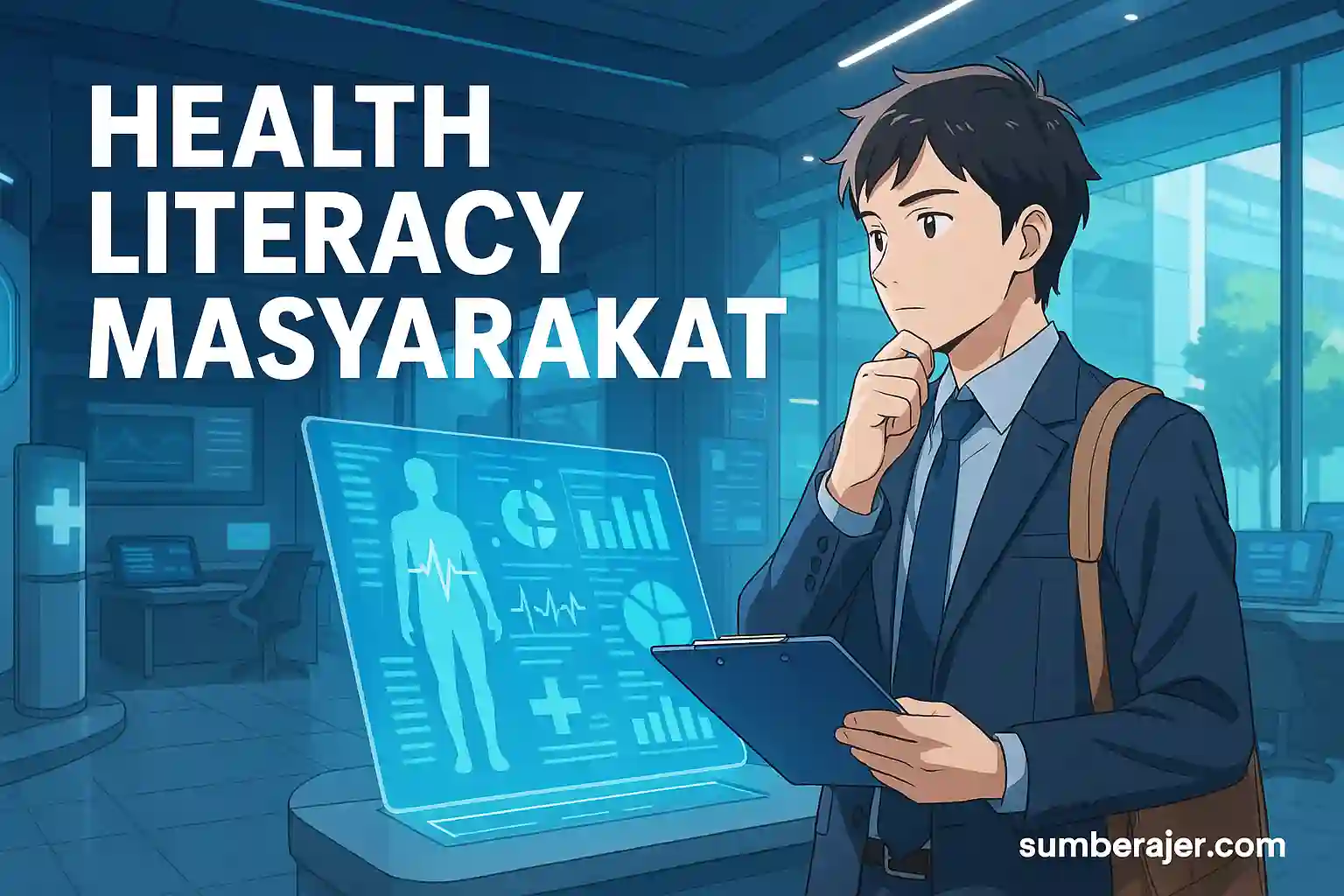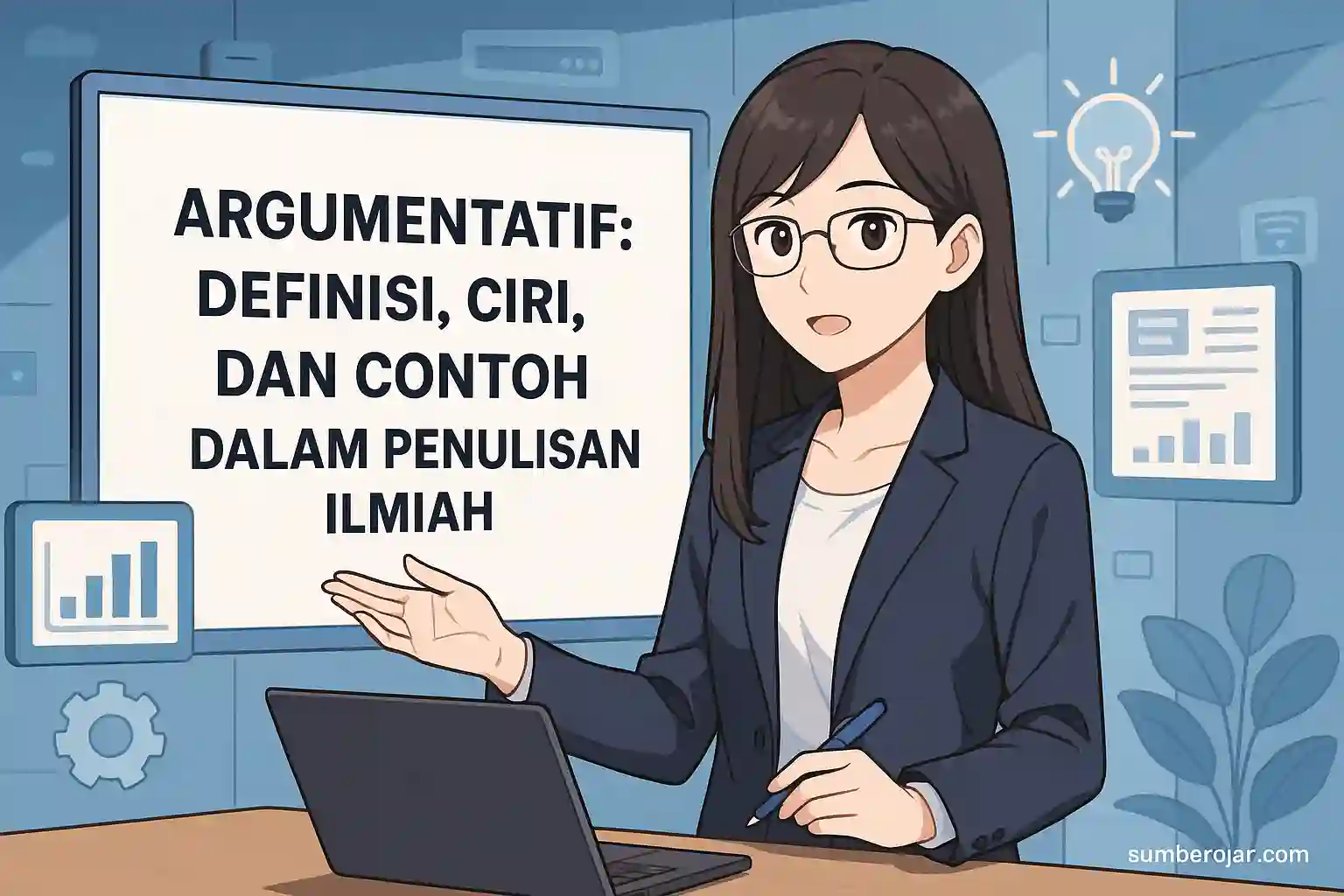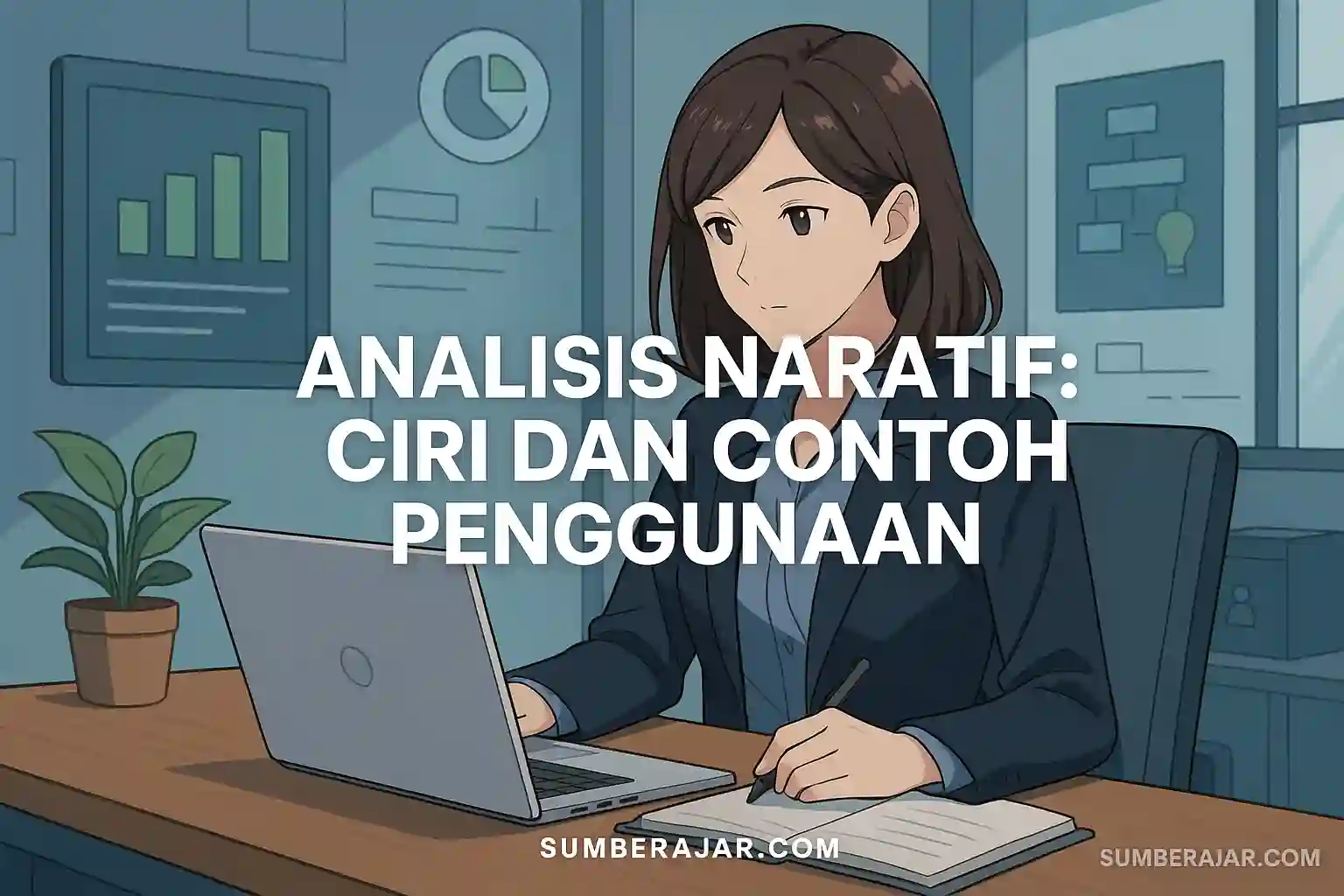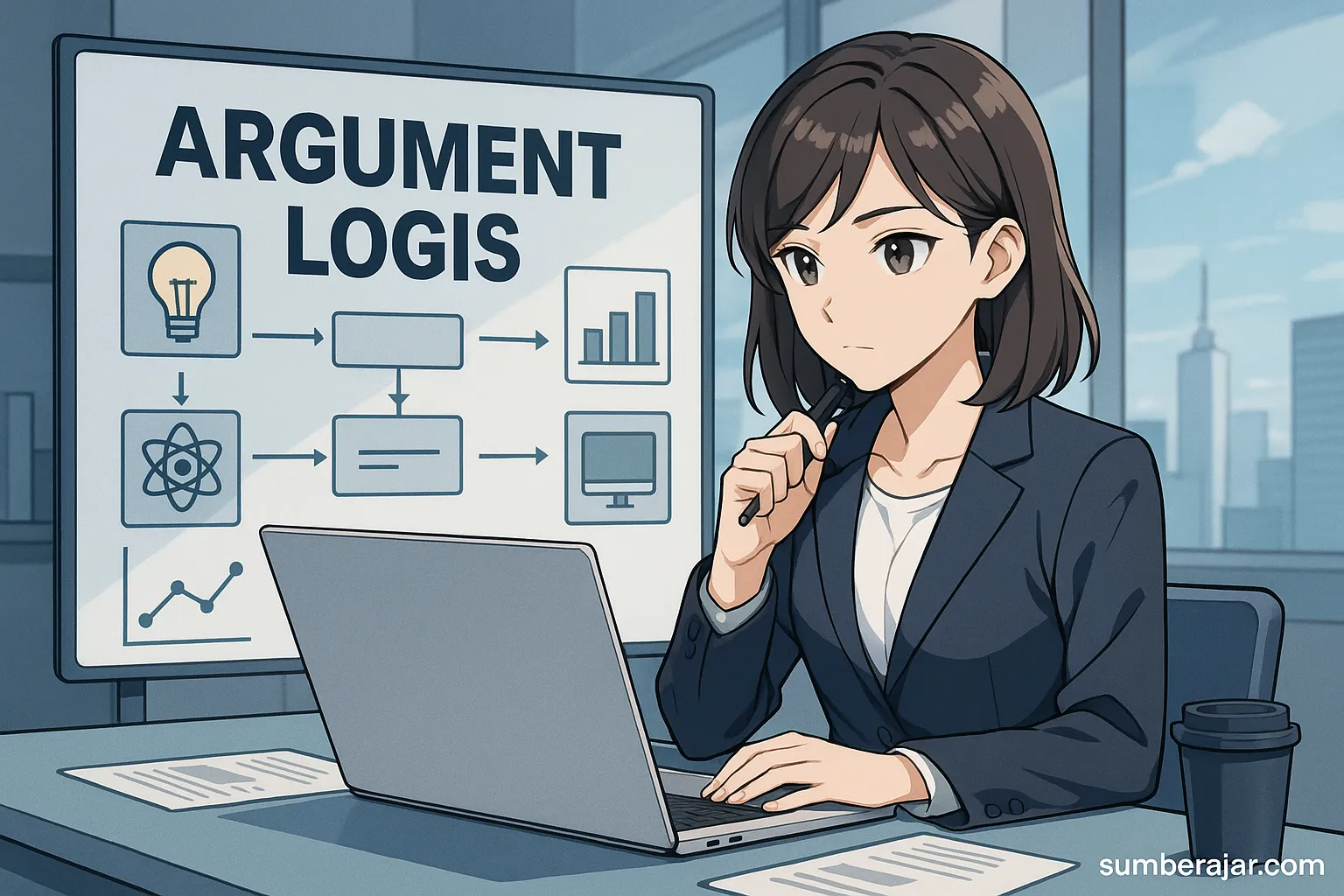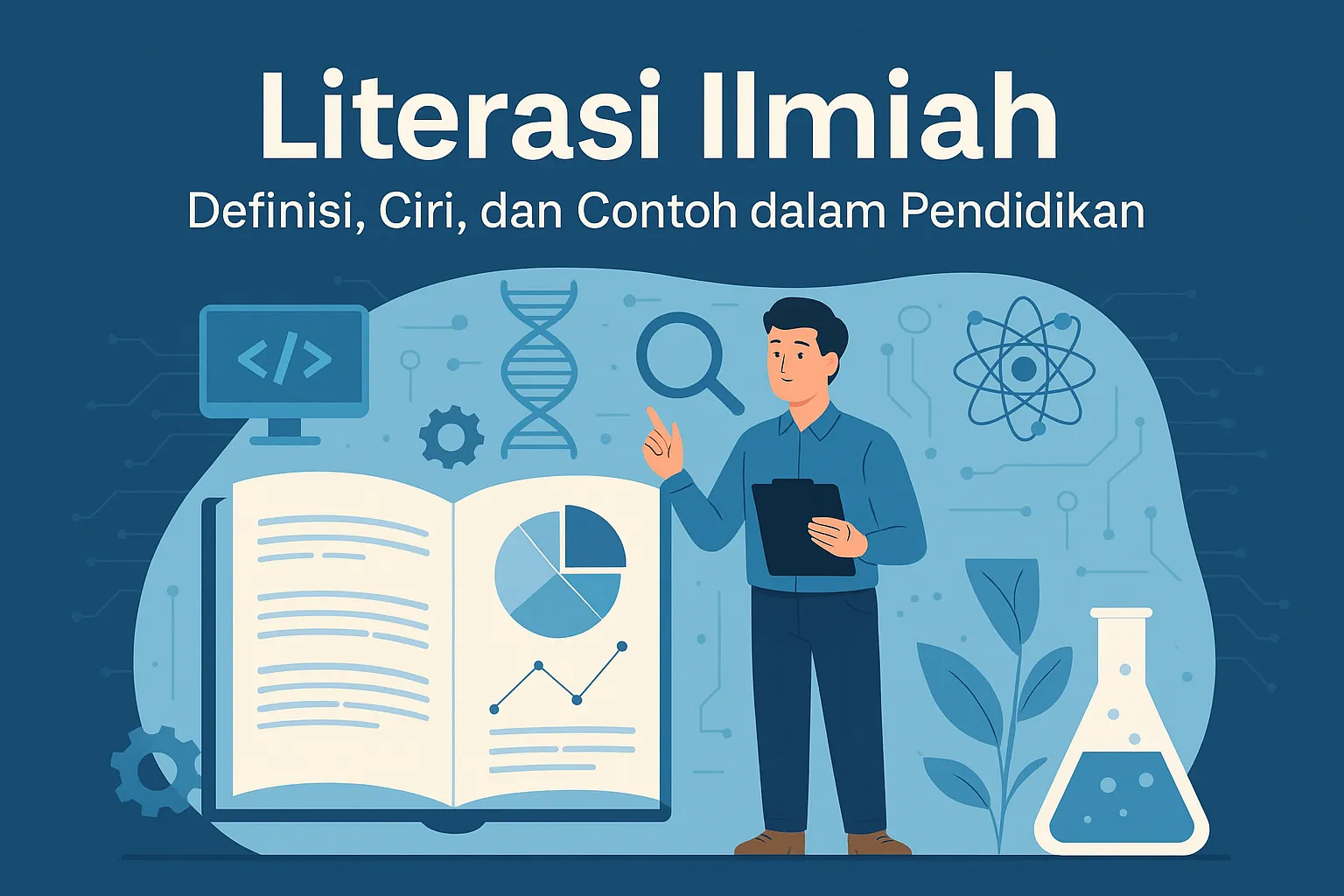
Literasi Ilmiah: Definisi, Ciri, dan Contoh dalam Pendidikan
Pendahuluan
Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, kemampuan berpikir kritis dan memahami informasi ilmiah menjadi sebuah kebutuhan utama. Dalam konteks pendidikan, muncul konsep literasi ilmiah yang semakin dianggap penting karena tidak hanya sekadar memahami fakta ilmiah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis bukti, serta membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang valid. Dengan latar inilah artikel ini hadir untuk menguraikan secara mendalam definisi literasi ilmiah, ciri-ciri utamanya, serta contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Pemahaman yang baik terhadap literasi ilmiah diharapkan menjadikan pendidik, siswa, dan pemangku kepentingan pendidikan lebih siap menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berbasis bukti.
Definisi Literasi Ilmiah
Definisi Literasi Ilmiah Secara Umum
Secara umum, literasi ilmiah (scientific literacy) dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memahami kandungan, proses, dan implikasi ilmu pengetahuan sehingga ia mampu berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat yang berbasis ilmiah. Sebagai contoh, menurut kerangka Organisation for Economic Co‑operation and Development (OECD) dalam program Program for International Student Assessment (PISA), literasi ilmiah adalah “kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti dalam rangka memahami dan membuat keputusan tentang dunia alam serta interaksi manusia dengan alam.” [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
Dalam riset pendidikan di Indonesia, literasi ilmiah sering dikaitkan dengan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi permasalahan sains, mengolah data, menarik kesimpulan berdasarkan bukti, dan mengevaluasi informasi ilmiah sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21. [Lihat sumber Disini - jppipa.unram.ac.id]
Dengan kata lain, literasi ilmiah lebih jauh dibanding literasi sains ataupun literasi baca-tulis biasa karena menekankan aspek proses ilmiah serta aplikasi pengetahuan dalam kehidupan. [Lihat sumber Disini - pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id]
Definisi Literasi Ilmiah dalam KBBI
Dalam kamus resmi bahasa Indonesia, istilah “literasi” dan “ilmiah” masing-masing memiliki makna yang dapat dirangkaikan untuk membantu pemahaman literasi ilmiah.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata literasi memiliki arti antara lain: “kemampuan menulis dan membaca”; “pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu”; “kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.” [Lihat sumber Disini - roboguru.ruangguru.com]
- Sementara kata ilmiah (berdasarkan penggunaan umum) berarti bersifat ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan (yakni sistematis, berasaskan bukti, dan metodis). Maka jika digabung, “literasi ilmiah” secara KBBI-terjemahan bisa dipahami sebagai: kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan untuk mengakses, memahami, menggunakan, serta mengkritisi informasi ilmiah dengan cara yang sistematis dan berbasis bukti.
Meskipun KBBI tidak menyediakan satu entri tunggal untuk “literasi ilmiah”, definisi ini dapat dibangun dari pengertian masing-kata di atas dan relevan digunakan sebagai kerangka awal.
Definisi Literasi Ilmiah Menurut Para Ahli
Berikut ini rangkuman definisi dari beberapa ahli dan organisasi riset/pendidikan yang cukup sering dikutip dalam kajian literasi ilmiah:
- Jon D. Miller , Miller dikenal sebagai pelopor pengukuran literasi ilmiah publik. Menurut beliau, literasi ilmiah mencakup “kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan menilai pengetahuan ilmiah, serta mengambil posisi yang rasional terhadap isu-sains dalam masyarakat”. [Lihat sumber Disini - en.wikipedia.org]
- American Association for the Advancement of Science (AAAS) , Dalam kerangka mereka, literasi ilmiah adalah kemampuan seseorang memahami bagaimana ilmuwan bekerja dan mencapai suatu kesimpulan ilmiah serta keterbatasannya. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
- OECD/PISA , Sesuai kerangka PISA, literasi ilmiah mencakup kemampuan: menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com]
- Khery, Y. (2022) , Dalam “Konseptualisasi Literasi Sains Mengacu pada Kerangka Sains PISA”, disebutkan bahwa “seseorang yang secara ilmiah literat akan senantiasa memperhatikan debat logis terkait sains dan teknologi yang memerlukan kompetensi: (1) menjelaskan fenomena secara ilmiah; (2) mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah; (3) menginterpretasikan data dan bukti”. [Lihat sumber Disini - download.garuda.kemdikbud.go.id]
- Nurfiani et al. (2025) , Dalam kajian tentang literasi ilmiah pada konsep ekosistem, dijelaskan bahwa literasi ilmiah mencakup pemahaman konsep sains, keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi ilmiah serta kecenderungan (disposition) untuk peduli terhadap isu sains/lingkungan. [Lihat sumber Disini - jurnal.ulb.ac.id]
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi ilmiah bukan hanya soal “mengerti sains”, tetapi melibatkan keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk menggunakan sains dalam konteks nyata agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.
Ciri-ciri Literasi Ilmiah
Agar pembaca lebih memahami secara operasional apa yang membedakan literasi ilmiah dari kompetensi lainnya, berikut adalah beberapa ciri utama literasi ilmiah yang dapat dijumpai dalam praktik pendidikan:
- Kemampuan menjelaskan fenomena secara ilmiah
Individu yang memiliki literasi ilmiah dapat menjelaskan mengapa suatu fenomena alam atau teknologi terjadi dengan menggunakan konsep dan prinsip sains, bukan hanya meniru fakta. Misalnya, siswa dapat menjelaskan mengapa air mendidih lebih cepat pada tekanan rendah saat naik gunung menggunakan konsep tekanan uap dan termodinamika. - Kemampuan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah
Ciri lainnya adalah kemampuan untuk menilai bagaimana penelitian atau penyelidikan ilmiah dilakukan , misalnya mengenali variabel, hipotesis, metode eksperimen, hingga keterbatasan penelitian , serta dalam kesempatan tertentu dapat merancang penyelidikan sederhana sendiri. Ini sesuai dengan kerangka PISA “evaluate and design scientific enquiry”. [Lihat sumber Disini - media.neliti.com] - Kemampuan menginterpretasikan data dan bukti ilmiah
Seseorang yang literat secara ilmiah dapat membaca grafik, tabel, hasil eksperimen, dan memahami implikasi serta keterbatasannya. Ia mampu menarik kesimpulan berdasar bukti, mengetahui bahwa kesimpulan ilmiah bersifat sementara dan terbuka perubahan. [Lihat sumber Disini - download.garuda.kemdikbud.go.id] - Keterkaitan pengetahuan sains dengan kehidupan nyata dan pengambilan keputusan
Literasi ilmiah bukan hanya dalam ranah kelas laboratorium, tetapi juga bagaimana seseorang dapat menggunakan pengetahuan sains untuk membuat keputusan sehari-hari: misalnya memilih pangan berdasarkan label gizi, menilai isu vaksin atau perubahan iklim secara kritis, atau memahami teknologi baru dan risikonya dalam masyarakat. [Lihat sumber Disini - pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id] - Sikap ilmiah dan kecenderungan (disposition) untuk berpikir kritis dan terbuka
Individu literat secara ilmiah memiliki sikap seperti: ingintahuan (curiosity), skeptisisme sehat terhadap klaim yang tak terbukti, keterbukaan terhadap perubahan bukti, kolaboratif dalam pengumpulan informasi, dan tanggung-jawab sosial untuk menggunakan pengetahuan sains secara etis. Bahkan kajian literasi ilmiah mencantumkan bahwa aspek disposition ini penting selain aspek kognitif dan keterampilan. [Lihat sumber Disini - jurnal.ulb.ac.id] - Kemampuan komunikasi ilmiah
Tidak hanya memahami sains sendiri, tetapi juga mampu menjelaskan kepada orang lain (atau masyarakat umum) konsep ilmiah, metode, risiko dan manfaat teknologi atau penelitian, serta menyampaikan pendapat berbasis bukti. Ini penting agar sains tidak terisolasi dan dapat memberi kontribusi sosial. Beberapa kajian menyebut komunikasi sebagai bagian dari literasi ilmiah. [Lihat sumber Disini - journal.unpas.ac.id] - Kontekstual dan reflektif
Ciri final: literasi ilmiah mencakup refleksi tentang dampak sains dan teknologi dalam masyarakat: efek lingkungan, etika penelitian, implikasi sosial-ekonomi. Sehingga literasi ilmiah membawa kesadaran bahwa sains memiliki konteks dan tanggung-jawab sosial. [Lihat sumber Disini - download.garuda.kemdikbud.go.id]
Dengan demikian, pendidikan yang benar-benar mengembangkan literasi ilmiah akan menekankan lebih dari sekadar penguasaan konten sains. Ia harus melibatkan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk menyelidiki, mengevaluasi, mengkomunikasikan, serta mengaitkan sains dengan dunia nyata.
Contoh Literasi Ilmiah dalam Pendidikan
Dalam praktik pendidikan,termasuk di sekolah menengah dan tinggi,literasi ilmiah dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi dan konteks. Berikut beberapa contoh nyata:
- Proyek penelitian siswa berbasis masalah nyata
Misalnya siswa diminta menyelidiki air limbah sekolah: mengukur pH, kandungan zat kimia, menarik kesimpulan berdasarkan data, lalu menyampaikan rekomendasi. Ini melatih ciri-ciri literasi ilmiah: menyelidik (design inquiry), menginterpretasi data, serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. - Penggunaan pertanyaan terbuka dalam pembelajaran sains
Guru mengajukan: “Mengapa suhu global meningkat dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem lokal kita?” Siswa kemudian mengeksplorasi data, membaca artikel ilmiah, mengevaluasi klaim, lalu mempresentasikan hasilnya. Dengan demikian tidak hanya memahami konsep, tetapi juga aspek evaluasi bukti dan implikasi sosial. - Analisis media dan isu sains/teknologi
Contoh di sekolah: siswa membaca artikel populer tentang vaksin atau perubahan iklim, lalu di kelas mendiskusikan validitas klaim, metode penelitian yang digunakan, konflik kepentingan, dan akhirnya menarik kesimpulan yang bersifat ilmiah. Ini menguatkan kemampuan komunikasi ilmiah dan sikap kritis. - Integrasi literasi ilmiah dalam kurikulum STEM
Banyak riset pendidikan Indonesia menyebut bahwa penguatan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sebaiknya disertai pengembangan literasi ilmiah agar peserta didik tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga proses ilmiah serta aplikasi dalam konteks pekerjaan dan masyarakat. [Lihat sumber Disini - sketsaunmul.co] - Tugas interpretasi data ilmiah sederhana
Misalnya siswa diberikan grafik tentang konsentrasi CO₂ dalam atmosfer dari tahun ke tahun. Siswa kemudian diminta menginterpretasi tren, mengaitkan dengan aktivitas manusia, dan memberikan rekomendasi tindakan. Ini menumbuhkan kemampuan interpretasi data dan pengambilan keputusan berbasis bukti. - Kolaborasi lintas disiplin dan masalah global
Contoh: proyek antar-kelas sains dan geografi untuk meneliti dampak urbanisasi terhadap aliran sungai. Siswa menggunakan metode pengambilan data, analisis statistik sederhana, lalu mempresentasikan hasil sekaligus mengaitkan dengan kebijakan sekolah atau komunitas. Dengan cara ini, literasi ilmiah dikaitkan dengan konteks sosial dan lingkungan.
Dalam semua contoh tersebut, yang penting adalah bahwa pendidikan menempatkan siswa sebagai aktor aktif dalam proses ilmiah , bukan sekadar penerima fakta , sehingga literasi ilmiah berkembang secara holistik.
Kesimpulan
Literasi ilmiah adalah kemampuan yang sangat krusial di era modern: bukan hanya memahami fakta sains, tapi juga mengerti bagaimana ilmu dibangun, bagaimana menyelidik, mengevaluasi, mengkomunikasikan dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah nyata serta membuat keputusan yang berlandaskan bukti. Dalam pendidikan, literasi ilmiah menuntut kurikulum dan pembelajaran yang menekankan proses sains, interpretasi data, sikap kritis, komunikasi ilmiah, dan konteks sosial-teknologi.
Dengan memahami definisi secara umum, definisi dari KBBI, dan definisi menurut para ahli, serta menerapkan ciri-ciri yang telah diuraikan, pendidik dan institusi pendidikan dapat merancang strategi pembelajaran yang benar-benar mengembangkan literasi ilmiah siswa. Contoh-contoh dalam pendidikan di atas dapat dijadikan acuan praktik agar literasi ilmiah tidak hanya menjadi jargon tetapi menjadi bagian nyata dari kompetensi peserta didik. Semoga artikel ini memberi gambaran yang komprehensif dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah maupun institusi pendidikan lainnya.